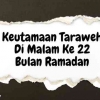Ada dua pertanyaan yang bisa diajukan saat memasuki sebuah warung makan. Pertama, apa yang ada (makanan) di warung, dan atau, kedua, apa yang terjadi (layanan) di warung.
Yang lazim adalah pertanyaan pertama. Karena tujuan seseorang datang ke warung makan tentulah untuk makan. Maka pertanyaan utamanya adalah ada jenis makanan apa saja yang disajikan di situ?
Pertanyaan kedua itu lazimnya datang kemudian. Terutama jika pelayan dirasa sangat bagus atau sebaliknya buruk sekali. Mengapa layanannya bagus, atau sebaliknya buruk?
Saya hendak fokus pada pertanyaan kedua ini. Dalam khazanah sosiologi, konsep inti pertanyaan itu adalah relasi dan interaksi sosial antara pewarung (pedagang) dan pelanggan (konsumen).
Dua konsep itu sejatinya adalah konsep utama dalam praktek warung makan. Intinya, pewarung membangun relasi yang seakrab mungkin dengan pelanggan demi mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru.
Itulah prinsip dasar warung makan Jawa (Tengah) yang saya pahami. Tapi dengan dua kasus berikut, saya ingin tunjukkan bahwa prinsip itu rupanya sudah mulai memudar.
***
Kasus A, di era pra-digital, pengalaman di satu warung makan di Salatiga tahun 1989, masih di lingkar kampus UKSW. Pelanggan utama warung ini adalah mahasiswa dan pegawai lajang yang kost di sekitarnya.
Suatu senja saya mampir makan malam di warung itu. Karena masih merasa lapar, walau sudah meludeskan sepiring nasi ayam, saya minta tambah pada simbok pemilik sekaligus operator warung.
Bukannya mendapatkan tambahan nasi ayam, alih-alih saya diingatkan simbok pewarung agar tidak tambah makanan. Sebab masih ada pelanggannya yang belum datang makan malam. Khawatir mereka tidak kebagian makanan nanti.
Simbok pewarung itu tidak ingin mengecewakan pelanggan yang sudah berupaya datang ke warung, berharap bisa makan, tapi tidak mendapatkan makanan.
Saya membathin, "Warung ini seperti ruang makan keluarga saja, setiap anggota harus mendapat baguan makanan."
***
Kasus B, di era digital, pada hari Jumat 28 Desember 2018 di Wijilan, jalur gudeg yang sohor di Yogyakarta. Sekitar pukul 11.00 siang, saya sekeluarga untuk pertama kalinya mampir ke sana. Karena anak bungsu saya, terpengaruh rekomendasi kuliner di dunia maya, ingin merasakan langsung makan gudeg di salah satu warung gudeg legendaris di jalan itu.
Perjalanan ke sana dari Stasiun Tugu adalah perjuangan menembus kemacetan Yogya yang kini rupanya serupa Jakarta. Tapi, saya pikir, sepadanlah mengingat nikmatnya gudeg di warung kondang Wijilan itu. Bayangan saya seperti itulah.
Tiba di Wijilan, kami langsung menghampiri warung gudeg kondang itu. Belum juga kaki melangkah masuk warung, salah seorang pramusaji langsung setengah berteriak, "Habis!" Sependek itu teriakannya. Tanpa rasa sesal. Apalagi kata "maaf".
Karena sekitar 25 meter dari warung itu ada satu lagi warung dengan nama yang sama, kamu coba peruntungan ke sana. Hasilnya sama, jawaban tanpa rasa empati, "Habis!"
Kami sekeluarga sungguh kecewa. Susah-payah datang ke Wijilan untuk makan gudeg. Dalam kondisi perut lapar pula. Tapi hanya mendapatkan penolakan seperti itu.
Yang menyakitkan, kata "Habis!" itu hanya berlaku untuk calon konsumen seperti kami yang sudah susah-payah datang ke warung itu untuk makan. Faktanya, di warung itu saya lihat masih banyak gudeg dan kelengkapannya. Tapi para pelayan sibuk mengemasnya ke kotak-kotak makanan. Rupanya, stok gudeg di dua warung itu sudah habis dipesan orang di luar sana. Sehingga yang datang ke warung itu malah tidak kebagian.
Saya membathin kesal, "Untuk apa buka warung untuk melayani pelanggan yang tidak datang ke warung?"
***
Prinsip asli warung adalah melayani pembeli yang datang secara fisik. Ada komunikasi transaksional yang bersifat langsung antara pewarung dan pembeli. Jika transaksi itu berulang secara terpola dalam waktu lama, maka hubungan yang terjadi adalah pewarung-pelanggan. Komunikasi menjadi lebih akrab.
Pada warung kasus A, pewarung memperlakukan pelanggan sebagai anggota keluarga, tepatnya sebagai "anak-anak" yang harus dijamin ketersediaan makanannya. Karena itu warung makannya menjadi semacam ruang makan keluarga. Para pelanggan umumnya saling kenal, karena itu kegiatan makan di situ menjadi semacam waktu makan keluarga.
Pewarung sangat menghargai dan menjamin hak makan dari para pelanggannya. Oleh karena itu dia selalu menakar volum makan setiap pelanggan, agar semua pelanggan kebagian makanan. Jangan sampai ada pelanggan yang kecewa tidak mendapat makanan.
Pada warung kasus B, hubungan pewarung dan konsumen sudah mengarah pada hubungan penjual dan pembeli lazimnya. Tidak teramati lagi hubungan akrab yang hangat, melainkan hubungan bisnis yang cenderung dingin. Cukup dengan kata "Habis!", tanpa sesal, untuk menolak calon konsumen yang datang. Urusan selesai.
Warung kasus B tidak berorientasi kepuasan lagi seperti kasus A. Orientasinya adalah produktivitas, atau ringkasnya "omset" dan "laba". Menjual sebanyak mungkin demi laba sebesar mungkin.
Karena itu, jika fungsi warung kasus A adalah wahana komunikasi (antara pewarung dan pelanggan), maka fungsi warung pada kasus B adalah wahana penjualan semata. Mengutamakan siapa yang pesan lebih dulu dan mengutamakan pesanan partai besar. Tidak masalah jika konsumen yang datang langsung ke warung tidak kebagian. Yang penting dagangan habis terjual.
Kondisi kasus B ini dikatalisasi pula oleh teknologi komunikasi digital. Orang cenderung menjadi "malas" datang ke warung, karena lebih praktis pesan lewat aplikasi gadget. Warung kasus B sudah mengarah ke bisnis online yang lagi ngtren. Tidak salah sebenarnya, kecuali filosofi dasar "warung Jawa sebagai locus komunikasi" sudah terkikis di situ.
Sebenarnya pengikisan nilai filosofis itu bisa di atasi dengan memisahkan warung offline dengan warung online. Dengan begitu, pelanggan atau konsumen tradisional yang lebih nyaman datang dan makan langsung di warung, tak terampas haknya oleh konsumen online.
Saya tak keberatan dengan integrasi warung tradisional Jawa ke era bisnis online. Tapi saya merasa nelangsa, khawatir nilai-nilai "kekeluargaan" itu sudah mulai memudar dari budaya layan warung makan Jawa. Padahal, nilai itulah kekuatan sekaligus kekhasan warung makan Jawa.
Warung Jawa terutama bukan soal rasa makanan tapi soal rasa hati. Setidaknya begitu menurut saya, Felix Tani, petani mardijker, sedang bernostalgia di Jawa Tengah.***
Solo, 31 Desember 2018