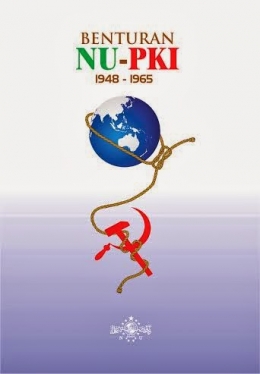[caption id="attachment_322890" align="aligncenter" width="342" caption="http://mosleminfo.com/"][/caption]
Awalnya, ketika saya membaca berita bahwa NU menerbitkan buku putih berjudul “Benturan NU-PKI 1948-1965” langsung ada rasa ketertarikan untuk segera membacanya. Namun pada akhirnya banyak rasa kekecewaan pada buku tersebut. Kekecewaan pertama yang muncul adalah buku tersebut hanya setebal 200-an halaman. Saya sebenarnya mengharapkan isi buku lebih tebal sehingga dapat saya baca lebih lama dari ‘menikmati secangkir kopi’. Bukan tanpa alasan, karena untuk peristiwa serumit itu penjelasan sebuah buku kecil akan sangat mengambang. Benar juga, banyak hal yang mesti saya kritisi dari isi buku tersebut.
Saya memiliki latar belakang yang dapat dibilang cukup ‘aneh’ untuk lingkungan tempat saya hidup. Saya terlahir dari lingkungan NU yang kental, memiliki ayah seorang pengurus NU dan salah satu tokoh agama setempat, hingga menghabiskan waktu cukup lama di pesantren NU. Namun ketika kuliah, saya sempat terlibat dalam organisasi mahasiswa beraliran ‘kiri’. Di kemudian hari, saya mulai merasakan manfaat akan latar belakang tersebut. Salah satunya, menyikapi peristiwa sekitar tahun ’65 secara objektif. Tulisan di bawah bukan untuk menyinggung salah satu kelompok tertentu, namun murni bersifat opini hasil pemikiran objektif yang saya lakukan.
Buku putih yang diterbitkan oleh tim dari NU tersebut amat saya sayangkan karena memiliki analisis yang dangkal. Pada awal buku memang dijelaskan bahwa penerbitan buku tersebut adalah sebagai bentuk reaksi pihak NU yang merasa tersudutkan atas keterlibatan organisasi Islam tersebut dalam pembantaian ribuan (jutaan?) anggota PKI. Terutama setelah majalah Tempo edisi oktober 2012 mengulas hal tersebut dalam edisi spesial. Saya sangat menyesalkan penggunaan istilah-istilah seperti ‘orientalis’ dan ‘Indonesialis’ yang justru menggambarkan buku tersebut, atau tim penulisnya, merasa ‘alergi’ terhadap orang-orang luar yang mencoba meneliti masalah ini. Menurut saya, cukup dalam buku tersebut menyebut istilah ilmuan atau menyebut nama mereka saja. Penulis buku seakan tidak percaya dengan hasil penelitian mereka secara objektif, namun lebih seperti sikap sentimen. Dasar pemikiran dan pandangan kedua pihak (penulis dan peneliti luar) tentu saja akan berbeda. Mereka tidak menjadi bangsa yang terlibat langsung dengan peristiwa itu. Namun dalam hal ini, saya berpikir para ilmuan dari luar itu lebih objektif karena tidak memiliki ikatan emosional dengan peristiwa tersebut. Sebagai contoh untuk memahami pola pikir saya, pembaca dapat membayangkan bagaimana pandangan orang Jawa terhadap peristiwa Sampit atau orang Hindu terhadap peristiwa Ambon dan Poso.
Banyak yang telah mengetahui keteribatan CIA dalam peristiwa seputar tahun 1965, namun buku putih ini tidak menyinggungnya. Termasuk kepentingan ekonomi-politik negara barat terhadap Indonesia pada waktu itu. Penggambaran ideologi Marxisme juga terkesan sangat dangkal. Hanya menonjolkan sisi atheisme yang memang menjadi salah satu dasar ideologi materialisme dialektis mereka. Namun hal ini dapat saya maklumi karena NU merupakan organisasi keagamaan. Meski begitu, alangkah lebih baik apabila analisa kondisi sosial-politik waktu itu dapat dilengkapi dengan fakta tersebut. Terlebih lagi, apabila penjelasan mengenai ideologi komunisme dijelaskan lebih mendetail. Hal itu akan memberikan pemahaman mengenai latar belakang aksi sepihak program land reform mereka.
Di lain pihak, saya menganggap para pimpinan CC PKI waktu itu (dan sebelum 1965) banyak mengambil kebijakan partai yang sembrono. Tan Malaka merupakan salah satu pimpinan yang tidak suka dengan cara-cara PKI tersebut, sehingga dia ‘ditendang’ keluar dan mendirikan partai Murba. Kesalahan membaca situasi yang mereka lakukan, dengan mengadopsi revolusi Soviet, justru menghantarkan mereka pada kehancuran dan genosida. Masyarakat industrial Rusia tentu saja berbeda dengan masyarakat agraris Indonesia dimana sebagian masih semi-feodal. Pernyataan perang mereka terhadap Tuhan dan agama merupakan suatu tindakan bodoh. Padahal waktu itu, dan masa sebelumnya, banyak kalangan religius dan bahkan pemuka agama yang menjadi kader PKI. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Haji ‘Merah’ Misbah di jawa tengah.
Kesalahan lain adalah ‘memukul rata’ ideologi kapitalisme dan komunisme yang hanya digambarkan berasal dari akar sejarah filsafat yang sama dan berakhir dengan atheisme yang sama pula. Hal ini terasa mengecewakan ketika ditambah kesan negatif atas istilah humanisme. Atheisme dan humanisme tentu saja merupakan dua hal yang jauh berbeda. Religiusitas manusia tanpa rasa humanisme tenta akan melahirkan sikap kaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Sahabat Umar ibn. Khattab telah memberikan contoh nyata mengenai humansme yang sangat diperlukan untuk menjaga ajaran Islam dari arus zaman. Saya tentu tidak perlu menunjuk peristiwa mana yang melibatkan beliau untuk mencontohkan hal ini, pembaca pasti mengerti akan sisi kebijaksanaan dan kemanusiaan Umar ibn. Khattab dibalik ketegasan beliau.
Masih banyak lagi hal perlu saya kritisi dalam buku ini, namun yang lebih menarik bagi saya adalah bagian akhir buku yang mencoba menjelaskan sikap Gus Dur terhadap PKI dan para eks-anggotanya. Ketika membaca bagian ini, kekecewaan saya seakan terguyur hanya dengan membaca nama Gus Dur. Beliau memang orang yang selalu membuat saya kagum sejak kecil yang hanya mengenal beliau sebagai ‘wali kesepuluh’ hingga saat saya mulai mempelajari pemikiran beliau. Penulis buku memberi saya kesan jangga terhadap tafsiran beliau atas permohonan maaf Gus Dur serta wacana pencabutan TAP MPR tahun 1966 tentang larangan ajaran Marxisme. Gus Dur pada saat itu memang sedang mengusahakan rekonsiliasi nasional dengan para eks-tapol. Hak-hak mereka mulai dipulihkan. Meskipun permintaan maaf Gus Dur sendiri saya pikir tidak mewakili NU ataupun Negara, melainkan dapat saya katakan bersifat personal. Pernyataan Pramoedya waktu itu juga merupakan bentuk ketidak-puasan atas hal tersebut. Pram menginginkan Gus Dur meminta maaf sebagai kapala negara dan segera melakukan tindakan hukum. Somasi yang ditujukan pada Gus Dur waktu itu memang resiko beliau sebagai presiden pertama yang meminta maaf secara terbuka atas tragedi tersebut. Hal ini saya rasa tidak perlu dijadikan persoalan besar mengingat siapa pun presidennya, hingga saat ini, tidak akan mampu berbuat demikian. Meskipun saya juga merasa kecewa atas somasi tersebut.
Mengenai pencabutan TAP MPR tahun 1966, penulis buku juga kurang menjelaskan secara mendalam. Bagi saya, upaya Gus Dur tersebut di luar rekonsiliasi yang beliau lakukan. Namun lebih pada hak asasi manusia dan kebebasan berpikir. Seorang dengan intelektualitas seperti beliau tentu merasa kurang nyaman apabila kebebasan dalam hal akademik dibatasi oleh aturan dari pemerintah. Saya pernah menuliskan opini tentang betapa pengorbanan seorang Gus Dur dalam mendidik bangsa inidemikian tak ternilai. Ini merupakan salah satunya. Sebagai analogi, seorang anak tidak akan selamanya memutuskan baik-buruk suatu perkara samata atas pertimbangan orang tuanya. Demikian pula bangsa ini yang tidak akan mampu tumbuh menjadi bangsa yang besar jika kebebasan berpikir terkekang oleh pemerintahnya sendiri.
Terakhir, saya cukup mengapresisi penjelasan rekonsiliasi alamiah yang dilakukan oleh NU dan bangsa Indonesia secara umum. Hal ini juga dituliskan dalam bagian akhir buku. Saya pikir, peristiwa serumit itu tidak akan pernah menemui titik terang. Jalan terbaik adalah dengan memendam dalam-dalam memory peristiwa tersebut dan seiring pergantian generasi tidak akan ada lagi stigma negatif ataupun dendam. Tidak peduli komnas HAM, kontras, LSM lain atau siapapun, semuanya harus mulai belajar memandang ke depan dan membiarkan masa lalu tertinggal jauh dibelakang hingga tak lagi terlihat. Itu adalah rekonsiliasi terbaik daripada sekedar menunggu permintaan maaf kedua pihak. Negara komunis terbesar, Rusia dan China, sudah lama melupakan komunisme dan melaju menjadi bangsa yang maju berbalut perekonomian bangsa (ekonomi kapitalisme, bukan komunisme) yang kokoh. Sampai kapan kita terus berkutat dengan istilah ‘laten komunis’ ini????
Biarkan kami menjadi bangsa yang utuh kembali....!!!