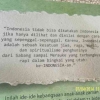Peran psikologi dalam menangani persoalan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sudah sering diangkat menjadi topik-topik seminar dan konferensi psikologi, baik dalam subdisiplin psikologi sosial, klinis-makro, maupun subdisiplin yang lain. Psikologi, sebagai ilmu yang bersinggungan dengan dimensi-dimensi manusia, mencoba berkontribusi mulai dari merumuskan definisi “bangsa” sampai dengan melakukan penelitian dan intervensi sosial solutif terhadap permasalahan bangsa. Gejala ini sangat menggembirakan karena hal ini menunjukkan bahwa kita terus-menerus mempertanyakan diri kita sebagai sebuah bangsa, sebuah prakondisi akan perkembangan yang sehat, sekaligus melihat dan mencoba menjangkau kemungkinan-kemungkinan bagaimana bangsa kita akan “menjadi”.
Dalam salah satu definisi dalam kerangka kewargaan (civic), seperti bangsa Indonesia, basis kesatuan bangsa dikonsepsikan berdasarkan keterlibatan sukarela para warga (citizen)-nya dalam prinsip ideologis dasar, seperti perasaan sebagai warga (sense of citizenship), komitmen terhadap lembaganya, serta partisipasi yang diminta ideologi dan lembaga-lembaga itu (Meeus, Duriez, Vanbeselaere, & Boen, 2010, dalam Juneman & Meinarno, 2012). Lebih lanjut, apabila diperlukan adanya perubahan ideologi, maka konsensus negosiatif antar warga dapat memungkinkan hal tersebut. Dalam hal ini, keanggotaan kelompok dapat diperoleh siapapun yang memenuhi secara demokratis kriteria yang ada. Dari aspek psikologis, bangsa (Volk, nation) merupakan komunitas yang diikat oleh persepsi-persepsi subjektif yang melihat dirinya sebagai bagian dari bangsa itu, dan karenanya bangsa memiliki jiwa (Volksgeist, national spirit; Volksseele, national psyche), yang sesungguhnya bukan berasal dari kesamaan kesukuan, bahasa, atau kekerabatan, melainkan berasal dari identifikasi psikologis pribadi-pribadi yang bersama-sama meleburkan diri dengan bangsa tersebut (Lazarus & Steinthal, dalam Rosenberg, 2008).
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka setiap psikologi (diandaikan bahwa psikologi itu tidak singular) yang mengindikasikan dan mempreskripsikan kerekatan perasaan dan komitmen warga dengan komunitas bangsa yang diimajinasikannya layak disebut sebagai Psikologi Kebangsaan. Mengapa Psikologi Kebangsaan menjadi penting sebagai suatu bidang studi dewasa ini? Sebagaimana kita ketahui, bangsa menghadapi berbagai persoalan sepanjang sejarahnya. Sebagian besar persoalan, apabila ditilik, sesungguhnya merupakan persoalan bagaimana bangsa berperilaku. Psikologi sebagai ilmu yang berhasrat menemukan hukum-hukum perilaku, apabila sukses dalam misinya itu dalam konteks kolektif-kebangsaan, akan berkontribusi dalam memahami, menjelaskan, serta meminimalisasikan bahkan menyelesaikan berbagai varian persoalan bangsa yang timbul, mungkin timbul, dan pernah timbul dalam berbagai jenis dan skalanya. Dalam konteks Indonesia, psikologi kebangsaan menjadi semakin relevan karena jika kita berbicara tentang peran Indonesia dalam kancah internasional, yang pada 2015 semakin faktual dengan masuknya dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (di mana Indonesia merupakan bagiannya), maka bukan hanya psikologi internasional yang perlu dikuasai, namun justru psikologi bangsa kita sendiri lah yang pertama-tama perlu digali dan dipetakan karakteristik, kekuatan dan kerentanannya, sambil menghubungkan diri dan berdinamika dengan jejaring internasional.
Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana metode mengenali psikologi bangsa? Wilhelm Wundt, Bapak Psikologi, pernah menyatakan bahwa perkembangan jiwa kolektif dapat diakses melalui bahasa, mitos, dan adat (Wundut, dalam Rosenberg, 2008). Implikasinya, psikologi kebangsaan perlu berkolaborasi dengan ilmu linguistik, mitologi, dan etnologi (juga ilmu-ilmu fisik, dan sosial lainnya, termasuk psikohistori, cf. Bendersky, 1988) dalam mempelajari kehidupan mental bangsa. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa psikologi kebangsaan tidak berbicara tentang penjumlahan psikologi sekumpulan individu yang menjadi anggota sebuah bangsa, juga tidak berbicara tentang psikologi massa yang statis dan dapat diprediksikan dalam kondisi tertentu. Psikologi kebangsaan merupakan sebuah gestalt (totalitas) interaksi yang menampakkan konfigurasi baru dari jiwa-jiwa individu-individu tersebut yang selalu tetap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan perkembangan personal dan situasional yang dapat mengubah gestalt itu. Yang berinteraksi bukan hanya aspek sadar, tetapi juga aspek-aspek tidak sadar; bukan hanya aspek masa sekarang, tetapi juga aspek historis dan aspek visioner; bukan hanya aspek individu tetapi juga kelembagaan. Ringkasnya, psikologi kebangsaan berbicara mengenai “perjalanan” identitas dan bangunan ingatan dari individu-individu dan lembaga-lembaga menuju kolektivitas bangsa, dari bangsa pada masa yang lalu menjadi bangsa pada masa sekarang dan “potensi menjadinya” bangsa di masa yang akan datang. Tidak heran, Woodworth (1912) sejak lama mengingatkan bahwa kita perlu berhati-hati dalam melakukan generalisasi tentang karakter dan perilaku bangsa. Mengapa? Sebab bangsa selalu dalam kondisi “bergerak” yang berada dalam “ketegangan” antara sosiologi masyarakat, kondisi alam, dan psikologi individual anggota bangsa. Mengambil kesimpulan tentang jiwa bangsa sangatlah tidak mudah; kita bisa tergelincir pada simplifikasi yang boleh jadi tidak akan menambah sesuatu pemahaman apa mengenai bangsa kita, melainkan hanya akan memperburuk arah perjalanan bangsa. Oleh karenanya, pencatatan yang tekun, kaya, dan hati-hati mengenai kasus-kasus perilaku anggota bangsa sambil menyandingkannya dengan hipotesis mengenai situasi umum jiwa bangsa, bahkan yang menunjukkan konflik pemahaman antar keduanya, menjadi sangat penting untuk tidak terjebak dalam penyederhanaan dimaksud.
Guna memahami psikologi kebangsaan, di samping menyelidiki “perjalanan” dari individualitas menuju kolektivitas-bangsa sebagaimana disebutkan di atas, dari arah lain kita juga dapat mendekatinya dengan cara menyorotnya dari psikologi kelompok yang lebih luas, seperti Psikologi Asia, Psikologi Asia Tenggara, dan Psikologi ASEAN, di mana bangsa Indonesia menjadi bagiannya. Mengapa pendekatan ini dapat dibenarkan? Oleh karena, perlu kita akui, bahwa psikologi sebagai sebuah ilmu tidak bebas nilai (Kim, 1995), dan bangsa kita membagi sejumlah nilai yang sama (shared values) dengan bangsa-bangsa yang terdekat di sekeliling kita. Sebagai contoh, Psikologi Masyarakat Asia dalam salah satu simpulnya bersifat relasional, kontekstual, dan kolektif (Kim, 1995), sesuatu yang nampaknya juga eksis dalam masyarakat kita. Yang patut kita waspadai, sekali lagi, adalah perampatan (generalisasi) yang berlebihan. Meskipun sejak membuminya Psikologi Asia dengan hadirnya Asian Psychological Association (APsyA), Association of Behavioural Researchers on Asians (ABRA), ASEAN Regional Union of Psychological Societies (ARUPS), dan Asian Association of Social Psychology (AASP), kita memiliki “teropong” dan “lensa” psikologi baru untuk melihat masyarakat Indonesia, kita perlu menyadari bahwa teropong dan lensa itu juga tidak selalu memadai dan meminta kita berkontribusi, melalui Psikologi Kebangsaan, untuk meningkatkan kecanggihan segenap teknologi psikologi kita itu agar lebih peka dan presisif dalam pernyataan kita mengenai psikologi kita sendiri.
Hal lain yang perlu memperoleh perhatian kita adalah bahwa, sebagaimana psikologi yang tidak singular dengan berbagai asumsi epistemologis yang dapat saling “bertabrakan” (Juneman, 2013), demikian pula Psikologi Kebangsaan. Psikologi Kebangsaan jangan diharapkan untuk menghasilkan profil kejiwaan dan perilaku bangsa yang berlaku bagi semua anggota bangsa. Dalam salah satu studi Psikologi Kebangsaan yang sudah dimulai sejak lama di Tiongkok, Boorman dan Boorman (1967) menemukan bahwa Masyarakat Tionghoa memiliki beberapa deskripsi psikologis yang kontradiktif, yang dipengaruhi antara lain oleh perbedaan karakteristik provinsial. Kontradiksi-kontradiksi (kalau tidak “interlocking realities”, William James dalam Boorman & Boorman, 1967) yang mesti dianggap sebagai paradoks dalam Psikologi Kebangsaan sangat dimungkinkan, dan justru jangan dianggap sebagai kegagalan Psikologi itu, melainkan merupakan kenyataan yang membawa kita kepada pemahaman psikologis yang semakin mendekati kebenaran. Psikologi Kebangsaan adalah psikologi yang realistis, yang tidak duduk di “menara gading”, yang cair, yang tidak formalistik.
Saudara Imam Ratrioso telah mencanangkan bukunya "Rakyat Nggak Jelas: Potret Manusia Indonesia Pasca Reformasi" (ISBN 9786021201220) sebagai yang pertama dari Seri Buku Psikologi Kebangsaan. Sebenarnya buku ini terinspirasi dari apa yang pernah dilakukan Mochtar Lubis ketika menulis dan menyampaikan Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki Tahun 1977. Pada saat itu, Mochtar Lubis mengemukakan tujuh ciri manusia Indonesia, sebagai berikut: (1) hipokritis (munafik), (2) segan dan enggan bertanggungjawab atas perbuatannya, kelakuannya, pikirannya, dan sebagainya, (3) berjiwa feodal, (4) percaya takhyul, (5) artistik, (6) berwatak lemah, dan (7) ciri lainnya: tidak hemat, lebih suka tidak bekerja keras (kecuali terpaksa), kurang sabar, cepat cemburu dan dengki terhadap orang yang dilihatnya lebih darinya, gampang senang dan bangga pada yang hampa-hampa, manusia-sok, tukang tiru, cenderung bermalas-malasan, cukup logis, masih lemah dalam mengaitkan antara sebab dan akibat, mesra dalam hubungan antar manusia, ikatan kekeluargaan yang mesra, berhati lembut, suka damai, punya rasa humor yang cukup baik, cepat belajar (Lubis, 2013). Saudara Ratrioso (2015), tiga puluh delapan tahun kemudian, mengemukakan delapan hipotesis tentang profil manusia Indonesia pasca-reformasi, yaitu (1) semakin mementingkan diri sendiri, (2) kemauan belajar yang rendah, (3) semakin agresif, (4) melunturnya kesadaran Ke-Indonesia-an, (5) kemenangan materialisme yang semakin sempurna, (6) kepasrahan yang tetap tinggi, (7) tetap mudah memaafkan, dan (8) tahan menderita.
Berbeda dari Lubis, Ratrioso (2015) menggunakan teori-teori psikologi sebagai alat bantu untuk memahami manusia Indonesia. Di samping itu, Ratrioso membatasi kesimpulannya, yakni hanya berlaku bagi manusia Indonesia yang hidup pasca-reformasi. Sebelumnya, Psikolog Sarlito Wirawan Sarwono (2005) menulis artikel berjudul “Bangsa Yang teledor”, Budayawan Emmanuel Subangun (2007) menulis “Bangsa Yang Lupa Ingatan”, Psikiater Limas Sutanto (2008) menulis “Bangsa Yang Dangkal”. Kendati demikian, terdapat persamaan di antara tulisan-tulisan itu, yakni tiadanya basis penelitian empiris, semacam sosial-epidemiologis, sebagai landasan bagi berdirinya kesimpulan-kesimpulan mereka tentang jiwa bangsa ini. Cukup mengejutkan bahwa hampir 40 tahun kita mendambakan adanya kesimpulan yang lebih bertanggungjawab mengenai ciri atau sifat umum Manusia Indonesia berdasarkan kesadaran kritis mengenai tingkat urgensi atau kepentingannya, namun kita tidak melakukan sesuatu upaya yang serius untuk menyelenggarakan semacam national initiatives dalam rangka itu. Nah, patut kita renungkan, ciri manusia Indonesia apakah yang tercermin dari kenyataan ini?
Terdapat sejumlah hal yang menarik perhatian saya dari buku ini. Pertama, Ratrioso dengan jeli menghubungkan pembahasan pikirannya dengan Revolusi Mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Suatu kali saya di penghujung tahun 2014 bertemu dengan Bapak Ichsan Malik, praktisi psikologi perdamaian, yang dikenal sebagai pencetus gerakan Baku Bae ketika terjadi konflik sosial di Ambon. Ia menyatakan satu hal yang menarik, yaitu bahwa di saat revolusi mental diangkat, psikologi malah “meeental”. “Ini kan kita jadinya seperti ngeledek!” ujar beliau. Benar juga! Revolusi mental merupakan sebuah terminologi yang seharusnya merupakan ranah utama psikologi, karena psikologi mempelajari kehidupan mental. Saudara Ratrioso tepat sekali ketika dalam bukunya di Bagian 3 “Apa Yang Harus Dilakukan dan Darimana Dimulai” guna menghadapi gambaran manusia Indonesia yang “seakan-akan pesimistik”; ia menyatakan pertama-tama kita perlu “Mengkonstruksi lagi jatidiri dan karakter bangsa”, suatu anjuran yang tepat sekali menyentuh jantung tindakan psikologis. Revolusi mental memang harus berawal dari mental juga, bukan dari fisik bangsa. Mental yang menjadi fokus adalah mental bangsa, yang kita bayangkan sebagai koordinat dari segenap proses dan praktik sosial bangsa ini, baik yang dihidupi oleh individu maupun lembaga-lembaga sosial.
Selanjutnya, Ratrioso menyatakan dalam bukunya:
“Acara pernikahan atau hajatan itu bagus, termasuk membuat pasar malam juga bagus. Tapi jika caranya menutup fasilitas umum yang sudah lazim dipakai orang banyak, tanpa ada izin dan panduan yang jelas, tentu saja ini tidak bisa dibiarkan. Praktik demikian merupakan cermin konsep berpikir bahwa orang lain tidak penting.”
Amatan ini adalah amatan yang tajam! Hipotesis Ratrioso bahwa bagi manusia Indonesia “orang lain tidak penting” seolah membantah konsepsi Psikologi Timur dan Psikologi Orang Indonesia yang selama ini meyakini bahwa orang Indonesia memiliki konsep diri interdependen-relasional-kolektivistik (yang justru sangat mempertimbangkan orang lain), bukan konsep diri independen-individualistik seperti orang Barat. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa paradoks dalam profil sebuah bangsa sangat dimungkinkan. Persoalannya adalah bagaimana menjembatani pemahaman-pemahaman yang paradoksal itu. Apabila kita menggunakan rumus sederhana dari Bapak Psikolog Sosial, Kurt Lewin, bahwa perilaku merupakan fungsi dari diri dan lingkungan (Behavior = function (Person, Environment)), maka kita boleh menarik dugaan sementara bahwa kegiatan individu memantau interaksinya dengan lingkungan akan menentukan caranya memandang orang lain dalam lingkungan dan menyikapinya dalam kurun waktu tertentu. Dalam anekdot Ratrioso di atas, ada kemungkinan bahwa secara ekologis, ada batas-batas (definisi) tentang “orang lain”. Ada “orang lain” yang dianggap penting dengan perilaku itu; ada “orang lain” yang dianggap tidak penting dengan perilaku itu. Siapakah “orang lain” bagi kita dalam berbagi konteks lingkungan, dengan demikian merupakan pertanyaan yang perlu dijawab jika kita ingin menyimpulkan apakah bangsa kita memang semakin mementingkan diri sendiri.
Pada halaman 57 Ratrioso mengungkapkan:
“Ceramah agama yang diminati adalah yang banyak lucunya, hiburannya dan hadiahnya. Para dai yang mengajarkan pengetahuan secara serius dan sungguh-sungguh tidak mendapat tempat di hati rakyat. Rakyat maunya belajar itu yang tidak sungguh-sungguh tapi kalau bisa langsung menghasilkan kehidupan yang enak, mewah, dan masuk surga. Sebagian kita sudah semakin apatis terhadap proses-proses yang rasional untuk memperbaiki hidup.”
Hal ini merupakan gejala yang serius! Jika kita setuju bahwa pendidikan formal merupakan salah satu ajang untuk melakukan revolusi mental, kita juga perlu menyadari bahwa gejala yang dikemukakan Ratrioso di atas juga melanda ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah formal kita. Arus pragmatisme dan instanisme memiliki ekses-ekses yang justru lebih menguasai kita ketimbang kebaikan-kebaikan originalnya. Kita harus merevolusi secara menyeluruh proses-proses interaksional yang terjadi dalam ruang-ruang kelas pembelajaran kita. Apabila Ratrioso mensinyalir bahwa gejala di atas mencerminkan kemauan belajar yang rendah, saya ingin menambahkan bahwa betapa kemauan belajar kita setinggi atau sesedikit apapun sangat perlu untuk dibarengi dengan interaksi yang mampu memfasilitasi aktualisasi dari kemauan itu. Kita ingat pepatah “Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.” Persoalannya di sini adalah bagaimana mendesain sebuah interaksi yang mampu menghubungkan antara kemauan dai (dalam kasus di atas) atau guru dengan kemauan orang yang belajar. Apa artinya? Idealisme dan pragmatisme, dai dan jamaah, guru dan siswa perlu dipertemukan. Perlu dihidupkan negosiasi di antara keduanya. Selama ini kita barangkali menjadi tidak adil dengan serta-merta “menyalahkan” salah satu pihak, kalau tidak dai-nya ya jamaah-nya, kalau tidak gurunya ya siswanya; atau materi khotbah atau kurikulumnya. Padahal, kita tidak pernah secara sistematis dan berkelanjutan bertemu dan berdialog antara pembelajar dan pelajar. Malahan saya mencermati bahwa pertemuan antara sekolah, guru, dan siswa diadakan seringkali untuk memenuhi syarat administratif akreditasi sekolah! Kalau begini, tidak ada proses perjumpaan dari hati ke hati. Tidak akan ada yang mengalami revolusi mental sehingga tidak akan terjadi pula percepatan pembelajaran.
Di halaman 98, Ratrioso berujar:
"Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merebak sampai ke tingkat yang tidak bisa dinalar oleh akal siapapun. Ada istri mencincang suaminya, ada suami yang membakar istrinya, ada ibu yang membunuh anaknya dan memasukkan jaddnya ke septic tank dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan yang sudah tak bisa terakomodasi oleh nalar yang waras."
Ratrioso memberikan contoh ini untuk menjelaskan hipotesisnya mengenai salah satu potret manusia Indonesia, yakni “makhluk yang semakin agresif”. Saya setuju sekaligus tergelitik ketika Ratrioso memasukkan kata “waras” dan “akal” ketika menyoal tentang kekerasan. Saya berpendapat bahwa banyak dari aspek-aspek kewarasan kita bersangkut paut dengan bahasa. Saya pernah menunjukkan melalui sebuah artikel saya yang berjudul Bahasa Sebagai Praktik Sosial bahwa masalah pendidikan sampai dengan masalah bunuh diri dapat dianalisis dengan pendekatan analisis bahasa (Juneman, 2010). Masalah bahasa apa yang ada dalam kasus di atas? Mengutip pendapat Sudaryanto, seorang pakar linguistik (dalam Frans Sartono, 2014), istilah “kekerasan” tidak begitu konkret. Yang lebih konkret adalah “kekejaman” atau “kejahatan”; jadi seharusnya “Kekejaman (atau Kejahatan) dalam rumah tangga” bukan “Kekerasan dalam rumah tangga”. Sudaryanto mengatakan bahwa salah satu fungsi bahasa yang utama adalah mengembangkan akal budi. Dengan menggunakan bahasa secara keliru, maka banyak permasalahan manusia yang akan timbul dan lestari (Juneman, 2010), dan akal budi (dalam istilah Ratrioso: nalar, kewarasan) tidak akan berkembang baik. Bila demikian, persoalan akan tetap tinggal seperti benang kusut, seberapa daya dan upaya pun kita keluarkan. Tepat sekali Sudaryanto menyatakan bahwa revolusi mental berawal dari bahasa. Kalau begitu, apakah perlu ditambahkan lagi profil manusia Indonesia ditinjau dari penggunaan bahasanya? Ini merupakan pertanyaan yang menurut hemat saya sangat mendesak untuk didiskusikan dalam rangka studi Psikologi Kebangsaan.
Saya mengucapkan banyak selamat kepada Saudara Ratrioso atas penerbitan buku ini. Saya mengenal beliau sejak enam tahun yang lalu. Dalam perjalanan pulang dari sebuah acara Himpunan Psikologi Indonesia di tahun 2010, ia menyampaikan kepada saya bahwa ia ingin menulis sebuah buku tentang bangsa ini dengan menggunakan pendekatan psikologi. Ia mengemukakan kegelisahannya atas kondisi bangsa, dan bertanya-tanya mengapa psikologi tidak bisa melakukan sesuatu untuk ambil bagian, sedikitnya dari sisi pemikiran, untuk turut memperbaiki keadaan bangsa ini. Menulis sebuah buku tidaklah mudah, apalagi buku yang memetakan kondisi manusia Indonesia. Namun atas kegigihan dan ketekunannya, ia berhasil juga membuahkan buku ini. Saya kira tidak berlebihan jika penulisan buku ini dipandang sebagai salah satu upaya yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, lebih-lebih dalam menegakkan payung studi Psikologi Kebangsaan di negeri ini. Upaya ini perlu dilembagakan, bukan dalam arti “dibuat kaku” melainkan agar terjaga keberlangsungannya, dan terus-menerus diperbarui.
Juneman Abraham
Cara mengutip: Abraham, J. (2015). Psikologi Kebangsaan Sebagai Payung Studi Baru di Indonesia (Epilog). In: Ratrioso, I., Rakyat Nggak Jelas: Potret Manusia Indonesia Pasca Reformasi (pp. 323-339). Jakarta: ReneBook. Retrieved from http://media.kompasiana.com/buku/2015/04/18/psikologi-kebangsaan-sebagai-payung-studi-baru-di-indonesia-713196.html
Referensi
Astaf'ev, P. E. (2006). Nationality and universal tasks: Toward a Russian national psychology. Russian Studies in Philosophy, 45(2), 5-33.
Bendersky, J. W. (1988). Psychohistory before Hitler: Early military analyses of German national psychology. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 24, 167-182.
Boorman, H. L., & Boorman, S. A. (1967). Strategy and national psychology in China. Annals of the American Academy of Political and Social Science, National Character in the Perspective of the Social Sciences, 370, 143-155.
Juneman. (2010, 29 Mei). Bahasa sebagai praktik sosial. Koran Jakarta, h. 4. https://www.academia.edu/240482/Bahasa_Sebagai_Praktik_Sosial_Dalam_Pendidikan_
Juneman. (2013). Psikologi dan gugatan epistemologis terhadap perumpunan ilmu dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi. Dalam Prapto Yuwono, Neil Semuel Rupidara, Ferry F. Karwur, & Titi Susilowati (2013)(Eds.), Menggugat fragmentasi dan rigiditas pohon ilmu, 43-68, ISBN 978-979-8154-47-8.
Juneman, & Meinarno, E. A. (2013). Semakin kental identitas religius semakin lunturkah identitas nasional? Peran Keberpancasilaan pada remaja Indonesia. Dalam Jas Laile Suzana Jaafar, Yahaya Mahamood, Zahari Ishak (2013)(Eds.), Menongkah arus globalisasi: Isu-isu psikologi di Malaysia dan Indonesia. Kuala Lumpur: Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Universiti Malaya.
Kim, U. (1995). Psychology, science, and culture: Cross-cultural analysis of national psychologies. International Journal of Psychology, 30, 662-679.
Lubis, M. (2013). Manusia Indonesia: Sebuah pertanggungjawaban. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rosenberg, D. J. (2008). Patho-teleology and the spirit of war: The psychoanalytic inheritance of national psychology. Monatshefte, 100(2), 213-225.
Sartono, F. (2014). Revolusi mental berawal dari bahasa. Kompas. http://nasional.kompas.com/read/2014/11/23/16233291/Revolusi.Mental.Berawal.dari.Bahasa
Sarwono, S. W. (2005, 17 September). Bangsa yang teledor. Kompas, h. 6.
Subangun, E. (2007). Bangsa yang lupa ingatan. Ataraxis: Indonesian Journal of Mental Health, 1(1), 2-4.
Sutanto, L. (2008, 31 Juli). Bangsa yang dangkal. Kompas. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10475&coid=1&caid=34&gid=1
Woodworth, R. S. (1912). National psychology. Psychological Bulletin, 9(10), 397-399.