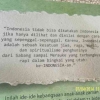Pada halaman 57 Ratrioso mengungkapkan:
“Ceramah agama yang diminati adalah yang banyak lucunya, hiburannya dan hadiahnya. Para dai yang mengajarkan pengetahuan secara serius dan sungguh-sungguh tidak mendapat tempat di hati rakyat. Rakyat maunya belajar itu yang tidak sungguh-sungguh tapi kalau bisa langsung menghasilkan kehidupan yang enak, mewah, dan masuk surga. Sebagian kita sudah semakin apatis terhadap proses-proses yang rasional untuk memperbaiki hidup.”
Hal ini merupakan gejala yang serius! Jika kita setuju bahwa pendidikan formal merupakan salah satu ajang untuk melakukan revolusi mental, kita juga perlu menyadari bahwa gejala yang dikemukakan Ratrioso di atas juga melanda ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah formal kita. Arus pragmatisme dan instanisme memiliki ekses-ekses yang justru lebih menguasai kita ketimbang kebaikan-kebaikan originalnya. Kita harus merevolusi secara menyeluruh proses-proses interaksional yang terjadi dalam ruang-ruang kelas pembelajaran kita. Apabila Ratrioso mensinyalir bahwa gejala di atas mencerminkan kemauan belajar yang rendah, saya ingin menambahkan bahwa betapa kemauan belajar kita setinggi atau sesedikit apapun sangat perlu untuk dibarengi dengan interaksi yang mampu memfasilitasi aktualisasi dari kemauan itu. Kita ingat pepatah “Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.” Persoalannya di sini adalah bagaimana mendesain sebuah interaksi yang mampu menghubungkan antara kemauan dai (dalam kasus di atas) atau guru dengan kemauan orang yang belajar. Apa artinya? Idealisme dan pragmatisme, dai dan jamaah, guru dan siswa perlu dipertemukan. Perlu dihidupkan negosiasi di antara keduanya. Selama ini kita barangkali menjadi tidak adil dengan serta-merta “menyalahkan” salah satu pihak, kalau tidak dai-nya ya jamaah-nya, kalau tidak gurunya ya siswanya; atau materi khotbah atau kurikulumnya. Padahal, kita tidak pernah secara sistematis dan berkelanjutan bertemu dan berdialog antara pembelajar dan pelajar. Malahan saya mencermati bahwa pertemuan antara sekolah, guru, dan siswa diadakan seringkali untuk memenuhi syarat administratif akreditasi sekolah! Kalau begini, tidak ada proses perjumpaan dari hati ke hati. Tidak akan ada yang mengalami revolusi mental sehingga tidak akan terjadi pula percepatan pembelajaran.
Di halaman 98, Ratrioso berujar:
"Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merebak sampai ke tingkat yang tidak bisa dinalar oleh akal siapapun. Ada istri mencincang suaminya, ada suami yang membakar istrinya, ada ibu yang membunuh anaknya dan memasukkan jaddnya ke septic tank dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan yang sudah tak bisa terakomodasi oleh nalar yang waras."
Ratrioso memberikan contoh ini untuk menjelaskan hipotesisnya mengenai salah satu potret manusia Indonesia, yakni “makhluk yang semakin agresif”. Saya setuju sekaligus tergelitik ketika Ratrioso memasukkan kata “waras” dan “akal” ketika menyoal tentang kekerasan. Saya berpendapat bahwa banyak dari aspek-aspek kewarasan kita bersangkut paut dengan bahasa. Saya pernah menunjukkan melalui sebuah artikel saya yang berjudul Bahasa Sebagai Praktik Sosial bahwa masalah pendidikan sampai dengan masalah bunuh diri dapat dianalisis dengan pendekatan analisis bahasa (Juneman, 2010). Masalah bahasa apa yang ada dalam kasus di atas? Mengutip pendapat Sudaryanto, seorang pakar linguistik (dalam Frans Sartono, 2014), istilah “kekerasan” tidak begitu konkret. Yang lebih konkret adalah “kekejaman” atau “kejahatan”; jadi seharusnya “Kekejaman (atau Kejahatan) dalam rumah tangga” bukan “Kekerasan dalam rumah tangga”. Sudaryanto mengatakan bahwa salah satu fungsi bahasa yang utama adalah mengembangkan akal budi. Dengan menggunakan bahasa secara keliru, maka banyak permasalahan manusia yang akan timbul dan lestari (Juneman, 2010), dan akal budi (dalam istilah Ratrioso: nalar, kewarasan) tidak akan berkembang baik. Bila demikian, persoalan akan tetap tinggal seperti benang kusut, seberapa daya dan upaya pun kita keluarkan. Tepat sekali Sudaryanto menyatakan bahwa revolusi mental berawal dari bahasa. Kalau begitu, apakah perlu ditambahkan lagi profil manusia Indonesia ditinjau dari penggunaan bahasanya? Ini merupakan pertanyaan yang menurut hemat saya sangat mendesak untuk didiskusikan dalam rangka studi Psikologi Kebangsaan.
Saya mengucapkan banyak selamat kepada Saudara Ratrioso atas penerbitan buku ini. Saya mengenal beliau sejak enam tahun yang lalu. Dalam perjalanan pulang dari sebuah acara Himpunan Psikologi Indonesia di tahun 2010, ia menyampaikan kepada saya bahwa ia ingin menulis sebuah buku tentang bangsa ini dengan menggunakan pendekatan psikologi. Ia mengemukakan kegelisahannya atas kondisi bangsa, dan bertanya-tanya mengapa psikologi tidak bisa melakukan sesuatu untuk ambil bagian, sedikitnya dari sisi pemikiran, untuk turut memperbaiki keadaan bangsa ini. Menulis sebuah buku tidaklah mudah, apalagi buku yang memetakan kondisi manusia Indonesia. Namun atas kegigihan dan ketekunannya, ia berhasil juga membuahkan buku ini. Saya kira tidak berlebihan jika penulisan buku ini dipandang sebagai salah satu upaya yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, lebih-lebih dalam menegakkan payung studi Psikologi Kebangsaan di negeri ini. Upaya ini perlu dilembagakan, bukan dalam arti “dibuat kaku” melainkan agar terjaga keberlangsungannya, dan terus-menerus diperbarui.
Juneman Abraham
Cara mengutip: Abraham, J. (2015). Psikologi Kebangsaan Sebagai Payung Studi Baru di Indonesia (Epilog). In: Ratrioso, I., Rakyat Nggak Jelas: Potret Manusia Indonesia Pasca Reformasi (pp. 323-339). Jakarta: ReneBook. Retrieved from http://media.kompasiana.com/buku/2015/04/18/psikologi-kebangsaan-sebagai-payung-studi-baru-di-indonesia-713196.html
Referensi
Astaf'ev, P. E. (2006). Nationality and universal tasks: Toward a Russian national psychology. Russian Studies in Philosophy, 45(2), 5-33.
Bendersky, J. W. (1988). Psychohistory before Hitler: Early military analyses of German national psychology. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 24, 167-182.
Boorman, H. L., & Boorman, S. A. (1967). Strategy and national psychology in China. Annals of the American Academy of Political and Social Science, National Character in the Perspective of the Social Sciences, 370, 143-155.
Juneman. (2010, 29 Mei). Bahasa sebagai praktik sosial. Koran Jakarta, h. 4. https://www.academia.edu/240482/Bahasa_Sebagai_Praktik_Sosial_Dalam_Pendidikan_
Juneman. (2013). Psikologi dan gugatan epistemologis terhadap perumpunan ilmu dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi. Dalam Prapto Yuwono, Neil Semuel Rupidara, Ferry F. Karwur, & Titi Susilowati (2013)(Eds.), Menggugat fragmentasi dan rigiditas pohon ilmu, 43-68, ISBN 978-979-8154-47-8.
Juneman, & Meinarno, E. A. (2013). Semakin kental identitas religius semakin lunturkah identitas nasional? Peran Keberpancasilaan pada remaja Indonesia. Dalam Jas Laile Suzana Jaafar, Yahaya Mahamood, Zahari Ishak (2013)(Eds.), Menongkah arus globalisasi: Isu-isu psikologi di Malaysia dan Indonesia. Kuala Lumpur: Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Universiti Malaya.
Kim, U. (1995). Psychology, science, and culture: Cross-cultural analysis of national psychologies. International Journal of Psychology, 30, 662-679.
Lubis, M. (2013). Manusia Indonesia: Sebuah pertanggungjawaban. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rosenberg, D. J. (2008). Patho-teleology and the spirit of war: The psychoanalytic inheritance of national psychology. Monatshefte, 100(2), 213-225.
Sartono, F. (2014). Revolusi mental berawal dari bahasa. Kompas. http://nasional.kompas.com/read/2014/11/23/16233291/Revolusi.Mental.Berawal.dari.Bahasa
Sarwono, S. W. (2005, 17 September). Bangsa yang teledor. Kompas, h. 6.
Subangun, E. (2007). Bangsa yang lupa ingatan. Ataraxis: Indonesian Journal of Mental Health, 1(1), 2-4.
Sutanto, L. (2008, 31 Juli). Bangsa yang dangkal. Kompas. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10475&coid=1&caid=34&gid=1
Woodworth, R. S. (1912). National psychology. Psychological Bulletin, 9(10), 397-399.