Desa yang diapit dua kaki gunung itu amat subur. Tanah yang ada di sana seolah menyimpan banyak kandungan emas. Apapun ditanam pasti tumbuh, dan berbuah. Sawah yang terbentang luas milik masyarakatnya juga demikian. Di tambah air yang melimpah dari mata air maupun arus air sungai yang membelah pemukiman penduduknya, menyirami tiap petak sawah atau kebun tanpa lelah.
Semua itu dipandang masyarakat sebagai suatu karunia Ilahi. Rata-rata warga di desa ini hidup bahagia. Sandang, pangan, dan papan boleh dibilang cukup. Interaksi antarwarga berjalan harmonis. Tiada pernah ada perselisihan. Kehidupan desa berlangsung sebagaimana seharusnya. Semua karena kerja keras Kuwu Naya.
Sebagai kuwu, Naya memang disegani oleh warganya. Ia amat cakap mengelola semua urusan, mulai dari irigasi sawah hingga gesekan antarwarga, yang satu dua kali sempat muncul, menyangkut soal jatah air untuk sawah mereka. Tapi itu semua bisa dikelola Naya dengan mulus.
Pendek kata, desa itu aman, tentram, dan sejahtera.
Namun begitu, ada yang mengganjal dipikiran Naya selama ini. Atau boleh jadi keluarganya secara turun temurun, menyangkut sawah yang sekarang ia kelola, sebagai sawah leluhur. Sawah yang letaknya di sisi sebelah kanan jalan itu berbeda dengan sawah kepunyaan warga lainnya. Pasalnya di titik tengah sawah berdiri pohon kemuning yang tingginya satu setengah meter, kokoh, dan sejauh mata memandang, jika orang melihat hamparan sawah di desa ini dari bagian barat, maka pohon ini tampak menonjol.
Naya tidak tahu persis kapan pohon Kemuning itu ada. Sebab buyut moyangnya juga tidak sekalipun mengabarkan soal ini. Di arsip desa pun tidak tercatat. Cuma satu pesan yang semua keturunannya ingat, "jangan ditebang pohon Kemuning itu".
Pesan ini pun di pikiran Naya justru yang paling mengganjal malah, Apa alasannya sehingga pohon itu tidak boleh disingkirkan? Sebagai Kuwu, tentu saja hal semacam ini mencederai logika kausalitas yang ia punya. Tiap orang mesti berpikir sebab, dan akibat dari suatu tesa. Jangan terima sesuatu keterangan itu absolute saja. Selalu demikian cara ia membenarkan tindakannya.
Sebab itu, tanpa konsultasi dengan siapapun. Juga tidak diketahui oleh istri, anak, dan warganya, ia nekad malam hari sendirian mendatangi pohon itu dengan perangkat tebangnya, kampak, dan golok. Karena memang diameter pohon ini amat tipis Jadi pikirnya, sekali tebas, dan cacah, hilang sudah pohon yang di matanya amat mengganggu pemandangan itu.
***
Suara desir angin yang kencang menemani Naya malam itu yang tengah berada di tengah sawahnya. Pepohonan di sepanjang jalan di sisi persawahan, juga daunnya seolah berkibar tak kalah kencangnya. Suara katak yang didengar Naya seperti menyayat pilu. Tikus-tikus sawah yang tidur pun terbangun mencari tahu. Cacing tanah juga tak mau kalah, meliuk-liuk di tanah becek, seakan berteriak jangan.
Namun tanpa ampun, ia hantamkan juga kapak itu pada Kemuning. Sekali hantam, sekali itu juga katak, tikus, cacing, burung, dan binatang lain yang selalu ada di sawah, berlarian menjauh, dan berteriak nyaring, pergi. Cacing tanah tak mau kalah, langsung masuk menembus lapisan tanah yang paling dalam. Hantaman demi hantaman kapak pada akhirnya meluluhlantakan pohon Kemuning yang konon sudah berusia ratusan tahun itu.
Tapi Naya belum puas juga sebab masih ada satu batang dari pohon Kemuning itu yang masih nempel di akarnya belum tuntas. Karena sudah menjelang subuh ia pun kembali ke rumahnya. Pikirnya usai urusan desa, sore hari ia akan lanjutkan memangkas batang dan mencabut akarnya.
***
Halim tergopoh-gopoh mendatangi balai desa. Padahal hari masih pagi, baru pukul 09.30. Seharusnya ia ada di sawah. Namun saat tiba, ia malah heran, di sana sudah ada juga Komar, Dayat, dan mang Tarja. Mereka petani sebagaimana dirinya. Komar sawahnya di Timur, Dayat di sebelah Utara, mang Tarja di Selatan, sementara dirinya di sebelah Barat.
"Kok pada kumpul di sini, tumben,"sapa Halim sembari menyalami mereka semua.
"Iya, ini lagi tunggu, pak Kuwu. Belum datang sejak pagi, kata stafnya. Ya kita tunggu aja sampai datang. Ada perlu apa Halim? Balas mang Tarja.
"Iya, mang, ini teh soal sawah. Kan kita mau panen ya, kemarin mah air banyak dan bagus, tapi tadi teh kok tiba-tiba susut, gitu. Kumaha nya?
"Puguh, kita juga sama atuh masalah na. Si Komar kitu, si Dayat oge. Kok bisa sama ya di sawah kita aja airnya yang susut, sementara yang lain tidak, malah biasa aja."
Percakapan mereka masih santai, dan biasa saja terkait soal sawah, dan masa panen sekarang. Hingga kemudian Kuwu Naya datang, dan laporan warganya tadi ditindaklanjuti oleh stafnya di bagian pengairan. Ada empat titik sawah yang dipunyai warga itu, baik Halim, Komar, Dayat, dan mang Tarja, yang mesti didatangi staf desa. Kebetulan juga empat sawah yang berada di penjuru desa itu sebagai benteng kokoh desa ini dari ancaman kekeringan. Sebab secara kasat mata, air sungai yang mengalir, dekat dengan sawah mereka masing-masing, juga sebagai jalan dari saluran air ke sawah. Karena itu bagian pengairan keheranan. Bagaimana mungkin air yang melimpah dari sungai tidak mengaliri sawah empat warganya ini?
"Ini sawah mang tarja?Tanya Munif.
"Leureus Kang.
"Ini saya heran, mang, Di sawah Dayat, Komar, juga Halim posisi sawah seharusnya tidak bakal kering, dan susut. Sebab mang Tarja lihat sendiri. Itu sawah sebelah mang Tarja, si Ruhun air banyak. Tapi mengapa susut ini?
Munif yang sudah turun temurun, dari buyut, kakek, hingga dirinya menjadi staf desa di bagian pengairan juga keheranan, apalagi si empunya sawah. Karenanya ia cepat kembali ke balai desa, sekaligus meyakinkan semua pemilik sawah untuk bersabar. Munif lapor pada Naya.
"Kalau kondisinya seperti ya disampaikan, ya sudah, ditata ulang aja,"kata Naya mengambil kesimpulan.
"Ditata ulang, bagaimana?
"Kok malah balik bertanya. Saudara kan yang bertanggungjawab untuk urusan air. Ya ditata ulang lagi. Empat sawah itu bisa diairi sawahnya dari air sawah yang lain di sebelahnya. Atau Saluran airnya dibenahi lagi supaya rata pengairan untuk sawahnya.
"Bukan itu masalahnya. Ini ganjil saja di mata saya. Saluran air limpahan dari sungai sudah lebih dari cukup mengairi sawah satu desa. Itu saya mengerti.Tapi empat sawah milik warga di sudut desa, justru kering, padahal sawah merekalah yang seharusnya airnya melimpah. Bagaimana mungkin air sungai yang ada di sisi sawah mereka tidak jalan mengairi sawahnya, tapi ke sawah sebelahnya mengalir biasa saja."
Naya tersentak mendapat penjelasan yang menurutnya juga tidak masuk akal ini. Akhirnya ia mengerti dan maklum dengan pandangan Munif itu. Dan mencari jalan keluar esoknya bersama staf kelurahan yang lain.
***
Sore sebagaimana niatnya, maka Naya kembali mendatangi pohon Kemuning yang tinggal batangnya yang menempel diakarnya untuk dipangkas dan dicabut sekalian. Sore itu tiada angin maupun suara kicauan burung yang senantiasa ada di tengah sawah. Awan juga tampak redup, tidak ada pelangi, sebagaimana biasanya ketika senja datang menjelang di desa ini. Di tengah sawah miliknya juga suasana seakan tidak ada kehidupan, sunyi jempling.
Naya sudah menyiapkan diri. Sekali dua kali, hantaman kapak, tidak menggoyahkan satu-satunya batang pohon Kemuning yang tersisa. Ia ambil golok, dipukulkannya pula, juga tidak mempan. Kapak dan golok, ia istirahatkan. Lalu ia coba dengan tangannya, sebab batangnya ini kecil dan tipis, seukuran sapu, barangkali tinggal dipites, atau diputar-putar bakal patah. Tapi nyatanya juga tidak. Justru liat dan kuat.
Belum selesai batangnya, ia alihkan ke akarnya. Ia coba hantamkan berulang kali, antara kapak dan golok. Akar itu tetap pada posisinya, tidak tergores sama sekali. Keringat membasahi wajah dan tubuhnya. Naya seketika bergidik, merinding. Ia heran, kemarin begitu mudah hantaman kapak, dan goloknya menghabisi yang namanya pohon ini. Tapi kini ia bingung, heran, dan tidak habis pikir. Bagaimana bisa tidak mempan dihabisi? Sampai di sini logika materialismnya bermain. Ternyata ada logika dunia lain. Ia pun putuskan untuk kembali pulang, persis magrib menjelang.
"Darimana Kang?Tanya istrinya Acih di teras rumah.
"Habis dari sawah. Di sana mulai banyak burung, kuatir ganggu padi, kan sebentar lagi panen,"Jawabnya.
"Atuh besok-besok mah yang ke sawah si Ujang aja, kang. Nanti akang kurang istirahatnya.
"Iya atuh, kalo begitu mah, si Ujang wae.
Semalaman Naya berpikir keras. Ada sesuatu yang baru kali ini ia tidak mengerti. Pohon yang seharusnya sudah tumbang justru malah jadi pikiran sekarang. Ada apa dengan pohon itu? Pohon yang kecil, tipis, dan tidak kokoh, tapi nyatanya sekokoh baja. Naya hanya berpikir, dan pulas tertidur di sisi Acih, akhirnya, tenang.
***
Oleh sebab ada fakta yang bertentangan dengan akal sehatnya, maka Naya ambil keputusan untuk menemui seorang yang lebih pintar. Pintar menebang pohon, dan pintar juga mengalahkannya. Karena ia sendiri kalah, mungkin semua orang di desa kalau dilibatkan menebang, juga pasti kalah. Tapi ia tidak mau, sebab ini sawahnya dia. Sawah keturunan yang mesti dijaga. Apa jadinya kalau orang satu desa ada di sawahnya?Yang pasti panen akan gagal, karena terinjak-injak.
Sebagai Kuwu tentu mudah baginya peroleh informasi, dan bantuan untuk didatangkan siapa orang yang punya kepandaian menghadapi hal-hal yang ganjil sebagaimana yang dia alami. Karenanya sudah beberapa orang yang punya kapasitas untuk dimintai tolong, tapi malah ngacir ketika datang ke lokasi. Padahal belum sama sekali melakukan tugasnya.
Dari situlah kemudian ia datangkan seorang Kiai sakti mandraguna, mampu berjalan di atas air, terbang melintasi batas langit dengan ruhnya, juga tidak sombong orangnya. Ia punya julukan, Kiai Cipancur. Orangnya tinggi semampai, sholeh, tenang, dan selalu bersorban. Tanpa janggut, dan jenggot. Ia dan Naya nyaris sebaya, sebagaimana kakak beradik bila diperhatikan dengan seksama.
Kiai Cipancur kemudian sudah bersama Naya di rumahnya.
"Kiai, punten ini, saya mau minta tolong. Ada sisa pohon Kemuning di tengah sawah saya yang masih belum bisa dicabut akarnya. Sudah saya usahakan sendiri, tapi tetap tidak bisa,"ungkap Naya pada Kiai yang juga tengah meneropong kedalaman isi hati Naya, jujur atau bohong soal kemauannya ini.
"Pohon Kemuning di tengah sawah?
"Benar Kiai.
Kiai Cipancur sempat kaget, namun ia bisa kuasai diri di hadapan Kuwu desa ini.
"Jadi maksud kuwu teh, supaya saya tebang habis sampai ke akarnya pohon itu?
"Benar kiai. Seharian saya habisi tempo hari tapi tidak mempan."
Sebagai orang yang dimintai tolong, dan tokoh yang disegani se-kabupaten, maka permintaan semacam ini pantang untuk ditolaknya. Tapi pohon Kemuning di tengah sawah yang ada di desa ini, yang kini bakal dihadapinya, bukan sembarang pohon. Pohon itu sebagaimana yang ia peroleh informasinya, dari buyut guru, embah guru, maupun nenek guru, adalah pusat kehidupan dunia lain.
Di situ semacam pintu masuk istana kerajaan setan yang konon sudah ribuan tahun mendiami wilayah tersebut. Apalagi kisah empat sawah di tiap sudut desa ini yang airnya menyusut, juga menurut kiai sebagai pertanda, bahwa benteng kokoh desa ini mulai ada gangguan. Sebab sawah warga di tiap sudut itu ibaratnya sebagai titik lokasi awal, atau arah jalan menuju istana di sekitar pohon Kemuning ini. Arah jalan setan tentunya.
"Jadi pohon Kemuning itu ya?Lagi-lagi kiai minta kepastian.
"Benar Kiai. Jika kiai bersedia saya akan berikan upah 5 rupiah Tiga rupiah saya serahkan sekarang, sisanya usai menuntaskan pekerjaan itu. Bagaimana kiai?
Bukan pesohor jika menolak niat baik dari Kuwu Naya. Zonder reserve, Kiai Cipancur pun bersedia melakukannya, sembari mewanti-wanti agar usai tugas segera ditunaikan sisa dua rupiah itu. Kuwu Naya memastikan, dan mengajak kiai untuk bersalaman, sebagai akad bahwa tugas dan upah sudah disepakati bersama-sama, dengan segala resikonya.
***
Tidak siang, tapi tengah malam Kiai Cipancur mendatangi lokasi di tengah sawah itu. Waktu menunjukkan pukul 24.01 Wib. Suasana sunyi. Hening tiada terkira. Angin menghembus lembut. Tanaman padi bergoyang pelan mengikuti hembusan angin, seirama. Katak, ular sawah, tikus, cacing, dan sejenisnya, entah kemana mereka semua tengah malam ini. Boleh jadi mereka minggat sementara untuk tidak mau tahu dengan kehadiran kiai sohor tersebut.
"Sampurasun,"begitu kiai berucap salam, entah pada siapa. Hanya mata bathinnya langsung menyaksikan kehadiran suatu makhluk yang sangat besar, yang digambarkan oleh kiai usai tugasnya itu pada pamong desa Balandongan dan anak cucunya belakangan hari, sebagai makhluk yang baru dilihatnya setelah sekian puluh tahun mendalami ilmu semacam ini.
Kiai berhadapan dengannya dalam jarak tiga meter dari pohon Kemuning itu. Kiai seolah ada di antara selangkangan makhluk itu, masih longgar pula adanya, diam, takzim, dan menunggu jawaban salamnya. Mahkluk itu berbulu di sekujur tubuhnya, melambai-lambai dihembus angin. Matanya merah menyala. Kuku-kuku yang ada dijemarinya tampak runcing mengkilat disinari terang rembulan. Tinggi badannya boleh jadi 10 meter, sama persis dengan tiang listrik. Kekar, kokoh, dan padat tubuhnya. Jika nyata adanya, barangkali kiai bakal lari terbirit-birit. Tapi ini mata bathin, sulit untuk dibayangkan orang semacam kita ini, bakal betah berlama-lama dengannya andai melihat dengan mata biasa.
Kira-kira mereka bercakap seperti ini.
Setelah saling menatap, dan diam, kemungkinan saling mengira-ngira batas kemampuan masing-masing untuk bertarung, mahkluk itu pun membuka dialog.
"ANDA SIAPA?
"Saya Kiai Cipancur."
"ADA URUSAN APA?
"Saya diminta tolong Kuwu Naya untuk menebang pohon Kemuning ini hingga tuntas."
"ASAL TAHU SAJA, SEBELUMNYA BEBERAPA ORANG TELAH DATANG. TAPI MEREKA SEMUA NGACIR. PADAHAL SAMPAI JUGA BELUM KE TEMPAT INI. TAPI ANDA BEGITU YAKIN. APA UPAH YANG ANDA TERIMA?
"Hanya uang 5 rupiah. Tidak lebih, dan tidak kurang, Baru dibayar 3 rupiah, sisanya 2 rupiah setelah tuntas pekerjaan ini.
"ANDA YAKIN SISA UANG ITU AKAN DITUNAIKAN?
"Saya yakin.
"BAGAIMANA JIKA TIDAK DITUNAIKAN."
"Kuwu sudah siap dengan segala resikonya."
Tanpa basa basi lagi mahkluk itu menyerangnya. Tapi kiai sudah siap dengan kemampuan yang dimiliki. Tentu pertempuran dahsyat menurut mata bathin tengah berlangsung alot. Hingga akhirnya kiai berhasil melumpuhkannya, dan dengan sendirinya akar dan pohon Kemuning itu bersih dari hamparan sawah Kuwu Naya.
Subuh menjelang kiai itu pun menemui Kuwu Naya yang tengah bersiap hendak menuju mushola. Kuwu Naya memperhatikan dengan cermat, kiai Naya tampak biasa saja sebagaimana keadaannya saat dimintai tolong.
"Bagaimana kiai?
"Alhamdulillah, sudah tuntas,"jawab kiai setengah menahan nafas berat, berat sekali seolah masih ada yang dipikulnya.
"Baiklah kalau begitu. Terima kasih sangat kiai atas bantuannya. Sisa uang dua rupiah saya akan berikan nanti siang, diantar oleh staf saya ke rumah kiai.
"Baiklah.
Keduanya pun bersamaan menuju mushola untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Usai itu kiai pamit, dengan segala beban yang dirasanya masih menindihnya di bahunya itu.
***
Jam menunjukkan pukul 12.30 siang hari. Matahari menyorot terang. Desa di mana kiai tinggal masih banyak warga yang beraktivitas. Sebagian tengah menjemur padi di jalan. Sebagian mengangkut hasil ladang, berupa ubi, singkong, dan kacang tanah. Beberapa orang juga tengah bersendau gurau di warung kopi Ceu Munah persis di depan sebelah kiri rumah kiai.
Ditunggu sesuai janji yang diutarakan Kuwu Naya, tak jua muncul staf desa datang ke rumahnya. Kiai maklum. Barangkali mereka masih di jalan. Sebab jarak antara desanya dengan desa pohon Kemuning itu amat jauh, sekitar 10 km. Satu hari itu kiai menunggu. Tapi tak jua datang.
Hari ke minggu, lalu bulan hingga tahun, beban yang dipikulnya sudah semakin membuat nafasnya pendek, dan terengah-engah. Bersamaan itu janji upah yang bakal ditunaikan juga tak kunjung ada kabar. Nyaris dua tahun kiai masih berharap akan datang utusan desa dari Kuwu Naya.
Namun di hari kamis malam Jumat Kliwon ia putuskan melepas saja apa yang ia kunci selama ini dalam tubuhnya. Kuwu Naya telah ingkar janji.
"Engkau pergilah wahai mahkluk jahanam. Aku tak sanggup lagi mengurungmu."
Bukan main gembiranya mahkluk itu. Juga tiada dapat digambarkan, malam itu, desa di mana kiai tinggal berguncang, bukan kediaman kiai saja, tapi satu desa berguncang sesaat setelah mahkluk itu dilepaskan, seolah ada gempa.
Kiai sudah memutuskan, dan tidak mau tahu lagi urusan selanjutnya antara mahkluk itu dengan Kuwu Naya. Ia hanya berserah diri pada yang Maha Kuasa.
***


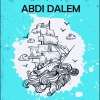
![Mengurangi Ketergantungan Beras [Bagian 1]](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/03/18/beras-bulog-65f72a2ede948f078b77eeb2.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)







