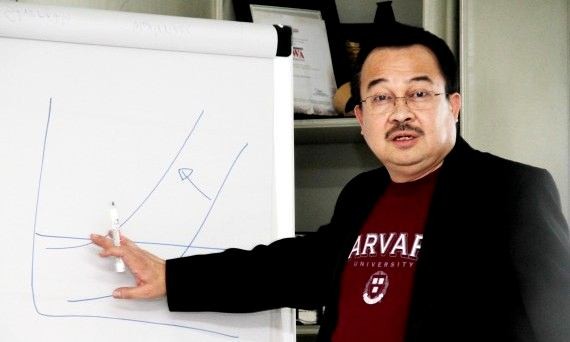[caption caption="Prof. Rhenald Kasali, Sumber: Tribunnews Aceh"][/caption]Saya selalu menikmati tulisan Prof. Rhenald Kasali yang bisa dipastikan tajam, kekinian, dan menggugah. Meski demikian, kali ini saya memberanikan diri untuk merespon tulisan beliau di Kolom Kompas.com kemarin, 22 Maret 2016, yang berjudul "Demo Sopir Taksi dan Fenomena Sharing Economy". Semoga dapat sedikit memperkaya diskusi kita tentang isu yang sedang menghangat ini.
Pertama, saya kurang sepakat dengan penggunaan istilah “sharing economy”. Saya lebih nyaman dengan istilah “digital collaborative consumption”, yang selanjutnya saya singkat DCC.
Kedua, DCC merupakan bagian kecil dari satu perkembangan yang lebih besar, yakni kemunculan “digital society”. Memahaminya dalam konteks yang lebih besar sangat membantu kita untuk mereproduksi solusi yang lebih komprehensif.
Ketiga, dalam logika yang lebih fundamental, fenomena-fenomena ini dapat lebih mudah dipahami sebagai konsekuensi dari penguatan “digital society” yang mendorong “perfect information” dan berujung pada “efisiensi”.
Mari kita diskusikan satu per satu. Sharing economy sendiri bukan merupakan istilah baru dan memang banyak digunakan untuk menggambarkan fenomena seperti yang dipaparkan Prof. Rhenald. Tulisan di Forbes, misalnya, pernah menggunakan istilah “share economy” untuk menggambarkan Airbnb; sedangkan artikel di Fortune juga menggunakan istilah “sharing economy” untuk menjelaskan Uber. Semuanya berasumsi bahwa istilah ini mampu mewakili aktivitas ekonomi yang bersifat “peer-to-peer-based sharing” dalam mengakses barang dan jasa baik secara konvensional maupun secara digital.
Bagi saya, jika aktivitas ekonomi itu melibatkan produsen dan konsumen yang terfasilitasi atau termediasi untuk melakukan proses jual-beli baik secara konvensional maupun digital, itu bukan “sharing” akan tetapi “selling/buying”. Konteks yang disebutkan Prof. Rhenald sebagai “tradisi orang tua kita yang hidup dalam sistem berbagi” memang lebih dekat dengan konsep “sharing”. Akan tetapi penggunaan aplikasi-aplikasi modern ini lebih dekat dengan konsep “selling/buying”.
Dalam hal ini saya lebih sepakat dengan tulisan di Harvard Business Review yang juga mengkritik penggunaan istilah “sharing economy”. Bedanya, mereka menawarkan istilah “access economy”, sedangkan saya mengusulkan istilah yang lebih spesifik yakni DCC. Sepertinya juga semakin banyak pengamat yang mengoreksi penggunaan istilah ini, seperti John Nughton yang sempat menuangkan kritikannya di the Guardian.
DCC saya pilih karena lebih mewakili fenomena riil di lapangan bahwa fenomena ini lebih sebagai proses “konsumsi” barang/jasa yang sifatnya “kolaboratif” dan “digital”. Dengan kata lain, ada kolaborasi antara 3 kelompok yakni sekumpulan penjual, fasilitator digital, dan pembeli yang bersebaran. Nah, DCC, atau dalam istilah Prof. Rhenald “sharing economy” ini mampu menjelaskan fenomena Airbnb, Gojek, Bukalapak, igrow, dan sejenisnya, tapi belum mampu menjelaskan konteks yang lebih besar dan jenis aplikasi digital yang lebih beragam.
[caption caption="Digital Collaborative Consumption dalam Masyarakat Digital"]

Digital Society sebagai Konteks yang Lebih Luas
Suka tidak suka, kita sedang memasuki tatanan sosial baru yang bernama digital society. Meminjam GSMA Intelligence, digital society mencakup tiga pilar, yakni digital citizenship, digital lifestyle, dan digital commerce.
Digital citizenship menggeliat cepat, mewarnai dinamika hubungan negara dan warga negara. Tidak heran kalau Kemendagri disibukkan dengan pengembangan digital identity atau lebih familiar dengan istilah e-KTP. KemPAN-RB dan Kemenkominfo juga tidak ketinggalan dengan penyusunan roadmap e-governance. Sedangkan daerah-daerah berlomba-lomba menjadi jawara pengembangan e-services seperti e-health, e-rapor, dan sebagainya. Helen Margetts menyebutnya dengan istilah Digital Era Governance (DEG), yang menggeser kejayaan New Public Management (NPM) dalam dunia administrasi dan kebijakan publik.
Pola interaksi baru ini juga sudah begitu kuat tercermin dalam digital lifestyle dengan semakin tumbuhnya digital literacy, atau masifnya perkembangan orang yang melek internet. Berbagai teknologi digital tidak lagi mampu dibendung penetrasinya ke semua usia, dari anak balita, sampai lanjut usia. Tak heran jika muncul istilah Internet of Things (IoT) yang berusaha memperluas daya guna internet ke berbagai aspek, seperti konektivitas antar benda secara virtual, remote control, dan sistem berbagi data. Celetukan “gak melek internet, gak gaul”, “gak pakai smartphone, gak kekinian” menjadi sangat lumrah. Internet menjadi gaya hidup yang tak terhindarkan.
Bagaimana dengan digital commerce? Kalau melihat geliat kelas menengah di perkotaan, siapa yang tak kenal mobile payments? Dengan beberapa kali klik, pembayaran sudah selesai tanpa harus repot-repot datang ke loket atau antre di kasir. Situs jual beli yang merajalela dan ribuan ibu rumah tangga yang bisa menjalankan bisnisnya sambil mengurus anak di rumah menjadi potret e-business dan e-entrepreneurship. Saya rasa konteks yang didiskusikan Prof. Rhenald banyak bersinggungan dengan pilar terakhir ini. Dengan kata lain, DCC atau “sharing economy” merupakan salah satu bentuk digital commerce.
Nah, pertanyaan selanjutnya: mengapa perkembangan ini tidak terbendung, makin populer, dan makin dilirik banyak orang, bahkan pemerintah? Prof. Rhenald sampai mengistilahkannya sebagai proses alamiah, sesuatu yang susah sekali untuk dihindari. Jika DCC terbatas menggambarkan sebagian kecil dari fenomena ini, mari kita coba melihat apakah konsep “perfect information” bisa menjelaskan fenomena digital society sebagai konteks yang lebih besar,.
Perfect Information dan Efisiensi
Perfect information yang lahir dari teori ekonomi ini “sementara saya pinjam” untuk menjelaskan perkembangan digital society. Secara sederhana, kita (atau institusi) harus mengambil keputusan dari banyak pilihan yang tersedia. Semakin banyak informasi yang ada tentang pilihan-pilihan tersebut, maka uncertainty atau ketidakpastian dapat semakin dikurangi. Dengan kata lain, certainty atau kepastian semakin meningkat dan mereka bisa menemukan pilihan yang “paling menguntungkan”. Pilihan orang yang paling menguntungkan ini tentunya menghasilkan efisiensi: bisa berupa uang, tenaga, waktu, energi, pikiran, dan sebagainya.
Mari kita pakai logika abstrak itu untuk menjelaskan digital citizenship, digital lifestyle, dan digital commerce (termasuk di dalamnya DCC). E-health di Surabaya, misalnya, mampu meningkatkan kelengkapan data medical record penduduk dan dapat diakses kapan pun dan di mana pun baik oleh dokter maupun pasien. Bahkan dalam perkembangannya, diharapkan pasien dapat membuat janji dengan dokter di puskesmas secara online. Artinya, informasi semakin perfect, uncertainty menurun, dan baik pemerintah maupun masyarakat menjadi lebih efisien dalam banyak hal.
Demikian juga dengan penggunaan Qlue oleh masyarakat Jakarta: informasi keluhan masyarakat semakin meningkat dan terdata secara sistematis, ketidakpastian informasi tentang masalah publik menurun, dan akhirnya pemerintah DKI mampu menghasilkan kebijakan yang lebih sistematis dan tepat sasaran.
Logika ini juga tentu mampu menjelaskan data Prof. Rhenald seperti ongkos taksi yang harusnya Rp 150.000 tetapi dihargai Rp 70.000; kamar penginapan yang permalamnya Rp 1 juta ditawarkan Rp 200.000, dan sebagainya. Tidak hanya menjelaskan lebih murahnya harga, tetapi “perfect information” juga mampu menjelaskan efisiensi-efisiensi lain yang dihasilkan dari sebuah DCC, seperti efisiensi tenaga, waktu, dan pikiran.
Dalam hal ini, perangkat digital membuat informasi tentang penawaran dan permintaan layanan angkutan dan penginapan semakin perfect sehingga memunculkan efisiensi.
Mari kita bandingkan: menunggu taksi di pengkolan dan menggunakan aplikasi untuk order taksi. Hampir pasti penggunaan aplikasi lebih efisien. Seperti Prof. Rhenald sampaikan, harganya kadang lebih murah. Selain itu, kita tidak perlu repot-repot nunggu di pengkolan yang panas karena kita bisa menunggu di kamar kos ber-AC sampai taksi datang dan menelpon kita. Waktu tunggu dan perkiraan waktu tempuh pun lebih pasti, sehingga lebih mudah mengusahakan untuk tidak telat datang janjian dengan kolega. Hemat uang, hemat waktu, hemat tenaga, hemat pikiran.
Meski ada banyak tantangan dalam perkembangan digital society di Indonesia, seperti ketidaksiapan infrastruktur, perangkat hukum, dan kultur konvensional masyarakat; saya sepakat dengan Prof. Rhenald bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah maupun penyedia layanan barang dan jasa konvensional untuk tidak segera "menyesuaikan diri" dengan potensi efisiensi yang luar biasa ini.
Dedy Permadi
Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM