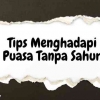Ketika beberapa tahun yang lalu environmentalis feminis Carolyn Merchant memproklamirkan "kematian alam", sebenarnya ia sedang meratapi carut-marut kebudayaan manusia modern saat ini. Bukan tanpa alasan ia bersuara lantang menjeritkan kegalauannya. Baginya, zaman dengan harmoni kosmos yang belum retak telah melewati episode gemilangnya. Dunia menjadi ladang kegilaan manusia untuk mengekspolarasi dan mengeksploitasi alam guna memuaskan nafsunya. Atas nama sains dan teknologi, manusia sanggup untuk menjadi pembunuh berdarah dingin untuk semata menyingkap dan menguasai rahasia dan kekuatan al
Alam pun tampak semakin tua dan ringkih. Merintih sekarat!. Mikro kosmos dalam diri manusia juga mengalami nasib yang tak kalah buruknya. Jiwa, tubuh, naluri, kehendak dan emosi kemudian dipaksa untuk melayani kepentingan sains di bawah pengawasan dan kekuasaan "nalar" yang menjadi sesembahan manusia modern. Bahkan imajinasi sebagai fakultas kreatif luhur manusia kemudian dipasung dan direndahkan di bawah hegemoni nalar sebagai fakultas analitis data dan benda-benda semata. Maka dimulailah babak baru zaman ini. Disharmoni alam dan manusia yang berujung pada ranah keterasingan, jauh dari firdaus peradaban manusia sebagai khalifatullah di muka bumi.
Itulah hasil dari proses peradaban modern yang sering dibangga-banggakan oleh "manusia berdasi". Kecanggihan teknologi digital dan gaya hidup yang serba instan telah menggiring kita pada kebudayaan tanpa rasa. Ketika pengetahuan empiris dari pendekatan matematis-mekanis ilmu alam diutamakan, maka wujud dunia seolah-olah hanya bisa dipahami melalui semata cara berpikir (nalar) fungsional. Dengan sifatnya yang abstrak, distingtif dan selektif, cara berpikir ini meniscayakan adanya proses elimenasi terhadap "yang lain" seperti alam, tubuh, rasa dan naluri. Korban paling tragis dari dominasi nalar ini adalah kaum perempuan yang bisa dilihat di awal zaman Pencerahan. Karena tugas reproduksinya yang dianggap belum lepas dari siklus alam, maka perempuan kemudian disingkirkan dari wilayah diskursif.
Dari sini dunia kemudian menampakkan watak telanjang materialistiknya. Dengan didukung oleh ideologi kapitalisme-liberal, dominasi nalar menggiring seluruh orientasi budaya manusia pada tiga modus procendi aktifitas peradaban yang menegangkan: usaha untuk memiliki, persaingan dan rasionalitas. Maka hilanglah kearifan spiritual dari keheningan jiwa kita. Pudarlah sensibilitas estetik dari relung-relung peradaban anak negeri ini. Yang ada hanya otoritas nalar dan pragmatisme hidup sesaat. Hidup dengan gaya hedonis dan semau gue. Gampang untuk melemparkan klaim kebenaran sepihak tanpa melakukan dialog dan pembacaan yang mendalam terhadap sejatinya persoalan. Bersikap fanatik dan hanyut terbawa arus fasisme gaya baru dalam beberapa sektor dan aspek sains, politik serta industri yang tega memanipulasi dan mengeksploitasi manusia lemah. Dan ini secara telanjang bisa kita lihat mulai dari istana presiden, di kantor-kantor birokrasi dan swasta, di mal-mal dan pusat perbelanjaan, di jalan-jalan protokol, bahkan di sekolah-sekolah kita.
Ketika dunia mulai mengenal Plato dari Yunani, kita tanpa terasa telah diajari tentang cara berpikir kalkulatif. Subyek dan obyek, ide dan realitas, pikiran dan tubuh, selanjutnya dipisah oleh garis demarkasi yang tegas dalam terminologi kaum filsuf. Kemudian datang konsep nalar dengan model "cogito Cartesian", yang menobatkan pikiran sebagai satu-satunya otoritas absolut bagi segala yang ada. Pada gilirannya konsep yang diusung Descartes ini mengilhami seorang Francis Bacon untuk mengkampanyekan pada dunia bahwa "pengetahuan adalah kekuasaan". Pengetahuan kemudian tidak berhenti pada fungsi teoritis-praktisnya saja, tapi juga sebagai senjata untuk menguasai dan menaklukan dunia.
Tapi kita toh tetap harus sadar bahwa dalam perjalanan sejarahnya, dominasi hegemonik nalar bukan sepi dari kritikan. "Revolusi Kopernikan" yang digagas Kant, serta ajaran Hegel bahwa "yang benar adalah yang menyeluruh", adalah sedikit contoh kerja keras para pemikir untuk menutupi lubang cacat pada pemikiran diskursif. Yang lebih ekstrim lagi kita kemudian disuguhi tontonan dramatis atas episode heroik gelombang kritik atas nalar modernitas. Mulai dari kritikan tajam kaum Romantik atas dominasi nalar pada alam dan manusia, atau kecaman pedas mazhab Frankfurt atas absurditas rasio instrumental dalam wacana modernitas, sampai revolusi strukturalisme yang meruntuhkan otoritas bahasa sebagai media penanda realitas sehingga kita melihat kebenaran kemudian berterbangan bagaikan buih ditiup angin.
Gambaran dari garis sejarah ini pun menyadarkan kita, bahwa kebudayaan, atau lebih umum lagi peradaban, tidak cukup hanya dibangun di atas dasar logika formal nalar diskursif dan kemudian abai terhadap konsep estetika sebagai refkeksi konseptual-filosofis atas ranah rasa dan imajinasi manusia. Bukan hendak meluruhkan cara berpikir fungsional, estetika hanya ingin memperkaya perspektif berbudaya kita. Ia ingin mengambil peran untuk mengisi "terra incognita" dari relung peradaban modern yang sering terabaikan. Sejarah telah berbicara bahwa sensibilitas berlebih dari para penyair misalnya, telah mengubah sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi indah. Menampakkan sisi-sisi artistik dari kehidupan, sekaligus mewedarkan lakon profetik kenabian karna syair dan karya seni yang baik selalu mampu mengatasi ruang dan waktu.
Tapi estetika tanpa pijakan epistemologi dan etika sosial yang jelas juga hanya akan melahirkan malapetaka peradaban lain: dunia yang chaos, liar tanpa norma dan keberpihakan, serta dibayang-bayangi hantu nihilisme yang mengaburkan makna kebenaran. Ranah rasa juga harus berani melakukan "social imaginary" melalui pencarian nilai tentang horizon makna yang menjadi rujukan bagi cita tatanan ideal yang ingin diperjuangkan. Oleh karenanya, seni dalam bentuk apa pun harus bersedia untuk dipengaruhi dan berdialektika dalam hiruk pikuk perubahan sosial, bahkan melakukan perubahan itu sendiri.
Pada pokok ini kita kemudian dihentakkan oleh agenda besar kebudayaan kita. Bahwa budaya tanpa rasa yang mengungkung alam bawah sadar kita harus dihempaskan dari rongga peradaban ini. Sediakan sedikit ruang "jalan lain" untuk anak-anak generasi kita agar mereka tidak selalu melihat segalanya secara hitam-putih, kawan-lawan, baik-buruk, dan distingsi normatif lainnya. Ajarkan bahwa sesuatu bukan hanya melulu dilihat dari hasilnya, tapi lebih pada bagaimana proses untuk menuju hasil itu diperjuangkan. Tumbuhkan kerendah hatian nalar mereka guna membiarkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan menyelinap dalam keheningan jiwa mereka. Inspirasikan, bahwa tidak selamanya rutinitas dan mobilitas itu "baik". Adakalanya diam itu lebih baik untuk kondisi dan hal-hal tertentu. Karena segala gerak kita untuk menjala cahaya dan merangkum pancaran warna bianglala, harus berakhir pada titik kontemplasi yang secara jujur membuka dialog antara "aku" dan kesadaran paling dalamnya. Antara arogansi keperkasaan diri dan rendah hatinya akal sehat.