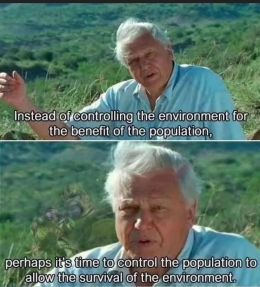Apapun yang kita lakukan, di manapun kita berada, tak dapat kita pungkiri bahwa kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Demikianlah komentar Martin Heidegger ketika memulai ulasannya di The Question Concerning Technology. Sebab tak ada lagi pilihan untuk melepaskan diri dari teknologi, yang dapat kita lakukan agar teknologi itu tidak justru menguasai kita adalah dengan menjaga jarak darinya.
Sayangnya, sudut pandang dalam memahami pemanfaatan teknologi justru membutakan pandangan kita akan fungsi dan tujuan dari teknologi itu sendiri. Umumnya, teknologi kita jadikan sebagai syarat untuk mencapai tujuan tertentu. Entah sebagai sarana yang memungkinkan suatu usaha dilakukan atau sebagai fasilitas yang memberikan kemudahan.
Secara etimologis, bangsa Romawi memahami teknologi dari sudut pandang kausalitas dari nomina causa dengan bentuk verba cadere yang berarti jatuh. Jadi sebuah akibat itu dijatuhkan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Bangsa Yunani memahaminya dari sudut pandang berbeda yakni kebergantungan dari kata aition yang berarti bergantung. Bahwa sebuah akibat itu bergantung pada hal lainnya.
Sebuah kacamata dibuat, dari sudut pandang kausalitas, karena kebutuhan untuk mengatasi pandangan yang rabun. Demikian pula smartphone dibuat karena pemakai ingin satu perangkat portabel yang mampu melakukan banyak hal tanpa merepotkan. Perangkat teknologis itu dibuat untuk mengatasi suatu persoalan yang muncul dan menjadi akibat mengapa perangkat itu perlu dibuat.
Dari sudut pandang kebergantungan, kacamata tadi hanya bisa dibuat karena adanya kaca sebagai bahan dasarnya (akibat material), pembuat dengan keahliannya (akibat efisien), konsep tentang bentuk dan ukuran (akibat formal), hingga fungsi dan tujuan mengapa sampai kacamata itu dibuat (akibat final). Bagi yang terbiasa dengan tradisi nalar Aristoteles, sudut pandang ini tentu tidak asing.
Terhadap sudut pandang kebergantungan ini, Martin Heidegger memandang bahwa tidak semua akibat diciptakan setara. Dari keempat akibat yang disebutkan di paragraf sebelumnya, akibat efisien yang diberikan oleh pembuat dengan keahliannya menempati posisi paling menentukan. Ketiga akibat lainnya; material, formal, and final bergantung pada dan tidak akan berguna tanpa peran pembuatnya.
Keahlian yang dimiliki oleh pembuat kacamata membuat ketiga akibat lainnya termanifestasikan kapasitas dan potensinya. Tanpanya, bahan dasar hanya akan berserakan begitu saja sehingga tidak akan mungkin menemukan bentuk dan ukuran yang sama sekali baru. Akibat itu kemudian memberikannya fungsi dan tujuan baru yang menyesuaikan bentuk dan ukurannya.
Nah, manifestasi kapasitas yang diwujudkan oleh peran pembuat dengan keahliannya inilah yang merupakan esensi dari sebuah teknologi. Hal itulah yang merangkum keempat akibat yang memunculkan suatu perangkat teknologis dan mengatur aspek pemanfaatannya. Sehingga, bagi Heidegger, teknologi tidak sekadar menyediakan sarana dan fasilitas namun juga sebagai usaha untuk memaknai cara bagaimana kita hidup.
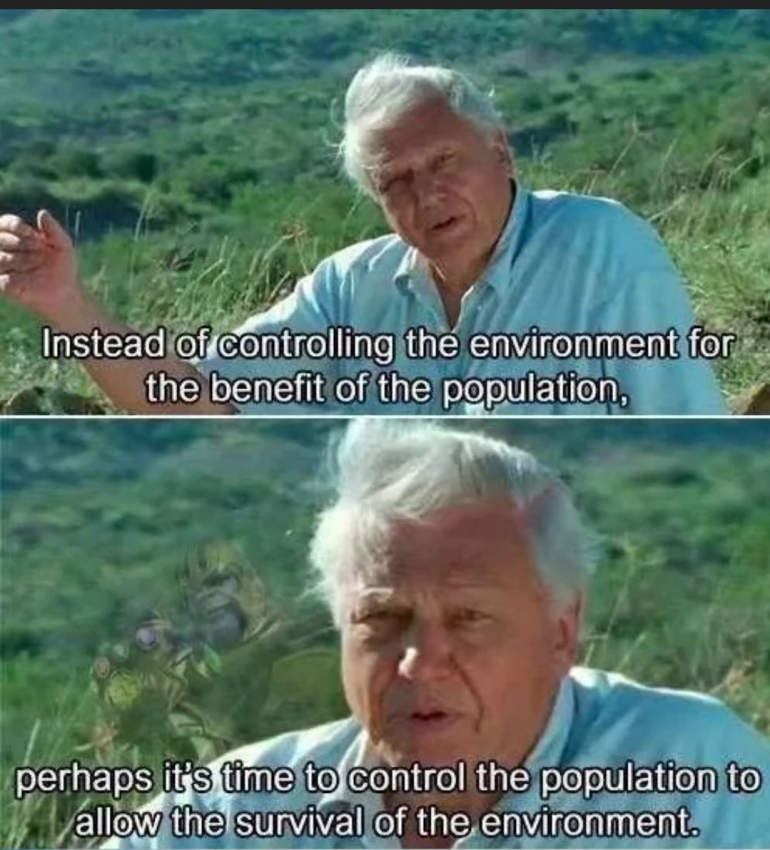
Aristoteles membedakan kedua kata itu berdasarkan objeknya. Jika episteme bermakna menyingkap suatu objek yang sudah ada maka techne bermakna menyingkap suatu objek yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi techne lekat dengan makna menemukan sesuatu yang baru.
Jadi pembuat kacamata tidak sekadar membuat kacamata namun juga menemukan kebutuhan yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Pengguna kacamata juga akan langsung mengenali benda itu sebagai kacamata karena fungsinya telah disesuaikan sedemikian rupa berdasarkan bentuk dan ukurannya.
Demikianlah teknologi, kreasi dalam menemukan suatu cara untuk mengatasi suatu masalah dan berkembang bentuk serta ukurannya sejalan dengan kebutuhan yang terus menerus beragam sesuai permintaan penggunanya.
Lalu, mengapa teknologi yang dibuat untuk memudahkan justru malah menimbulkan kecemasan?
Heidegger menjawab dengan alasan bahwa teknologi modern sangat membebani. Hal itu disebabkan oleh kreasi pemanfaatannya bersifat monopolistik dan cenderung menundukkan. Hal itu tentu berbahaya. Sebab konversi dari bahan dasar, terutama yang diekstrak dari alam, tidak lagi didasari oleh pertimbangan mutualisme antar makhluk namun menjurus pada maksud menguasai dengan menimbun.
Dulunya, teknologi memanfaatkan sumber daya dari alam lalu mendaurnya ke bentuk energi lainnya tanpa mengurangi sumber energi asal sama sekali. Bisa dikatakan bahwa kreasi pemanfaatan teknologi itu adalah bagian dari pelestarian alam itu sendiri. Teknologi kincir angin di masa lalu memanfaatkan angin yang berembus lalu mengonversinya ke energi gerak yang menjalankan mesin.
Teknologi modern tidak demikian. Sumber daya alam cenderung dikeruk dan dihabisi tanpa ada solusi untuk pelestarian serta pencarian alternatif. Energi yang diekstrak dari alam hanya ditimbun dan terus digunakan tanpa ada proses kreasi daur ulang. Lihat saja minyak bumi, batu bara, hingga kayu dari hutan terus dihabisi untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak kreatif dari manusia itu sendiri.
Sudut pandang pemanfaatan teknologi dari mazhab ini begitu sesat. Teknologi ini memandang bumi sebagai penyedia bahan dasar uranium, langit sebagai penyedia nitrogen, sungai sebagai penyedia listrik tenaga air, hingga sawah dan kebun petani sebagai penyedia pangan yang bisa dibeli dengan harga murah begitupun dengan kawasan konservasi sebagai destinasi wisata.
Teknologi modern memaksa dunia untuk menampakkan sumber daya yang bisa ia tawarkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Semua sumber daya mesti disediakan dengan segera, selalu bisa dipesan setiap saat, untuk segera diolah lalu didistribusikan dalam siklus penawaran dan permintaan. Heidegger menyebutnya sebagai 'simpanan potensial' di mana warisan masa lalu baik dari bumi maupun dari peradaban manusia tidak lebih dari sekadar stok persediaan yang bisa dipesan kapan saja.
Parahnya, sudut pandang ini juga menyesatkan cara kita mengonsumsi sumber daya lewat pemanfaatan teknologi. Lihat saja ketika kita dilanda listrik padam atau kelangkaan BBM. Negara akan menghadapi kondisi siaga satu yang bisa memicu pemberontakan publik sebab mereka tidak bisa melakukan sesuatu tanpa adanya energi yang biasanya disediakan oleh sumber-sumber tersebut.

Sudut pandang ini benar-benar menjebak dan memerangkap alam dalam fungsinya hanya sekadar daya koheren yang selalu bisa diukur dan dihitung untuk kepentingan menopang aktivitas manusia.
Untungnya, penyakit mental yang disebabkan oleh sudut pandang ini masih dapat dinetralisir dengan mengambil jarak untuk berkontemplasi akan relasi kita dengan pemanfaatan teknologi dan perangkat teknologis sebelum hal-hal itu memperbudak kita dalam belenggu konsumerisme.
Ada pilihan yang sepenuhnya dalam kendali kita: menjadi budak konsumerisme yang hidupnya bergantung pada ketersediaan sumber daya atau menjadi bebas dengan memahami siklus mutualisme antar makhluk dan memastikan proses daur ulang energi sembari mengembangkan solusi alternatif.
Memandang alam sebagai penyedia stok bahan dasar dan sumber daya akan mematikan daya kritis kita terhadap tafsir baru pengembangan teknologi. Mengapa demikian?
Karena hal itu akan memosisikan diri kita pada akibat final yang justru menjadi sasaran tujuan dan fungsi dari teknologi tersebut. Padahal, harusnya kita berada pada posisi akibat efisien yang mendefinisikan bentuk dan ukuran baru dari suatu bahan dasar sehingga muncul tujuan dan fungsi yang juga baru dalam pemanfaatannya.
Manusia tidak bisa terus berpura-pura memosisikan diri sebagai 'penguasa' alam yang mengatur jalannya distribusi sumber daya melalui teknologinya sendiri.
Sebab manusia sendiri sangat bergantung pada alam. Teknologi mesti dipahami dalam kerangka membantu manusia melakukan pembacaan terhadap pemanfaatan sumber daya.
Teknologi tidak melulu soal mengungkap potensi alam namun yang lebih penting adalah potensi hasrat dan nalar kritis dari manusia itu sendiri untuk mengatasi ketidakberdayaannya di hadapan kedigdayaan alam.
Smartphone dan Konflik Identitas
Dari sudut pandang kausalitas, tradisi memaknai perangkat teknologis warisan peradaban Romawi, internet dengan jaringan dan layanan begitu luas membutuhkan perangkat yang mampu mengatasi kebutuhan komunikasi, profesi, hingga hiburan.
Jika dulunya kebutuhan itu membutuhkan perangkat terpisah, sekarang fasilitas dari perangkat-perangkat itu disematkan pada satu perangkat: smartphone.
Perangkat yang tidak bisa semenitpun lepas dari genggaman tangan kita ini merupakan portal ke segala dunia yang sekaligus membangun karakter kita di dunia yang berbeda pula.
E-mail dan sistem informasi terpadu instansi memoles karakter profesional kita di bidang di mana kita bergelut, media sosial merangkai karakter imajinatif sekaligus obsesif sesuai ketertarikan dan mimpi kita, begitu pula dengan layanan streaming media yang melepaskan karakter bebas serta ekspresif mengikuti suasana hati dan selera hiburan yang kita pilih.
Smartphone merupakan perangkat yang tidak hanya menjembatani kita dengan jaringan yang terlampau luas untuk kita jangkau namun juga menyimpan beragam identitas yang kita siapkan untuk berganti secepat usapan jari jemari di layar perangkat.
Di postingan karya kreasi terkadang kita menjadi pribadi yang rendah hati namun di postingan media sosial kita bisa berubah menjadi pribadi temperamental terhadap opini yang berseberangan dengan sudut pandang kita. Karakter-karakter yang menjadi bagian dari serpihan konsep diri kita termanifestasikan pula dalam perangkat smartphone yang kita punya.
Sehingga bukan lagi akibat kebutuhan kita mengatasi peran-peran kita di dunia profesional maupun di dunia keseharian, smarphone sebagai perangkat teknologis justru kemudian menjadi alasan bagi kita untuk menciptakan, atau menyempurnakan, konsep smartphone yang menyesuaikan dengan identitas baru yang coba kita bangun.
Smarphone tidak lagi menjadi hasil akibat dari peristiwa sebelumnya namun menjadi akibat bagi peristiwa yang belum sepenuhnya terjadi.

Saat tujuan itu tidak tercapai karena fungsi smartphone tidak sesuai, atau tidak kita ketahui potensinya, maka kekecewaan yang muncul sangatlah mendalam.
Mengapa demikian? Sebab kita memandang smartphone sebagai perangkat teknologis yang punya 'simpanan potensial' yang setiap saat harus menyediakan stok persediaan bagi kebutuhan psikologis kita. Kita ingin bersosialisasi di media sosial dan smartphone menyanggupi itu. Namun, kita ingin lebih, identitas pribadi yang kita tampilkan di media sosial harus mendapat pengakuan dari warganet lainnya. Ini yang di luar kuasa smartphone.
Akibatnya, bullying di media sosial dampaknya sangat mendalam sebab pribadi yang menjadi korban menganggap bahwa ketika internet menolak tawaran identitasnya itu berarti seluruh orang di dunia nyata juga menolak dirinya. Padahal tidak demikian, hanya sudut pandangnya saja yang dibatasi oleh pemaknaannya terhadap pemanfaatan smartphone tersebut.
Dari sudut pandang kebergantungan, pemilik smartphone tampaknya cenderung memosisikan diri pada penerima akibat bukannya sebagai pemicu akibat.
Sehingga konsep dirinyalah yang didefinisikan oleh smartphone alih-alih dirinya yang seharusnya mendefinisikan smartphone sebagai saru dari sekian banyak perangkat teknologis yang memudahkannya dalam mengatasi masalah teknis.

Belanja paket data, upgrade perangkat ke seri atau model terbaru, hingga pemenuhan aksesoris sebagai bagian dari identitas pemakai kemudian masuk dalam kategori kebutuhan dasarnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, melampaui kebutuhannya akan pangan atau rasa aman.
FOMO (fear of missing out) atau takut ketinggalan momen kebersamaan dengan kelompok sosialnya merupakan jenis kecemasan yang muncul akibat interaksi berlebihan di media sosial. Gangguan psikologis ini muncul akibat kebergantungan terhadap akibat final dari perangkat smartphone yang dipahami oleh pemiliknya sebagai satu-satunya moda yang menghubungkannya ke kehidupan sosial.
Demikian pula dengan harapan besar terhadap perangkat teknologis yang tidak dibarengi dengan kemampuan kritis pemiliknya. Sebab pemiliknya lebih percaya akan kemampuan perangkatnya ketimbang kemampuannya sendiri.
Ini merupakan salah satu aspek yang membuat proses E-Learning yang dulu digaungkan akan merevolusi interaksi kelas menjadi gagal total dalam implementasinya.
Bahkan e-book belum bisa menandingi buku yang sampai hari ini masih lebih laku dan diminati oleh sebab portabilitas dan dukungan perangkat yang ditawarkan e-book dianggap belum sebanding dengan energi yang dibutuhkan untuk menampilkannya.
Dalam kasus ini, kesederhanaan buku cetak dianggap merepresentasikan daur ulang dari siklus mutualis alam itu sendiri atau singkatnya; power saving.
Smartphone tidak lagi dipandang sebagai ekstensi dari tubuh yang mengatasi kekurangan tubuh itu sendiri. Lebih dari itu, pemilik smartphone bahkan memindahkan dirinya dengan menitipkan konsep diri beserta masing-masing karakternya ke perangkat tersebut.
Bahkan dari temuan studi psikologi mutakhir, pemilik smartphone yang perangkatnya jatuh atau hilang mengalami sensasi near death experience (panik menjelang kematian) akibat peristiwa itu.
Seperti kata Martin Heidegger tadi, teknologi modern seperti smartphone sangatlah membebani. Membebani akibat materialnya (karena ketergantungannya pada konsumsi energi) maupun akibat efisiensinya (di mana pemilik tidak lagi dapat memisahkan diri dari perangkatnya). Sifatnya monopolistik karena ia tidak menawarkan bentuk ekspresi diri pemilik selain mengemis pengakuan warganet lewat karakter yang tunjukkan di media sosial.
Selain itu, sifatnya juga menundukkan. Pemilik, setelah memiliki perangkat smartphone, tidak lagi mampu melepaskan diri dari kewajiban yang melekat padanya: isi paket data tiap bulan, update status di media sosial setiap saat, hingga transaksi jual beli online.
Perangkat ini anehnya menciptakan kebutuhan yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh manusia. Padahal, harusnya dengan hadirnya teknologi smartphone, kebutuhan manusia harusnya tercukupi seperti dengan hadirnya teknologi kacamata yang mengatasi masalah pandangan.
Smartphone bukanlah sekadar alat atau perangkat teknologis sebab ia mendefinisikan keberadaan kita di ruang lainnya, internet misalnya. Bahkan, perangkat ini sudah mampu menciptakan kelas sosialnya sendiri seperti dalam kasus militansi pemilik iPhone atau kasta Sultan pemilik smatrphone dengan spesifikasi paling mutakhir.
Oleh sebab itu, kita mesti memperbaiki sudut pandang dalam mendefinisikan ulang relasi kita dengan perangkat teknologis yang kita ciptakan sendiri.
Seperti pendekatan Aristoteles, techne mesti berkaitan erat dengan episteme. Kreasi menciptakan hal baru mesti menempatkan pembuatnya pada tataran kontemplatif yang menentukan tujuan dan fungsi dari perangkat yang dibuatnya.
Bukan malah sebaliknya; ditundukkan dan terkungkung oleh pemaknaan monopolistik yang menjemukkan.
Mungkin dari beberapa akibat fatal yang diakibatkan kesalahan pembacaan kita dalam memaknai pemanfaatan teknologi, kita mesti mempertimbangkan saran Martin Heidegger.
Bahwa perangkat teknologis merupakan salah satu jalan bagi kita untuk memaknai hidup dan interaksi kita dengan lingkungan. Kita adalah agen harmoni yang menjaga ketersediaan dan keseimbangan sumber daya dalam siklusnya yang mutualis.
Mari tanyakan kepada diri kita, dalam meneguhkan peran kita sebagai akibat efisien, akankah kita mengorbankan alam beserta sumber dayanya untuk teknologi selanjutnya yang ingin kita bangun?
Atau, apakah dengan teknologi yang kita kembangkan mampu menuntun kita semakin mengenal sekaligus melestarikan alam dan seluruh potensinya?



![Mengurangi Ketergantungan Beras [Bagian 1]](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/03/18/beras-bulog-65f72a2ede948f078b77eeb2.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)