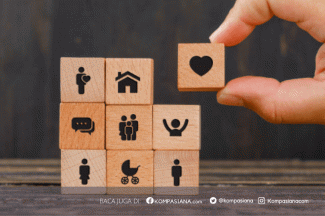Di era digital, kecepatan jempol sering kali lebih tinggi daripada kecepatan nurani. Satu potongan video bisa menjelma menjadi alat penghakiman massal. Begitulah yang terjadi pada sekelompok siswa SMP di Lombok Timur yang viral karena ucapannya saat menyantap MBG beberapa waktu lalu.
Potongan video itu menyebar luas, menjadi bahan olok-olok, dan memancing komentar tajam dari warganet. Sayangnya, siapa yang pertama kali menyebarkannya tidak pernah dijelaskan secara terbuka, meskipun pihak sekolah disebut-sebut sudah mengusutnya. Sementara itu, opini publik sudah telanjur menjatuhkan vonis.
Anak-anak itu menjadi santapan empuk media sosial. Kalimat seperti "tidak beradab", "tidak pantas jadi siswa", bahkan "cocoknya dibuang ke comberan" bertebaran di ruang komentar. Dunia maya mendadak berubah menjadi ruang sidang, dan para warganet tampil sebagai hakim tanpa mempertimbangkan usia dan konteks.
Saya ikut menanggapi, bukan untuk membela perilaku anak-anak itu, tetapi untuk menyoroti bahaya perisakan (bullying) yang mereka alami. Bahwa mereka salah, iya. Namun mereka tetap anak-anak. Cara kita melihat dan memperlakukan mereka semestinya melalui pendekatan pendidikan, bukan penghukuman publik.
Yang mengkhawatirkan, sekolah justru terkesan ingin segera cuci tangan. Indikasinya jelas ketika sekolah memfasilitasi pembuatan video permintaan maaf yang kemudian disebar luas oleh para konten kreator. Sekolah seolah lebih takut kehilangan reputasi ketimbang melindungi psikologis peserta didiknya sendiri.
Video permintaan maaf itu menyebar tanpa pendampingan guru, memperlihatkan bahwa kepentingan menjaga citra lebih diutamakan daripada proses pembelajaran nilai. Sekolah terlihat berupaya menenangkan publik, tetapi melupakan tanggung jawab moral terhadap perkembangan kepribadian dan harga diri anak-anak yang sedang tumbuh.
Para konten kreator pun ikut berpesta. Mereka menggandakan video itu, menambahkan komentar sinis, dan memelintir narasi sesuka hati demi tayangan viral. Mereka lupa, menyebarkan wajah dan identitas anak di bawah umur tanpa izin adalah pelanggaran etika yang bisa berimplikasi hukum serius.
Sayangnya, dunia maya kini dikuasai para pemburu sensasi yang miskin literasi anak. Mereka menganggap semua yang trending boleh disebar, semua yang "mengundang reaksi" sah dijadikan bahan konten. Padahal di balik layar, ada jiwa muda yang bisa terluka dan kehilangan rasa percaya diri.
Lalu apa hasil yang sebenarnya diharapkan sekolah dari video permintaan maaf itu? Tidak ada hasil pendidikan yang muncul, selain memperpanjang rantai trauma bagi anak. Yang diuntungkan hanyalah para pemburu konten yang kenyang sensasi dari derita bocah yang belum paham dunia dewasa.
Lebih jauh, kasus ini seharusnya membuat kita berkaca. Barangkali anak-anak itu hanyalah refleksi dari lingkungan yang kita ciptakan sendiri --- lingkungan yang penuh kekerasan verbal, hinaan, dan ejekan yang tiap hari kita konsumsi di media sosial tanpa sadar menirunya dalam keseharian.