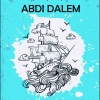Menjadi orang terkenal mungkin pernah dicita-citakan banyak orang, terkenal dalam bidang apa saja. Di antara banyak profesi untuk bisa jadi terkenal, paling banyak ya jadi artis --selebritis, kalau istilah sekarang. Tapi itu tak gampang, perlu modal. Rumus paling umum ya soal tampang, kalau nggak cantik atau ganteng sekali, ya ancur sekali. Itu rumusan baku. Orang dengan tampang sedang-sedang saja susah tembus pasar, kecuali masuk rumus kedua; hoki alias bejo.
Saya juga begitu. Dari dulu pengen jadi orbek, orang beken. Tapi dalam bidang apa?
Mulanya pengen jadi artis juga. Kalau dengerin musik rock pas bagian solo gitarnya, suka ikutan bergaya ala Slash Guns N Roses; sapu jadi gitarnya. Belakangan rada kreatif, bikin gitar-gitaran listik dari tripleks dan dicat, rada mirip ketimbang sapu. Tapi itu juga saya yakin gak bakalan sukses, wong sampai sekarang tak pernah belajar gitar dengan serius. Padahal teman sekelas di SMA dari 42 orang, 27 diantaranya cowok, 23 di antaranya bisa main gitar. Beberapa bisa disebut level jago.
Geser dikit pengen jadi artis film. Ikutan teater. Lumayan juga kalo ini. Latihan serius, ikut pentas sana-sini. Pernah jadi aktor terbaik festival teater pelajar. Kelas tiga SMA karir mulai menanjak. Ada yang ngajak ikutan main sinetron (judulnya lupa), bintangnya Desy Ratnasari yang lagi naik daun sejak sinetron Lelaki dari Tanjung Bira dan Sengsara Membawa Nikmat. Lumayan, dapat peran figuran; jadi loper koran. Sukses dengan peran tanpa nama itu, dilanjut dengan yang lain. Syutingnya di Pangandaran yang dulu jadi lokasi favorit film-film kolosal semacam Saur Sepuh. Tapi terpaksa mengundurkan diri, Ebta dan Ebtanas (model UAN jaman itu) sudah menjelang. Satu hari menjelang Ebta, saya balik ke sekolah. Habis itu lulus, lanjut kuliah di Makassar. Karir seni peran berhenti.
Di Makassar jatuh hati pada karir lain yang punya potensi jadi orbek meski kelas lokal; jadi penyiar radio. Waktu itu, jadi penyiar radio tampak sangat mengasyikkan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Bisa jadi pekerjaan sambilan, dapat duit, terkenal.
Terbayang keasyikannya. Saya teringat sebuah novel Hilman Hariwidjaya --si pencipta tokoh Lupus---yang bercerita tentang penyiar radio, Olga dan Sepatu Roda, yang kemudian difilmkan dengan bintang Desy Ratnasari dan Nike Ardilla.
Tahun 95, bersama dengan seorang teman cewek yang masih SMA, ikutlah audisi jadi penyiar radio FM yang sedang naik daun di Makassar; Sonata FM. Saya gagal. Meski gaya saya lumayan 'masuk,' takdir berkata lain; suara saya cempreng, nggak enak didengar ketika berhadapan dengan peralatan audio. Sementara teman saya yang cewek lulus; modalnya memang bagus, dia juga penyanyi yang sering menang kontes. Maunya jadi penyiar, malah jadi pengantar penyiar yang mau siaran...
Tapi teman saya itu berbaik hati mencarikan saya tempat. Datanglah sebuah tawaran dari radio lain, radio AM, radio keluarga. Bukan sebagai penyiar tetap, tapi sebagai pengisi acara mingguan. "Kang, radio itu butuh penyiar acara lagu-lagu daerah Nusantara. Yang Sunda kosong, penyiar sebelumnya pulang kampung. Mau nggak?" tanyanya. Saya mengiyakan.
Orang Sunda yang merantau ke Makassar cukup banyak. Catatan Kerukunan Warga Jawa Barat (KWJB) menyebut ada sekitar 15 ribu orang di seluruh Sulsel, itu yang tercatat, yang tidak, mungkin lebih banyak lagi. Profesinya beragam, dari tentara, pegawai BUMN (terutama Pos dan Telkom), dan yang paling banyak; tukang kredit yang nyaris ada di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Itu adalah pasar bagi radio itu, apalagi memakai gelombang AM yang jangkauan siarannya jauh lebih luas.
Saya pun mendaftar. Dan diterima. Suara cempreng saya tak dipermasalahkan. Mungkin pertimbangan utamanya adalah bahasa, dan jelas saya lulus dalam hal itu, saya kan jelas keturunan USA (Urang Sunda Asli). Jadilah penyiar di situ, seminggu sekali, setiap hari Rabu sore selama dua jam. Pihak radio makin senang, karena ternyata jumlah koleksi kaset lagu Sunda yang dimilikinya, kalah dengan koleksi punya saya, lebih baru pula. Pendengar juga senang dengan gaya slebor saya. Telepon studio ramai, permintaan lagu melonjak. Penggemar lumayan banyak, ibu-ibu...
Apa boleh buat, maksud hati pengen dikenal di kalangan anak muda Makassar, malah digandrungi ibu-ibu yang pengen nostalgia dengan lagu-lagu Sunda, lagu kampung halamannya nun jauh di sana. Yaah, tapi lumayan lah, daripada manyun.
Sayangnya, karena desakan pasar, dan katanya persoalan kepemilikan, radio itu tutup, mau pindah ke jalur FM dengan mengambil segmen yang berbeda. Karir penyiar saya hampir tamat.
Teman cewek tadi menawarkan posisi lain, di radio FM baru yang mengusung lagu-lagu dangdut. Duh, kok malah pindah aliran? Tapi saya terima. Dua bulan siaran sama dia --karena satu induk manajemen, teman saya itu juga dipinjamkan sementara selama siara percobaan. Sayangnya, ketika akan siaran beneran, saya digusur. Datang rombongan penyiar lagu dangdut lawas yang bedol desa dari radio AM lain yang bangkrut. Saya tahu, suara cempreng saya lagi-lagi pasti penyebabnya. Kalaupun dua bulan itu dibiarkan cuap-cuap, yak arena siaran percobaan, daripada kosong...
Karir penyiar radio saya mandek. Saya sakit hati, tapi lama-lama ya sadar diri, hehe... Saya kembali ke habitat awal, fotografi dan pers kampus.
Sampai akhirnya tahun 1999, saya bergabung dengan sebuah LSM kajian media. Saat itu, setelah reformasi, banyak proyek-proyek demokratisasi media dengan pendanaan dari luar negeri, USAID, AUS-AID, DFID, dan lain-lain. Duitnya menggelontor. Meski belum lulus kuliah yang tinggal skripsi saja itu, saya diterima di LSM itu, namanya Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (eLSIM). Gajinya lumayan besar untuk ukuran waktu itu, apalagi untuk mahasiswa.
Bersama seorang kawan, adik kelas di kampus, saya jadi tulang punggung di situ. Bagian analisis dan kajian media; kegiatan utama LSM itu selain penyelenggaraan berbagai workshop jurnalisme untuk para wartawan. Uang yang cukup berlimpah kemudian dialihkan oleh para petinggi LSM untuk membangun sebuah radio berita. Ini terinspirasi oleh Radio Utan Kayu yang didirikan sejawat LSM lain yang satu jaringan di Jakarta, yaitu ISAI (Institut Studi Arus Informasi).
Karena dasarnya suka, dan merasa punya pengalaman, saya ikut cawe-cawe di radio itu, termasuk membuatkan logonya, Radio Independen, namanya. Jingle radio juga saya buat, yang isi suaranya adalah Rosa yang 'memelesetkan' lagu Tegar miliknya yang sedang hits. Saya merekamnya lewat saluran telepon. Diotak-atik dikit, hasilnya mantep.
Masa percobaan, ikutan siaran juga. Malah keasyikan. Sampai akhirnya 'diusir' oleh bos. "Jangko siaran, urus saja kajian media!" Saya maklum. Mungkin si Bos juga sakit kupingnya denger suara saya. Lagipula, kegiatan memang lagi banyak-banyaknya, kerjaan lagi numpuk-numpuknya. Sementara saya malah haha hehe cuap-cuap nggak jelas...
Ya sudah, tamatlah sudah 'karir' sebagai penyiar radio saya. Habis itu, tak pernah mau nyoba lagi. Tapi setidaknya saya sudah pernah merasakannya meski bukan sebagai penyiar profesional. Pernah punya penggemar juga meski emak-emak, hehe...
Yaah setidaknya saya belajar satu hal, bercita-cita memang boleh, tapi kadang juga harus tahu batasan. Ibarat mau jadi tentara tapi tinggi badan aja nggak nyampe, mendingan urung saja, namanya melawan takdir. Mau jadi penyiar radio tapi suara cempreng, mendingan mundur, kasian pendengar. Masih banyak profesi lain yang mungkin lebih cocok, dan mungkin malah lebih dinikmati nantinya.
Buktinya, setelah menjadi dosen, hobi cuap-cuap dan nyerocos itu ada gunanya juga, tinggal masukan materi aja. Pendengarnya ada juga meski hanya beberapa puluh orang; itupun kadang sambil terkantuk-kantuk, padahal saya tak memutarkan lagu pengantar tidur! Jangan-jangan, suara saya bukan cempreng, tapi lebih cocok jadi pengantar tidur...