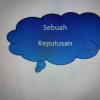Teringat menjelang Pilkada DKI lalu, Yusril Ihza Mahendra yang berkeinginan untuk maju sebagai cagub, aktif bersuara di berbagai media digital termasuk medsos dan televisi. Tujuan utamanya adalah untuk mengkampanyekan dirinya. Selain itu juga untuk terus mereduksi elektabilitas Ahok sebagai incumbent yang masih tinggi di berbagai survey saat itu.
Hal itu dilakukan di tengah-tengah kesibukannya mendatangi hampir semua partai, baik yang berbasis nasionalis ataupun agama. Tujuannya untuk meloby dan meminta agar partai meminangnya sebagai calon gubernur. Saat itu, Yusril boleh dikatakan cukup berhasil menurunkan popularitas dan elektabilitas Ahok, sehingga ada potensi untuk dikalahkan. Sekedar catatan, Ahok masih belum terpeleset kasus penistaan agama saat itu.
Yusril juga tekun mengikuti segala proses internal partai-partai tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan tiket dukungan. Tapi, fakta lapangan berkata lain. Yusril yang awalnya begitu yakin akan mampu mendapatkan kendaraan partai dan memenangkan pilkada, menjadi tertegun, kaget dan gamang setelah mendapati sikap partai yang berubah-ubah.
Semakin lesu dan tidak bergairah ketika sadar bahwa partai, terutama elite parti mengambil sikap pragmatis sempit. Partai-partai tersebut tidak mau memberinya tiket karena merasa terancam bila dia sukses di pilkada. Para elite partai tidak ingin Yusril dan partainya menjadi besar kedepannya.
Akhirnya Yusril pun lempar handuk sebelum bertanding karena kalah oleh pragmatisme sempit elite partai. Kepentingan elite partai lebih dominan dibanding kepentingan yang lebih luas. Maka tidak heran kemudian munculah sang anak, dan orang yang 'bisa dikendalikan' sebagai pilihan. Tanpa melihat kualitas si calon.
*****
Rupa-rupanya, belajar dari pengalaman pilkada DKI, Yusril pun mengambil sikap pragmatis demi membesarkan dirinya dan partainya. Dia yang politisi religius namun juga nasionalis, dengan terbuka dan tanpa malu-malu meminta pendukung ex-HTI untuk bergabung dengan partainya. Dia calonkan juga para elite pendukung khilafah tersebut untuk maju bertarung merebut kursi parlemen melalui partainya di tahun 2019 nanti.
Semua itu dia lakukan semata-mata pertimbangan pragmatis untuk kepentingan dirinya dan partainya. Yusril tahu, bahwa market share pemilih Partai Bulan Bintang dari kalangan nasionalis dan Islam moderat sangatlah minim dan belum cukup aman untuk melewati batas minimal Parliamentarythreshold sebesar 4%.
Untuk itu, dia sengaja melakukan diferensiasi pemasaran bagi partainya. Yusril sengaja mencipta trade marked bahwa partainya wellcome terhadap pendukung khilafah. Dia yakin, jumlah pendukung dan simpatisan khiilafah akan cukup untuk membawa partainya membesar, syukur-syukur masuk 5 besar.
Yusril sudah jenuh dan tidak mau lagi dicuekin oleh parta-partai lain dalam setiap proses pengambilan keputusan penting, terutama tentang kepemimpinan nasional. Dia sepertinya tidak ingin hanya pandangan dan keilmuannya saja yang menarik dan dihargai, namun dirinya sendiri tidak dilirik sebagai calon pemimpin masa depan gegara partainya yang gurem.
Apakah ini berarti dia akan merubah pandangan ideologinya menjadi seperti HTI? Secara pribadi, saya tidak yakin Yusril akan melakukannya. Kewarasan pikirnya membuatnya masih akan sangat cinta NKRI dengan Pancasilanya.
Menurut penulis, Yusril hanya bertindak pragmatis saja demi kepentingan partainya. Dia akan bersikap netral pada pilpres kali ini, karena dengan Prabowo menolak hasil itjima ulama 212, maka sudah tidak ada alasan untuk mendukungnya.
Yusril saat ini hanya akan fokus di pileg dengan mengkapitalisasi secara maksimal suara dari para pemilih yang 'rindu khilafah' tersebut, untuk kemudian mengejar mimpinya menjadi orang nomer satu negeri ini.
*****
Begitu juga dengan Megawati saat mengajukan Jokowi sebagai capres pada tahun 2014 lalu. Pertimbangan pragmatis yang diambil. Dia sadar, bahwa akan sulit untuk menang melawan Prabowo yang sangat kuat saat itu. Selain itu, adanya dorongan dari banyak pihak, baik internal partai maupun luar untuk memilih Jokowi sebagai capres.
Akhirnya, setelah yakin bahwa Jokowi bakalan tetap 'manut' jika terpilih sebagai presiden, maka Megawati pun bersedia hanya sebagai Queen maker saja dan 'mengutus' Jokowi untuk maju sebagai capres. Hasilnya, meski harus tetap 'manut' pada sang Ibu, Jokowi adalah presiden yang cukup berhasil membangun negeri ini dibanding para pendahulunya.
Sementara Jokowi sendiri dalam menentukan KH. Ma'aruf Amin sebagai cawapresnya juga hanya pragmatisme sempit sebagai pertimbangan. Akibat tekanan sebagian elite partai pendukungnya, terutama PKB dan PPP yang mendapat support dari PB NU, membuat Jokowi mencoret Mahfud MD dan menggantinya dengan KH. Ma'aruf Amin sebagai cawapres.
Jokowi, yang ingin menjaga kekompakan partai-partai pendukungnya, terpaksa memPHP Mahfud MD pada detik-detik menjelang deklarasi, dan membiarkannya kaget sendirian dengan baju putih barunya. Mahfud MD, yang menurut Jokowi sendiri dan banyak orang waras adalah sosok yang pas buat mewujudkan nawacita demi kebaikan negeri, tergeser karena pertimbangan pragmatis sempit individu elite partai.
Begitu juga PB Nahdlatul Ulama. Dengan pertimbangan pragmatis kepentingan organisasi, 'terpaksa' harus menyangkal bahwa Mahfud MD adalah kader mereka. Sebagai alternatif, menganjurkan KH Ma'aruf Amin sebagai cawapres kepada Jokowi jika ingin mendapat dukungan secara maksimal dari NU.
Cak Imin dan M Romahurmuziy juga sama saja. Dengan pertimbangan pragmatis sempit untuk kepentingan diri sendiri, maka Mahmud MD harus dicoret, agar kans mereka di tahun 2024 tetap ada, tidak tertutup oleh keberadaan Mahfud MD.
Kalau dilihat secara jernih, sebenarnya Mahfud MD adalah warga NU tulen. Dia punya kapasitas intelektual dan integritas yang sangat baik, serta diterima secara luas oleh banyak kalangan. Hal ini bisa menjadi entry point bagi NU dan Islam Nusantara pada umumnya, yang punya kans besar untuk mengambil alih kepemimpinan nasional pada tahun 2024 melalui Mahfud MD sebagai capres.
Namun karena hanya pertimbangan pragmatisme sempit, maka kesempatan seperti era Gus Dur harus terkubur. Pada tahun 2024 nanti para tokoh NU harus bersaing dengan tokoh lainnya pada posisi start yang relatif sama kuat.
*****
Yang terakhir. Prabowo juga tidak terlepas dari pertimbangan pragmatisme sempit. Ulama yang tergabung dalam kelompok 212 sudah mengeluarkan rekomendasinya dan berharap didengar dan dilaksanakan oleh Prabowo dan partai koalisinya.
Namun, sehari menjelang pendaftaran di KPU, nama cawapres rujukan tidak juga muncul. Yang muncul malah Wagub DKI Sandiaga Uno. Sepertinya ulama 212 yang harus mendengarkan Prabowo, bukan sebaliknya.
Nama Sandiaga Uno ini muncul karena memang pertimbangan pragmatis sempit dari Prabowo dan partai koalisi pendukungnya. Bisa jadi, Prabowo sudah tidak mau lagi jor-joran mengeluarkan dana logistik karena merasa kesempatan untuk menang kali ini semakin menipis.
Untuk itu dia butuh orang yang mampu menyediakan logistik dan membayar mahar politik. Jadi, saran ulama memang penting, tapi dukungan logistik adalah yang utama. Dan Sandiaga Uno orangnya. Dia dipilih sebagai cawapres karena pertimbangan pragmatis sempit, yaitu logistik.
Sementara bagi Sandiaga Uno sendiri, yang semula tidak masuk dalam radar cawapres dan tiba-tiba berhasil menyeruak muncul sebagai cawapres, tetaplah pertimbangan pragmatis yang melatar belakangi keputusannya. Uno yang mempunyai uang berlebih berniat melakukan investasi di bidang politik. Dia sepertinya yakin bahwa dengan berinvestasi di bidang politik akan membawanya berhasil dalam hidup.
*****
Namun, dari semua pertimbangan pragmatis sempit yang mendasari keputusan para politisi, ada yang menarik dari sikap Prabowo dan Jokowi dalam memilih cawapresnya. Terkesan Prabowo tidak tersandera oleh itjima ulama yang memberi harga mati bahwa cawapres harus seorang ulama, dengan menyodorkan dua nama untuk dipilih.
Alih-alih mendengar dan menuruti itjima ulama, Prabowo dengan tenang, tegas dan tanpa rasa takut ditinggalkan oleh para ulama, memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres, yang berarti pasangan nasionalis -- nasionalis.
Sementara Jokowi yang justru bebas dari 'paksaan' rekomendasi ulama, malah terkesan tersandera oleh nuansa 'cawapres harus ulama'. Dan memang, karena alasan pragmatis sempit, Jokowi terpaksa mengalah dalam memilih cawapres. Dan pantas juga bila sebagian orang berpendapat Jokowi sebagai penakut dan telah tersandera.
Yang jelas, pertimbangan pragmatisme sempit yang cuma mementingkan diri dan kelompoknya masih menjadi penentu dalam memutuskan kepemimpinan nasional atau daerah. Untuk itu, meskipun para pilitikus membungkunsnya dengan kata-kata retorika, demi kepentingan bangsa dan negara. Demi keutuhan NKRI. Demi kemaslahatan umat, dan lain sebagainya. Sejatinya, mereka sedang berkata tidak jujur. Sekian.