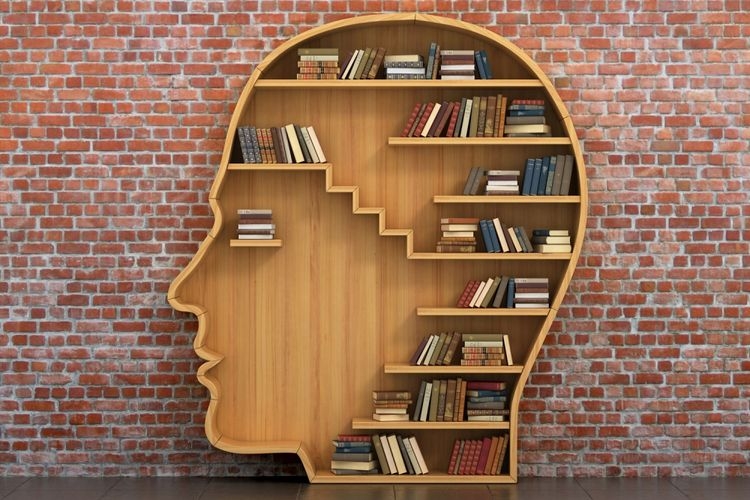Ketika literasi berjalan di tempat, dan gaungnya justru meninabobokan kita dalam ilusi kemajuan semu, apa yang perlu segera kita benahi?
Ini bukan hanya persoalan budaya minat baca. Sebagaimana dilaporkan Survei Literasi Kompas (13/8/2019), minat baca penduduk hampir merata pada semua kelompok umur (77,94 persen). Namun, menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, tingginya minat baca diiringi kesenjangan.
Kesenjangan itu terjadi di wilayah penduduk yang tinggal di perdesaan dan perkotaan. Juga penduduk yang berpendidikan tinggi memiliki minat baca lebih tinggi daripada berpendidikan jenjang rendah.
Kita tidak lantas merasa puas atas tingginya minat baca. Tantangan di depan masih menghadang. Lebih dari 55 persen murid Indonesia yang menamatkan sekolah hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP) mengalami buta huruf fungsional.
Mereka bisa membaca, namun tidak mampu menguasai materi yang dibaca. Hal ini disebabkan oleh pemangku kebijakan pendidikan terbelenggu ilusi kemajuan. Yang diraih cenderung kemajuan di permukaan. Kebutuhan akan pencitraan lebih dominan ketimbang kemajuan yang mendasar dan substansial.
Yang sedang kita alami, selain krisis pembelajaran, adalah krisis menalar sehat. Siswa di sekolah diajarkan mata pelajaran, namun tidak dilatih menalar. Mata pelajaran Matematika misalnya, dipelajari untuk sekadar bisa menyelesaikan soal berhitung.
Padahal, di balik kemampuan teknis menyelesaikan soal berhitung terdapat kemampuan menalar secara matematis. Logika menalar, juga pada mata pelajaran yang lain, belum mendapat porsi utama dalam proses pembelajaran.
Pelajaran Fisika yang dekat dengan keseharian siswa menjadi mata pelajaran asing. Teori dan rumus Fisika menjadi makhluk antahberantah yang datang dari luar planet. Pelajaran Fisika menjadi fakta sains yang jauh dan tak tersentuh oleh pengalaman keseharian.
Mengapa hal itu terjadi? Pelajaran yang diajarkan di sekolah nyaris tidak diberangkatkan dari kenyataan pengalaman. Sementara pengalaman keseharian yang dimiliki siswa sebagai modal belajar cukup melimpah. Modal belajar itu terbengkalai begitu saja.
Mengapa paku ujungnya lancip; mengapa minuman kopi yang panas dituang di atas lepek; mengapa lubang hidung kita tidak menghadap ke atas--semuanya merupakan fakta keseharian yang bisu. Guru jarang sekali membuka diskusi menggunakan pertanyaan yang "nakal" dan kritis sebagai pintu masuk untuk melatih nalar berpikir.

Nalar yang dirangkai dan berhasil ditemukan gatukan unsur-unsurnya akan membentuk sebuah konsep. Berpikir secara konseptual merupakan hasil dari proses menalar: mencermati, meneliti dan merangkai unsur-unsur kenyataan.
Konsep yang berhasil ditemukan siswa, sesederhana apapun bentuknya, dapat digunakan untuk memahami rumus baku ilmu pengetahuan. Namun, alangkah jauh tahap berpikir itu dari kenyataan proses belajar di sekolah.
Yang kita dapati adalah proses belajar yang instan. Guru langsung menjelaskan rumus, lalu siswa mengerjakan soal atau menjawab Lembar Kerja Siswa (LKS). Selesai.
Tidak heran, perilaku anak-anak generasi milenial saat mengendarai motor di jalanan belum mencerminkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Mereka mengalami krisis menalar.
Apa bahayanya? Rezim post-truth tidak dapat dianggap enteng karena mengapitalisasi emosionalitas informasi dan reproduksinya secara berulang-ulang melalui media sosial tanpa peduli pada fakta dan kebenaran, ungkap Raden Muhammad Mihrabi dalam Milenial dan Ancaman terhadap Demokrasi.
Mereka bukan hanya gagap dan terlunta-lunta memasuki industri 4.0. Lantas, apakah mereka dibiarkan saja menjadi tumbal akibat tidak sanggup menalar, berpikir kreatif dan inovatif, sehingga pada akhirnya harus tersisih dan tersingkir?
Sungguh, pendidikan kita menanggung dosa besar apabila merelakan hal itu benar-benar terjadi.[]
Jagalan, 130819