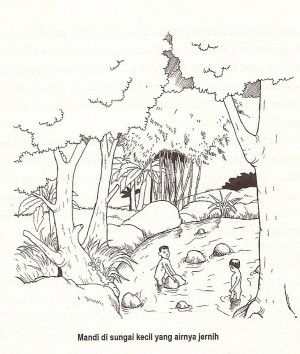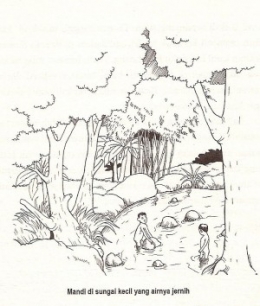Anda pikir cerita mudik hanya milik orang Jawa saja? Itu tidak benar. Kebiasaan mudik—kembali ke udik alias pulang kampung pada bulan Ramadan—juga dilakukan oleh orang-orang Batak di kampung saya sejak dulu.
Teman-teman dari kampung yang bersekolah maupun bekerja di Padangsidempuan, menjelang lebaran, pasti mudik, baik ke huta-huta di sekitar kota Padangsidempuan, yang jauhnya hanya sekitar puluhan kilometer, maupun ke Natal, Sibuhuan, atau Padangbolak yang jauhnya sampai ratusan kilometer. Mereka datang ke Padangsidempuan, ibukota kabupaten, untuk bersekolah di SMP, PGA, SMA, SMOA, atau universitas, atau bekerja.
Mereka yang bersekolah biasanya tinggal di rumah kerabatnya atau menyewa kamar (istilahnya mardagang alias menjadi anak dagang, anak kos-kosan). Karena dahulu sekolah libur pada bulan puasa, maka mereka kembali ke kampung sepanjang bulan itu. Yang pulang menjelang lebaran biasanya yang sudah bekerja, misalnya guru dan pegawai kantor, atau pedagang. Meski demikian, yang bersekolah agak jauh, misalnya ke Medan atau Padang, juga pulang menjelang lebaran, sadari mangalomang, alias sehari sebelum lebaran.
Kota Padangsidempuan dapat dijangkau dari Medan, Padang, atau Pekanbaru dengan bus Sibualbuali, Martimbang, ANS, ABS (singkatan Aek Batanggadis Sejati, usaha bus yang dibangun oleh orang-orang Mandailing. Bus ini kelak menjadi Antar Lintas Sumatra—ALS—hingga sekarang ini). Karena itu, mudik umum dilakukan dengan naik bus. Ada juga yang mudik dengan naik sepeda motor, terutama ketika sepeda motor sudah semakin populer, khususnya produk Jepang. Sebelumnya, sepeda motor banyak produksi Eropa, seperti Vespa, Cyrus, BMW, dan lain-lain.
Setelah dibangun jalan tembus dari Medan sampai Bandar-lampung, perjalanan mudik dari Jawa ke kampung saya semakin mudah. Pertama-tama pemudik naik kapal laut jalur Jakarta-Teluk Bayur atau Jakarta-Belawan selama dua hari satu malam, kemudian dilanjutkan dengan naik bus dari Padang atau dari Medan ke kampung saya sekitar 12 jam.
Bila lewat jalan darat, waktu yang ditempuh juga hampir sama, tapi enaknya kita bisa beristirahat di perjalanan. Ketika anak-anak masih kecil, langkah ini sering kami tempuh. Dari Jakarta kami menuju Pelabuhan Merak di ujung Pulau Jawa, kemudian naik feri menyeberang ke Sumatra. Dari Pelabuhan Bakahuni menanjak ke Bandar Lampung, kemudian ke Bukit Kemuning, Baturaja, Muaraenim, Tanjung Enim, Lahat, Bangko, Sarolangun, Sungai Dareh, Solok, Danau Singkarak, Bukittinggi, Lubuk Sikaping, Bonjol, Panti, Tapus, Rao, Muara Sipongi, Katanopan, Panyabungan, dan terakhir Padangsidempuan. Jika dari Jakarta berangkat malam, kami menginap di Lahat atau Lubuk Linggau, dan bisa jadi menginap lagi di Bukittinggi. Pernah saya hitung, perjalanan ini menempuh jarak 1.700 kilometer sekali jalan. Kalau sampai ke Medan tidak kurang daripada 2.000 kilometer.
Dalam acara mudik ini pernah sekali kami tabrakan di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Dahi anak saya sampai dijahit karena robek. Sekali pula menginap di tengah hutan, ketika terjadi longsor di Bukit Dua Baleh (Bukit Dua Belas). Untung kami bawa kompor dan perlengkapan memasak. Jadilah kami camping di tengah hutan itu. Untungnya, banyak pemudik yang juga terhambat, sehingga suasana pun menjadi seperti pasar saja. Banyak barang dagangan terpaksa digelar murah, seperti jeruk, markisa, semangka, dan lain lain. Kalau terlambat kan bisa busuk?
Alangkah nikmatnya perjalanan mudik bila dilakukan dengan santai sambil melihat-lihat pemandangan. Kalau lagi musim duku atau langsat, maka di daerah Sumatra Selatan, seperti Baturaja atau Muara Enim, kita dapat membelinya dengan harga murah. (Biasanya kami membeli oleh-oleh pada waktu balik ke Jakarta, karena buah macam duku berharga di Jakarta. Kami hindari membeli durian, karena seluruh isi mobil bisa bau. Lagi pula di Jakarta banyak durian). Walau menyetir, puasa jalan terus. Justru menyetir sembari berpuasa jauh lebih nikmat; tidak ada niat berhenti untuk makan. Berhenti hanya pada saat salat di masjid atau surau, yang banyak ditemui di sepanjang jalan. Kalau mengantuk, masjid dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat dan tidur sebentar.
Lain ceritanya kalau perjalanan mudik pas waktunya berbuka atau makan sahur. Kalau lagi di Bangko, kita dapat makan dendeng batokok (dendeng yang dibuat dengan cara ditumbuk dan tidak kering). Kalau pas di Bukittinggi berbuka dapat dilakukan di restoran yang berjejer-jejer di dekat Jam Gadang atau turun ke Pasar Bawah. Berbukanya bukan di rumah makan Padang seperti di Jawa atau tempat-tempat lain. Di Bukittinggi atau di Padang tak bakal kita temukan rumah makan Padang. Kalau tidak percaya, coba Anda cari sendiri.
Selain makanan, perjalanan mudik adalah kesempatan untuk menikmati alam. Pernah kami—saya dan anak-anak yang masih kecil—mandi di sungai yang airnya jernih di daerah Tanjung Enim. Mandi di sungai demikian merupakan kenikmatan tersendiri bagi orang Jakarta. Mana ada sungai di Jakarta yang airnya jernih? Pernah pula kami beristirahat di tengah Rimba Panti yang teduh atau di Bukit Dua Baleh, antara Rao dan Muara Sipongi di perbatasan Sumatra Barat dengan Sumatra Utara.
Perjalanan dua hari dua malam itu dilakukan setidaknya lima hari menjelang lebaran. Makin dekat lebaran makin padat jalanan. Di Pelabuhan Merak acapkali timbul kemacetan, namun begitu menginjak Pulau Sumatra jalanan jadi lancar. Mudik ke kampung dengan mobil semacam itu saya lakukan sewaktu orangtua masih ada, tenaga masih kuat, masih mampu menyetir sendiri, dan ekonomi belum terlalu mapan. Sesudah ekonomi keluarga membaik, mudik kami lakukan dengan naik pesawat terbang ke Medan. Dari Medan sudah tersedia mobil yang membawa kami ke kampung-halaman, lengkap dengan sopirnya. Waktu tempuhnya hanya sekitar 12 jam.
Paling bahagia bila kami sampai di kampung dengan selamat dan bisa berkumpul di rumah orangtua bersama saudara-saudara dari Medan. Kami masing-masing membawa keluarga. Rumah orangtua yang besar pun jadi tampak kecil, tapi justru di sinilah letak kebahagiaan itu. Terlebih ketika bersalam-salaman usai salat id. Bukan sungkeman, hanya bersalam-salaman. Pertama-tama kepada kedua orang-tua, kemudian ke yang lebih tua. Terkadang acara bersalam-salaman itu dibumbui dengan tangisan. Seperti Anda tahu, orang Batak itu amat emosional. Apalagi dalam suasana seperti itu. Seolah yang kuat menangislah yang paling tinggi derajat permintaan maafnya. Anak-anak acapkali bingung dibuatnya.
Kalau tangisan sudah reda, acara dilanjutkan dengan makkobar, berpidato, oleh semua anggota keluarga tanpa kecuali, meski kebanyakan marimom alias mengikut saja, terutama kaum perempuan. Inilah ciri khas keluarga Batak. Memohon maaf atas segala kesalahan, baik disengaja maupun tidak, sambil berharap ke depan senantiasa dalam lindungan Allah. Terakhir, ayah saya berpetuah. Dulu, sewaktu kecil, dalam hati saya menggerutu, kok lama betul petuahnya. Kini justru sayalah yang melakukan hal itu terhadap anak-anak saya. Kalau yang tua mendengarkan takzim, yang menengah mendengar dengan dahi mengerut dan pikirannya melayang entah ke mana, maka yang kecil terus saja gelisah menunggu kapan petuah berakhir agar bisa mendapat “salam tempel”.
Usai berpetuah hidangan pun dibuka. Ada ketupat ketan yang enak dipadu dengan rendang, gulai ayam, gulai pakis, sambal hati, dan makanan bersantan serta pedas lainnya. Tersusun pula kue-kue lebaran, mulai dari lemang yang rasa-nya sama dengan ketupat ketan, dodol, kembang loyang, karak koling, dan lain-lainnya.
Pulang ke Jakarta saya membawa semangat baru, meski jalan yang kami lalui tetap sama. Isi mobil juga sudah berbeda. Kalau semula isinya kain sarung (oleh-oleh paling berharga di kampung) ataumakanan pabrik, maka pulangnya berganti dengan oleh-oleh dari kampung. Jika berupa makanan, yang tak ketinggalan adalah ikan sale, ikan asin (terutama teri nasi alias teri Medan), atau penganan lebaran seperti lomang, alame, karak koling, kembang loyang, dan sebagainya. Nantinya, oleh-oleh itu ditambah lagi dengan berbagai macam makanan yang kami beli di sepanjang jalan. Di Bukittinggi, misalnya, kami akan membeli kerupuk sanjai, sedangkan di daerah Sumatra Selatan kami beli duku Palembang. Tentu bawaan yang baunya bisa bikin repot di perjalanan kami hindari, seperti durian, kuweni, atau ambacang. Ikan asin saja kerapkali kami paketkan agar kendaraan tidak bau.
Dalam perjalanan balik ke Jakarta, kami lebih santai lagi. Melalui Padangpanjang atau Solok, misalnya, kami sempatkan makan sate Padang di kota itu. Atau makan martabak Mesir yang justru ada di Baturaja, bukan di Kairo. Semua pengalaman itu amat berharga. Hati dan pikiran pun kembali jernih menatap lembaran lembaran baru kehidupan. ***