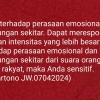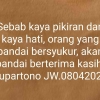Otot-otot Bapak bertonjolan. Meski bukan turunan orang berilmu digjaya, badan Bapak sering berkilau diterpa sinar matahari. Sehari-hari dia bekerja di dekat tungku yang panas. Terkadang bersama Wak Mijan, Kak Rauf dan aku. Tapi Wak Mijan dan Kak Rauf yang paling sering bersamanya.
Aku tak tahan uap panas dari tungku. Tak hanya keringat bersemburan, kulit juga memerah serupa kepiting rebus. Juga terasa amat payah mengokang naik turun dua kayu di dalam dua bambu besar itu. Dari selonsong bambu itulah kemudian menyembur-nyembur angin untuk menjaga nyala di dalam tungku.
Pak Ile Besi, demikian orang menyebut Bapak. Besi di belakang nama Bapak, sebenarnya gelar-gelaran saja. Tentu bukan karena tubuhnya sekeras besi. Melainkan dia seorang pandai besi tersohor di kampung kami.
Besi yang Bapak tempah menjadi arit untuk menyabit padi, atau bekal menakik getah karet, selalu lebih lama tajam dan mudah diasah ketika tumpul. Begitu juga perkakas dapur. Orang-orang sering memakai keahlian Bapak yang mumpuni itu. Kendati Mang Husni dan Kek Lubai berprofesi sama dengannya, bahkan tempat penempaan besi mereka tak terpaut jarak yang jauh, toh orang-orang lebih percaya pada keahlian Bapak.
“Itu, lho! Selain pisau buatan Pak Ile Besi lebih bagus, dia juga jujur mengatakan bahan pembuat pisau itu. Kalau dari besi murah, dia pasti kasih tahu. Apalagi kalau dari besi mahal, misal dari bekas rel kereta api.” Begitu sekali dua pelanggan membincangkan Bapak.
Aku juga heran, darimana Bapak mendapatkan besi bekas rel kereta api. Setahuku, rel kereta api berada jauh nun di kota besar.
“Rejeki tak akan lari ke mana, Arul! Kalau kita tetap berjuang, bekerja tanpa keluh-kesah, besi-besi akan datang sendiri ke sini,” kata Bapak kepadaku. Dia menghisap rokok dalam-dalam. Sebagai perokok, dia termasuk kelas berat. Bedanya dari perokok kelas berat lain, tubuh Bapak tetap tegap. Mungkin karena Bapak selalu berkeringat, dan tak selalu ambil pusing masalah yang saling membelit.
Seperti dua tahun belakangan, orderan mulai sepi, Bapak pun tak mengeluh. Orang-orang lebih suka membeli perkakas tajam buatan pabrik. Meskipun kualitasnya jauh kelas di bawah buatan Bapak, toh harganya sangat miring. Apalagi kemudian banyak yang terbuat dari stainless steel.
Ketimbang berkeluh kesah, Bapak mengasapi dapur dengan sekali-sekali mengolah sepetak kebun yang dulu terbengkalai di belakang rumah. Terkadang dia menanam bawang merah. Tapi ketika hujan menggila dan tanaman itu busuk, Bapak hanya menganggap itu cobaan. Bukan siksaan.
Pun ketika dia mencoba beternak kambing, dan salah seekor digasak harimau, tak ada keluhan apalagi umpatan dari mulut Bapak. Lain dengan Emak. Dia berkeluh-kesah sepanjang hari, bahkan sepertengah malam. Berulangkali kudengar Emak mengatakan ada yang salah dalam rumah kami. Mungkin di antara mereka pernah berbuat dosa yang sangat dimurkai Allah. Atau ada nazar yang belum tersampaikan, yang menjelma siksa saling bersipongang seolah kehidupan kami adalah tebing-tebing yang membelah ngarai.