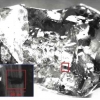(Tulisan ini saya dedikasikan untuk mahasiswa-mahasiswa Bridging Program FE UII)
Terlambat
Hari itu saya tidak melihat sosoknya. Dia tidak hadir tanpa memberi kabar. Saya tidak terlalu peduli dia datang atau tidak karena kehadirannya dapat dikatakan kurang berpengaruh pada dinamisasi kelas. Berbeda halnya jika mahasiswa yang tidak hadir adalah mahasiswa yang aktif dalam memberikan kontribusi pendapat, tanggapan, sanggahan atau solusi pada tiap-tiap diskusi kelas. Ketidakhadiran mahasiswa tipe ini sedikit banyak bisa mempengaruhi kedinamisasian kelas karena diskusi dan debat kemudian menjadi kurang ‘heboh’.
Setelah kelas usai, seorang mahasiswa menghampiri saya.
“Miss, Iwan tadi sebenarnya terlambat, tetapi malu untuk masuk kelas.”
“Kenapa malu?”, tanya saya.
“Entahlah. Tadi, dia kirim sms ke aku. Aku sudah sarankan, masuk saja, tetapi dia sungkan. Kalau aku jadi dia, aku akan masuk kelas. Lha wong sudah jauh-jauh datang, capek, setibanya di kampus malah tidak masuk kelas.”
Saya hanya menanggapi dengan tertawa. Di balik tawa itu, diam-diam muncul perasaan takjub.
Tradisi Malu
Keterlambatan adalah hal yang mungkin dianggap remeh temeh dan lazim bagi sebagian orang. Saking lazimnya, ini menjadi masalah klasik yang pasti dijumpai setiap dosen. Mahasiswa yang terlambat pun sering mengutarakan alasan-alasan yang juga klasik sekaligus basi, seperti tidak bisa bangun pagi, macet di jalan raya, bawa mobil, antri kamar mandi di kos, perut mules dan sejumlah alasan lainnya yang cenderung kekanakan. Seorang rekan dosen pernah dengan lemah lembut bertanya kepada seorang mahasiswa yang terlambat 30 menit “Mengapa kamu terlambat?”. Lalu si mahasiswa menjawab “Kan saya memang suka terlambat Bu..”.Sang dosen hanya “terkesima” mendengar jawaban itu. Saya yang mendengar cerita ini bergumam dalam hati The tragedy of zero shame!.
Coba kita sedikit menengok masyarakat Jepang yang sangat menjunjung tinggi budaya malu (shame culture). Dalam budaya malu itu, dunia begitu mengenal istilah hara-kiri atau orang Jepang lebih senang dengan istilah Seppuku yakni tindakan bunuh diri dengan menusuk perut menggunakan Tanto (pisau tajam berukuran 30-60 cm). Seppuku ini sangat populer di era Samurai. Seiring berkembangnya zaman, Seppuku sudah mulai tidak diterapkan secara resmi sejak tahun 1800an. Trennya pun berganti dengan pengunduran diri dari jabatan, tetapi tetap dalam semangat Seppuku. Sebagai contoh, pada tahun 2008 menteri pertanian Jepang, Seiichi Ota, mengundurkan diri atas permasalahan beras yang busuk. Pada tahun 2011, karena malu menerima banyak kecaman atas kinerja yang lamban dalam persoalan penanganan bencana gempa dan tsunami Maret 2011 serta krisis nuklir di Fukushima, Naoto Kan akhirnya mundur dari jabatan perdana menteri. Lalu masih banyak lagi kasus-kasus pelepasan jabatan karena MALU atas kegagalan atau ketidakmampuan menunaikan amanah yang telah dibebankan.
Bukan tradisi bunuh dirinya yang menjadi penekanan di sini, tetapi TRADISI MALU. Tradisi malu inilah yang dimiliki Iwan, mahasiswa pendiam yang lebih memilih untuk tidak hadir karena terlambat. Ia enggan masuk kelas karena malu telah melanggar aturan yang telah menjadi kesepakatan kelas. Ia mencoba untuk menghargai dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat yang mengenal tertib dan aturan, menghargai dosen dan rekan-rekannya yang telah mematuhi profesionalitas akademik dan secara umum menghargai kelas sebagai suatu unit sosial formal akademik yang bersistem dan bernorma. Iwan memang telah melakukan pelanggaran, yaitu terlambat, tetapi hal yang membuat saya takjub adalah perasaan malunya.
Iwan bukan satu-satunya mahasiswa yang menganut tradisi malu. Seorang rekan dosen bercerita tentang mahasiswanya yang juga malu. Lima menit pertama di kelas dosen ini adalah pengecekan kehadiran mahasiswa. Jika mahasiswa belum hadir pada lima menit pertama, maka sudah pasti dianggap tidak hadir karena proses tanda tangan kehadiran telah selesai. Hari itu, dua orang mahasiswa datang terlambat, kira-kira dua puluh menit setelah kelas dimulai. Mahasiswa terlambat 1 langsung membubuhkan tanda tangan di daftar hadir yang kebetulan sedang beredar. Lalu mahasiswa ini menawarkan daftar hadir pada temannya, mahasiswa terlambat 2.
“Eh kamu belum tanda tangan nih”, menawarkan daftar hadir ke mahasiswa terlambat 2 untuk ditandatangani.
“Aku nggak berhak tanda tangan, karena aku terlambat.”
Jawaban mahasiswa ini sungguh bukan jawaban yang biasa mengingat daftar hadir sedang beredar atau belum kembali ke tangan dosen dan setiap mahasiswa yang terlambat biasanya pasti memanfaatkan momen ini. Hal luar biasa lainnya yang membuat si dosen takjub adalah mahasiswa terlambat 2 yang menolak untuk tanda tangan ini adalah seorang mantan ketua geng tawuran yang cukup tenar di kota Yogyakarta. Jadi, Iwan dan mahasiswa ini sangat menjunjung tinggi tradisi MALU!
Apakah bangsa kita sebenarnya menganut tradisi malu juga? Tentu saja.Jawabannya bisa sangat relatif. Bangsa kita juga mengenal budaya malu tetapi kualitasnya mungkin tidak setinggi Jepang. Contohnya sederhana saja - stereotip “suka ngaret” atau “jam karet” masih terjaga baik dalam alam pikir masyarakat kita. Buktinya saat seorang mengeluh karena seorang rekan belum tiba pada waktu yang telah dijanjikan, atau mengeluh karena sebuah acara tidak juga dimulai padahal sudah lewat dari waktu semestinya, maka dengan serta merta akan muncul celetukan “biasalah…jam karet. Bukan orang Indonesia kalau enggak ngaret” atau “Indonesia kan emang jam karet”. Stereotip ini pun menjadi makin kokoh karena dinaungi oleh sebuah sistem informal, yakni “sistem yang penuh toleransi”. Pertama, masyarakat nampak cenderung makin permisif dan maklum dalam hal pelanggaran norma, artinya kurang adanya sanksi sosial terhadap keterlambatan. Contoh dalam dunia akademik, seringkali ditemui beberapa dosen memperkenankan mahasiswa yang terlambat untuk masuk kelas mengikuti perkuliahan atau tidak menjatuhkan sanksi bagi yang terlambat. Mungkin terlalu repot dan bukan hal penting untuk memperkarakan keterlambatan di saat dosen sedang sibuk dan konsentrasi menerangkan materi. Akan tetapi, budaya abai semacam ini cukup sukses membentuk karakter anak bangsa menjadi tidak punya rasa malu karena datang terlambat. Kedua, secara kolektif dan tidak disadari kita kadangkala berniat melanggar kesepakatan perjanjian dengan cara mengulur-ulur waktu untuk tiba di tempat perjanjian dengan dalih ‘jangan buang-buang waktu dengan menunggu karena toh mulai acara pasti molor’. Bayangkan saja, jika Anda, teman Anda, dan beberapa orang di luar sana bersikap skeptis dengan dalih seperti ini, maka sebuah acara betul-betul dimulai tidak tepat waktu. Contoh, jika mahasiswa berpikir ‘sepuluh menit lagi saya akan masuk kelas karena dosen pasti terlambat’, dan di saat yang bersamaan dosen juga berpikir ‘sepuluh menit lagi saya akan ke kelas, toh mahasiswa saya juga sering terlambat’. Maka jadi nyatalah Indonesia sebuah negeri jam karet.
Reformasi Diri
Untuk mengubah kondisi ini memang tidak mudah tetapi tidak mustahil. Dalam lingkup kelas Bridging Program, banyak cara telah saya terapkan. Beberapa cara gagal dan mulai ditinggalkan. Cara pertama, mahasiswa yang terlambat akan melalui tahapan ‘pengolahan’ dulu. Jadi, sebelum dipersilahkan duduk, mahasiswa diberi semacam instruksi yang harus dilakukan. Instruksinya adalah bernyanyi. Mahasiswa yang melalui tahap ‘pengolahan’ ini diharapkan merasa malu karena menerima hukuman bernyanyi atas kesalahan terlambat. Sekali lagi, MEREKA AKAN MERASA MALU. Akan tetapi, nampaknya ‘bernyanyi’ pun kurang efektif memunculkan rasa malu sekaligus mengurangi angka keterlambatan. Beberapa mahasiswa yang terlambat bahkan tidak sedikitpun merasa malu. Jika pun ada rasa malu itu, sifatnya hanya tentatif. Esok dan seterusnya, mereka akan terlambat lagi. Namun, ada juga mahasiswa yang malu untuk bernyanyi. Meskipun malu, mereka tetap saja datang terlambat. Ini yang kemudian membuat saya berpikir, ‘nampaknya mereka lebih malu bernyanyi daripada malu melakukan pelanggaran’. Kasus yang berbeda bahkan ada mahasiswa yang bersedia dan merasa senang bernyanyi karena memiliki kualitas vokal yang bagus. Tujuan dari hukuman bernyanyi tentu menjadi gagal. Lambat laun, instruksi mulai berkembang tidak hanya sebatas bernyanyi – mulai dari kultum dan membaca surat pendek. Ini pun kurang efektif karena kelemahannya, saya menjadi sibuk mengurusi ‘acara pengolahan’.
Hingga suatu hari, pada puncak keputusasaan saya, saya mengajak seisi kelas untuk bersama-sama membaca surat Al Fatihah. Ini adalah cara kedua. Tujuannya tentu mendoakan mahasiswa-mahasiswa yang sering terlambat semoga mendapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah, Allah berkehendak lain – mereka masih saja terlambat. Saya harus cari cara lain lagi.
Tahun berikutnya, penerapan cara ketiga, yakni zero tolerance. Mahasiswa yang tidak datang tepat waktu, dipersilahkan menutup pintu dari luar, artinya keterlambatan harus dibayar dengan larangan mengikuti perkuliahan. Namun, cara ini ternyata memiliki kelemahan. Mahasiswa yang sering terlambat jadi ketinggalan pelajaran. Presentase kehadiran menjadi rendah dan ini pasti mempengaruhi nilai yang akhirnya berpengaruh pada sertifikasi sistem manajemen mutu fakultas ISO 9001:2008. Dengan pertimbangan ini, tutup pintu dari luar pun akhirnya tak diterapkan lagi pada semester berikutnya, diganti dengan “toleransi tiga kali terlambat, empat kali dan seterusnya dianggap tidak hadir”.
Ini cara keempat yang juga tidak luput dari kelemahan. Awalnya saya bisa memberi tanda merah pada nama mahasiswa yang tercantum di daftar hadir – mahasiswa yang terlambat tentunya. Tetapi lama kelamaan, saya merasa terganggu karena mereka yang terlambat seringkali datang di saat saya sedang berbicara di forum kelas. Mana mungkin saya mengingat si Paijo sudah terlambat dua kali, si Painem baru terlambat satu kali, si Partoko sudah terlambat berkali-kali dan seterusnya. Organ otak saya tidak semaksimal itu untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus – wilayah Broca dan Wernicke dalam otak sedang sibuk-sibuknya bekerja mengolah bahasa dan di saat yang sama otak belahan yang lain harus melakukan searching data mahasiswa, mengingat-ingat si mahasiswa ini sudah berapa kali terlambat sekaligus membuka lembaran daftar hadir dan memberi tanda khusus pada nama yang terlambat. Ini melelahkan.
Cara keempat ini selanjutnya diganti dengan cara kelima. Mekanismenya adalah seorang mahasiswa mengecek kehadiran pada menit-menit awal sambil memberi pertanyaan sederhana pada tiap nama yang dipanggil. Pertanyaan sederhana yang diajukan hanya membutuhkan jawaban singkat. Mengecek kehadiran ini dilakukan secara bergantian oleh mahasiswa yang berbeda-beda tiap harinya. Akan tetapi, kadangkala saya langsung begitu saja mengecek kehadiran, bila aktivitas kelas dirancang cukup padat hari itu. Setelah pengecekan kehadiran selesai, maka siapapun yang hadir setelahnya akan dianggap tidak hadir. Tentu praktik cek kehadiran di menit-menit awal ini pun tidak luput dari pertentangan. Mereka yang terlambat berdalih tentang waktu tempuh yang tidak singkat menuju kelas yang berada di lantai 3 (kebetulan kelas saya selalu berlangsung di lantai 3). Mengingat tingkat efektivitasnya, cara kelima ini cukup banyak diterapkan beberapa dosen bridging program.
Sebenarnya ada satu cara yang yang menjadi prinsip utama yang dipegang teguh oleh dosen-dosen Bridging Program - Lisanul hal afshahu min lisanil maqal, artinya keteladanan itu lebih kuat (pengaruhnya) daripada ucapan. Prinsip ini kemudian dijabarkan lagi menjadi
You cannot teach what you want
You cannot teach what you know
But you can teach who you are
Pada praktiknya (perihal keterlambatan) setiap dosen Bridging Program selalu berusaha tiba tepat waktu di kelas dengan harapan menjadi teladan dan diikuti oleh mahasiswa.
Terlepas dari cara-cara di atas, langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk kondisi yang lebih baik adalah pertama, mulai dari diri sendiri utuk belajar malu melanggar aturan alias malu datang terlambat ke kelas. Kedua, tumbuhkan kembali kontrol sosial dengan mulai belajar untuk mengoreksi pelanggaran yang dilakukan orang lain/teman. Jika rasa malu sudah terinternalisasi dalam diri, maka itu menjadi bagian dari definisi integritas yang tinggi. Sebaliknya, jika rasa malu itu tidak dimiliki, maka itu adalah isyarat akan integritas yang cacat. Terakhir, apakah kita tidak akan malu jika kemudian dinamai bangsa yang tidak tahu malu?
***