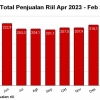Adalah sebuah keniscayaan kita adalah mahluk sosial. Namun apa jadinya jika kesosialan kita diwadahi sosial media. Menjadi manusia abad 21, kita akan selalu merasa connected (terhubung). Masih jelas slogan Nokia di awal 90 dulu, Nokia 'Connecting People'. Dan seperti sebuah lompatan, makna 'connecting' ini pun menjadi pondasi kokoh dan luas saat muncul sosial media di awal tahun 2000-an.
Kita semakin terhubung satu sama lain. Jarak dan waktu bukan lagi masalah untuk interaksi sosial. Dulu chat dengan SMS yang berbiaya relatif mahal, kata yang difikir, disusun dan diketik harus padat makna. Kini hal sebaliknya yang terjadi. Hal-hal yang paling sepele pun bisa kita share di Facebook, Twitter, Instagram, dll. Jiwa sosial kita bisa diwadahi dengan baik, bahkan over-baik.
Sosial media menjadi wadah insting partisipatif kita. Di jaman pra sejarah dulu, para pemburu akan membagi makanannya dengan kelompoknya. Jaman kolonial dan perang dunia, tiap negara pun berbagi rampasan perang dan tanah dengan warga negaranya. Kini, di sosmed insting parsipatif untuk selalu update informasi dan peristiwa menjadi konsumsi kita sehari-hari. Kita tidak ingin kudet, kuper atau bahkan katrok dalam chat grup di WhatsApp misalnya.
Gabungan jiwa sosial dan insting partisipatif ini pun memiliki 'efek samping' yaitu budaya entrainment. Jangan keliru membacanya entertainment. Entrainment sendiri berasal dari kata train. Kata ini berarti menyambung, mengikuti dan merunut. Namun untuk lebih kontekstual, mungkin bisa saya frame dengan kata 'mengekor'.
Kenapa mengekor? Karena info, berita, obrolan, posting, dll dari sosmed biasanya akan dishare/di-retweet/reblog/regram dsb dari satu sumber/akun/situs. Kita yang banyaknya user sosmed pun hanya mengekor berita/info yang sudah ada di lini masa kita. Baik itu berita yang menurut perasaan kita positif atau negatif, kita akan lihat atau bahkan dibaca lengkap.
Terlibatnya unsur perasaan dalam mengekor satu berita/info di sosmed ini pun menyulut viralitas. Kita pun tak sungkan akan berbagi berita dengan komunitas/grup/chat grup kita. Saat berita itu sedih, kita pun men-reply perasaan sendu. Begitupun saat berita yang kita bagi begitu menyulut amarah, tak ayal umpatan pun dilontarkan. Tweet/post/share kita pun bisa berisi makian/sinisme/amarah. Karena anonimitas yang kta punyai. (Baca artikel saya: Memahami Identitasi Diri di Sosial Media)

Dan yang terakhir 'lempar jumrah' pun disimbolisasi dengan aksi lanjutan. Ada sumber yang menggambarkan aksi 411 = tawaf, 212 = wukuf. Dan terakhir, dengan 'provokatif' digambarkanlah 'lempar Jumrah'. Makna implisit yang tertanam di benak kita adalah jika Ahok tidak juga ditahan, maka aktifitas 'lempar batu' hendak diperbuat?
Ada emosi yang diselipkan dari berita/info yang disebarkan di sosial media. Karena mungkin oknum dibalik ini semua faham entrainment perasaan akan muncul. Saat hal ini muncul, cukup mudah menjadikan tiap user agen partisipatif yang secara sosial bergerak aktif di sosmed. Saat sifat sosial dipadu insting komunal membungkus isu SARA yang banyak beredar, mudah bagi kita untuk diadu domba. (Baca artikel saya: Divide et Impera ala Sosial Media)
Dan semua refleksi fenomena sosial di dunia Gen Z ini harusnya sudah kita fahami bersama. Karena bukan lagi wacana kita bijak ber-sosmed. Sedang ke depannya, ada generasi Z bangsa Indonesia yang sebaiknya faham manfaat, tantangan, dan keburukan dari dunia teknologi saat ini. Sudah waktunya kita harus banyak belajar dari negara Barat yang sudah menciptakan sosmed. Dan kini mereka pun belajar 'menjinakkan' sosmed.
Saatnya kita pun banyak tahu, membaca dan mewacanakan literasi digital.
Referensi: Exploring Entrainment Pattern of Human Emotion in Social Media, He, Zheng, Zeng, Luo dan Zang 2016.
Salam,
Wollongong, 07 Desember 2016
11:30 pm