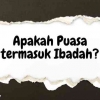PENDIDIKAN FILSAFAT PERSPEKTIF ISLAM
[caption id="attachment_175796" align="aligncenter" width="300" caption=" Filsafat. Sumber: Google. http://sociotalker.files.wordpress.com/2012/01/ghazali.gif"][/caption]
BAB I
PENDAHULUAN
Epistemologi, atau teori pengetahuan, membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat sebagai usaha untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan dengan buah pemikiran yang lainnya. Atau dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Karena ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Untuk tujuan inilah, agar tidak terjadi kekacauan antara pengertian “ilmu” (science) dan “pengetahuan” (knowledge), maka kita mempergunakan istilah “ilmu” untuk “ilmu pengetahuan.” Seperti halnya Irfani, adalah model metodologi yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Berbeda dengan epistemolkogi bayani yang bersifat eksoteris, maka epistemologi irfani lebih esoteris (batin) teks.
Dari uraian diatas penulis akan memaparkan epistimologi irfani dengan memberikan rumusan masalahnya sebagai berikut:
1.Bagaimanakah Sumber Asal Epistemologi Irfani?
2.Bagaimanakah perkembangan Epistemologi Irfani?
3.Bagaimanakah metodologi epistemologi irfani?
4.Bagaimana makna Zahir & Batin dalam epistemologi irfani?
5.Bagaimana konsep Nubuwah & Walayah dalam epistemologi irfani?
BAB I
PEMBAHASAN
A.Pengertian Irfani
Kata Irfan dari kata dasar bahasa Arab arafa semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan.[1] Tetapi ia berbeda dengan ilmu (`ilm). Irfan atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman (experience), sedang ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi (naql) atau rasionalitas (aql). Karena itu, secara terminologis, irfan bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakekat oleh Tuhan kepada hamba-Nya (kasyf) setelah adanya olah ruhani (riyadlah) yang dilakukan atas dasar cinta (love).[2] Kebalikan dari epistemologi bayani, sasaran bidik irfani adalah aspek esoterik syareat, apa yang ada dibalik teks.
B.Sumber Asal Irfani.
1.Irfan Islam berasal dari sumber Persia dan Majusi,
Seperti yang disampaikan Dozy dan Thoulk. Alasannya, sejumlah besar orang-orang Majusi di Iran utara tetap memeluk agama mereka setelah penaklukan Islam dan banyak tokoh sufi yang berasal dari daerah Khurasan. Disamping itu, sebagian pendiri aliran-aliran sufi berasal dari kelompok orang Majusi, seperti Ma`ruf al-Kharki (w. 815 M) dan Bayazid Busthami (w. 877 M).[3]
2. Irfan berasal dari sumber-sumber Kristen,
Pendapat dari Von Kramer, Ignaz Goldziher, Nicholson, Asin Palacios dan O’lery. Alasannya, (1) adanya interaksi antara orang-orang Arab dan kaum Nasrani pada masa Jahiliyah maupun zaman Islam. (2) adanya segi-segi kesamaan antara kehidupan para Sufis, dalam soal ajaran, tata cara melatih jiwa (riyadah) dan mengasingkan diri (khalwat), dengan kehidupan Yesus dan ajarannya, juga dengan para rahib dalam soal pakaian dan cara bersembahyang.[4]
3. Irfan ditimba dari India,
Seperti pendapat Horten dan Hartman. Alasannya, (1) kemunculan dan penyebaran irfan (tasawuf) pertama kali adalah di Khurasan, (2) kebanyakan dari para sufi angkatan pertama bukan dari kalangan Arab, seperti Ibrahim ibn Adham (w. 782 M), Syaqiq al-Balkh (w. 810 M) dan Yahya ibn Muadz (w. 871 M). (3) Pada masa sebelum Islam, Turkistan adalah pusat agama dan kebudayaan Timur serta Barat. Mereka memberi warna mistisisme lama ketika memeluk Islam. (4) Konsep dan metode tasawuf seperti keluasan hati dan pemakaian tasbih adalah praktek-praktek dari India.[5]
6.Irfan berasal dari sumber-sumber Yunani,
Khususnya neoplatonisme dan Hermes, seperti disampaikan O’leary dan Nicholson. Alasannya, ‘Theologi Aristoteles’ yang merupakan paduan antara sistem Porphiry dan Proclus telah dikenal baik dalam filsafat Islam. Kenyataannya, Dzun al-Nun al-Misri (796-861 M), seorang tokoh sufisme dikenal sebagai filosof dan pengikut sains hellenistik.[6] Jabiri agaknya termasuk kelompok ini. Menurutnya, irfan diadopsi dari ajaran Hermes, sedang pengambilan dari teks-teks al-Qur`an lebih dikarenakan tendensi politik. Sebagai contoh, istilah maqâmat yang secara lafdzi dan maknawi diambil dari al-Qur`an (QS. Al-Fusilat : 164), identik dengan konsep Hermes tentang mi`raj, yakni kenaikan jiwa manusia setelah berpisah dengan raga untuk menyatu dengan Tuhan. Memang ada kata maqâmat dalam al-Qur`an tetapi dimaksudkan sebagai ungkapan tentang pelaksanaan hak-hak Tuhan dengan segenap usaha dan niat yang benar, bukan dalam arti tingkatan atau tahapan seperti dalam istilah al-Hujwiri (w. 1077 M).[7]
C. Perkembangan Irfani.
1.Fase pembibitan,
Terjadi pada abad pertama hijriyah. Pada masa ini, apa yang disebut irfan baru ada dalam bentuk laku zuhûd (askestisme). Kenyataan ini, menurut Thabathabai, karena para tokoh sufisme yang dikenal sebagai orang-orang suci tidak berbicara tentang irfan secara terbuka, meski mengakui bahwa mereka dididik dalam spiritualisme oleh Rasul atau para sahabat. Karakter askestisme periode ini adalah (1) berdasarkan ajaran al-Qur`an dan sunnah, yakni menjauhi hal-hal duniawi demi meraih pahala dan menjaga diri dari neraka. (2) bersifat praktis, tanpa ada perhatian untuk menyusun teori atas praktek-praktek yang dilakukan. (3) Motivasi zuhûdnya adalah rasa takut, yakni rasa takut yang muncul dari landasan amal keagamaan secara sungguh-sungguh.[8]
2.Fase kelahiran
Terjadi pada abad kedua hijrah. Pada masa ini, beberapa tokoh sufisme mulai berbicara terbuka tentang irfan. Karya-karya tentang irfan juga mulai ditulis, diawali Ri`ayat Huquq Allah karya Hasan Basri (642-728 M) yang dianggap sebagai tulisan pertama tentang irfan, kemudian diikuti Mishbah al-Syari’ah karya Fudlail ibn Iyadl (w. 803 M). Laku askestisme juga berubah. Jika awalnya dilakukan atas dasar takut dan mengharap pahala, dalam periode ini, di tangan Rabiah Adawiyah (w. 801 M), zuhûd dilakukan atas dasar cinta kepada Tuhan, bebas dari rasa takut atau harapan mendapat pahala. Menurut Nicholson, zuhûd ini adalah model prilaku irfan yang paling dini atau irfan periode awal.[9]
3.Fase pertumbuhan
Terjadi abad 3-4 hijrah. Sejak awal abad ke-3 H, para tokoh sufisme mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku, sehingga sufisme menjadi ilmu moral keagamaan (akhlaq). Pembahasan masalah ini, lebih lanjut, mendorong mereka untuk membahas soal pengetahuan intuitif berikut sarana dan metodenya, tentang Dzat Tuhan dan hubungan-Nya dengan manusia atau hubungan manusia dengan-Nya, yang kemudian disusul perbincangan tentang fana’ (ecstasy), khususnya oleh Abu Yazid Bustami (w. 877 M) dan hulul (imanensi Tuhan dalam manusia) oleh alHallaj (858-913 M). Dari perbincangan-perbincangan seperti ini kemudian tumbuh pengetahuan irfan, seperti al-Lum`ah fî al-Tashawûf yang ditulis Abu Nashr Sarraj al-Thusi ( w. 988 M) dan Quthb al-Qulûb karya Abu Thalib al-Makki (w. 996 M).[10] Bersamaan itu, sejumlah tokoh sufisme, seperti Sirri al-Saqathi (w. 867 M), Abu Said al-Kharraz (w. 895 M), dan Junaid al-Baghdadi (w. 910 M), juga mempunyai banyak murid. Menurut Taftazani, inilah cikal bakal bagi terbentuknya tarikat-tarikat sufi dalam Islam, di mana sang murid menempuh pelajaran dasarnya secara formal dalam suatu majlis. Dalam tariqat ini, sang murid mempelajari tata tertib irfan, teori maupun prakteknya.[11] Dengan demikian, pada fase ini, irfan telah mengkaji soal moral, tingkah laku dan peningkatannya, pengenalan intuitif langsung pada Tuhan, kefanaan dalam Realitas Mutlak, dan pencapaian kebahagiaan, disamping penggunaan simbol-simbol dalam pengungkapan hakekat realitas-realitas yang dicapai irfan, seperti yang dilakukan Dzun al-Nun al-Misri (796-861 M). Namun demikian, kecenderungan umum fase ini masih pada psiko-moral, belum pada tingkat metafisis. Ide-ide metafisis yang ada belum terungkap secara jelas. Karena itu, Nicholson menyatakan, dari segi teoritis dan praktis, kaum sufis fase ini telah merancang suatu sistem yang sempurna tentang irfan, Akan tetapi, mereka bukan filosof dan mereka sedikit menaruh perhatian terhadap problem-problem metafisika.[12]
4.fase puncak
Terjadi pada abad ke-5 H. Pada periode ini irfan mencapai masa gemilang. Banyak pribadi besar yang lahir dan menulis tentang irfan, antara lain, Said Abu Khair (w. 1048 M) yang menulis Ruba`iyat, Ibn Utsman al-Hujwiri (w. 1077 M) menulis Kasyf al-Mahjûb, dan Abdullah alAnshari (w. 1088 M) menulis Manâzil al-Sâ`irîn, salah satu buku terpenting dalam irfan. Puncaknya al-Ghazali (w. 1111 M) menulis Ihya’ Ulum al-Dîn yang menyelaraskan tasawuf dan fiqh (irfan dan bayani).[13] Menurut Nicholson dan TJ. de Boer, ditangan al-Ghazali, irfan menjadi jalan yang jelas karakternya untuk mencapai pengenalan serta kefanaan dalam tauhid dan kebahagiaan.[14]
5.Fase spesikasi
Terjadi abad ke- 6 & 7 H. Berkat pengaruh pribadi al-Ghazli yang besar, irfan menjadi semakin dikenal dan berkembang dalam masyarakat Islam. Ini memberi peluang bagi tokoh sufis untuk mengembangkan tarikat-tarikat dalam rangka mendidik murid mereka, seperti yang dilakukan A. Rifai (w. 1174 M), Abd al-Qadir al-Jailani (w. 1253 M), Abu al-Syadlili (w. 1258 M), Abu Abbas al-Mursi (w. 1287 M), dan Ibn Athaillah al-Iskandari (w. 1309 M). Namun, bersamaan dengan itu, disisi lain, muncul pula tokoh-tokoh yang berusaha memadukan irfan dengan filsafat, khususnya neo-platonisme, seperti yang dilakukan Suhrawardi (w. 1191 M) lewat karyanya yang terkenal, Hikmah alIsyraq, Ibn Arabi (w. 1240 M), Umar ibn Faridl (w. 1234 M), dan Ibn Sab`in alMursi (w. 1270 M). Mereka banyak memiliki teori mendalam tentang jiwa, moral, pengetahuan, wujud dan lainnya yang sangat bernilai bagi kajian irfan dan filsafat berikutnya.[15] Bahkan, jika tokoh sebelumnya hanya menulis tentang bagaimana persiapan menerima pengetahuan, menurut Mehdi H. Yazdi,[16] Suhrawardi dan Ibn Arabi diatas justru yang mempelopori penulisan pengalaman mistik yang disebut pengetahuan irfan. Dengan demikian, pada fase ini, secara epistemologis, irfan telah terpecah (terspesifikasi) dalam dua aliran. (1) Irfan sunni menurut istilah Taftazani yang cenderung pada perilaku praktis (etika) dalam bentuk tarikat-tarikat, (2) irfan teoritis yang didominasi pemikiran filsafat. Disamping itu, dalam pandangan Jabiri, ditambah aliran kebatinan yang didominasi aspek mistik.[17] Meski demikian, menurut Muthahari, irfan praktis tetap tidak sama dengan etika dan irfan teoris berbeda dengan filsafat.
6.Fase kemunduran
Terjadi sejak abad ke-8 H. Sejak abad itu, irfan tidak mengalami perkembangan berarti, bahkan justru mengalami kemunduran. Para tokohnya lebih cenderung pada pemberian komentar dan ikhtisar atas karyakarya terdahulu, dan lebih menekankan bentuk ritus dan formalisme, yang terkadang mendorong mereka menyimpang dari susbtansi ajarannya sendiri. Para pengikut memang semakin bertambah, tetapi disana tidak muncul pribadi unggul yang mencapai kedudukan ruhaniyah cukup terhormat seperti pada pendahulunya.[18]
C. Metode Irfan.
Pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks seperti bayani, juga tidak atas rasio seperti burhani, tetapi pada kasyf, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks atau keruntutan logika, tetapi dengan olah ruhani, dimana dengan kesucian hati, Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsep atau masuk dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada oang lain. Dengan demikian, sebagaimana disampaikan Suhrawardi, secara metodologis, pengetahuan ruhani setidaknya diperoleh melalui tiga tahapan, (1) persiapan, (2) penerimaan, (3) pengungkapan, baik dengan lisan atau tulisan.[19]
1.Tahap persiapan
Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan (kasyf), seseorang yang biasanya disebut sâlik (penempuh jalan spiritual) harus menyelesaikan jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Para tokoh berbeda pendapat tentang jumlah jenjang yang harus dilalui.[20] Namun, setidaknya, ada tujuh tahapan yang harus dijalani, yang semua ini berangkat dari tingkatan yang paling dasar menuju pada tingkatan puncak dimana saat itu qalbu (hati) telah menjadi netral dan jernih sehingga siap menerima limpahan pengetahuan. Antara lain, taubat, wara`, zuhud, faqir dan seterusnya.
2.Tahap penerimaan
Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam jenjang spiritual, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara illuminatif atau noetic. Dalam kajian filsafat Mehdi Yazdi, pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak (kasyf), sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri (musyahadah) sebagai objek yang diketahui. Namun, realitas kesadaran dan realitas yang disadari tersebut, karena bukan objek eksternal, keduanya bukan sesuatu yang berbeda tetapi merupakan eksistensi yang sama, sehingga objek yang diketahui tidak lain adalah kesadaran yang mengetahui itu sendiri, begitu pula sebaliknya (ittihad).[21]Sedemikian rupa, sehingga dalam perspektif epistemologis, pengetahuan irfani ini tidak diperoleh melalui representasi atau data-data indera apapun, bahkan objek eksternal sama sekali tidak berfungsi dalam pembentukan gagasan umum pengetahuan ini. Pengetahuan ini justru terbentuk melalui univikasi eksistensial yang oleh Mehdi Yazdi disebut ‘ilmu huduri’ atau pengetahuan swaobjek (self-object-knowledge), atau jika dalam teori permainan.Dalam pandangan Suhrawardi, pengetahuan ini melalui empat tahapan, yakni persiapan, penerimaan, pembentukan konsep dalam pikiran, dan penuangan dalam bentuk tulisan. bahasa (language game) Wittgenstein, pengetahuan irfani ini tidak lain adalah bahasa ‘wujud’ itu sendiri.[22]
3.Tahap pengungkapan.
Ini merupakan tahap terakhir dari proses pencapaian pengetahuan irfani, dimana pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain, lewat ucapan atau tulisan. Namun demikian, karena pengetahuan irfani bukan masuk tatanan konsepsi dan representasi tetapi terkait dengan kesatuan simpleks kehadiran Tuhan dalam diri dan kehadiran diri dalam Tuhan, sehingga tidak bisa dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini bisa diungkapkan. Beberapa pengkaji masalah irfan atau mistik membagi pengetahuan ini dalam beberapa tingkat,[23]
(a) Pengetahuan tak terkatakan,
(b) Pengetahuan irfan atau mistisisme,
(c) Pengetahuan metasisisme yang terbagi dalam dua bagian;
- Oleh orang ketiga tetapi masih dalam satu tradisi dengan yang bersangkutan (orang Islam menjelaskan pengalaman mistik orang Islam yang lain).
- Oleh orang ketiga dan dari tradisi yang berbeda (orang Islam menjadi pengalaman mistik dari tokoh mistik non-muslim).
D. Konsep Zahir & Batin Dalam Epistemologi Irfani.
Sesuai dengan sasaran bidik irfan yang esoterik, isu sentral irfan adalah zahir & batin, bukan sebagai konsep yang berlawanan tetapi sebagai pasangan. Menurut Muhasibi (w. 857 M), al-Ghazali (w. 1111 M), Ibn Arabi (w. 1240 M), juga para sufis yang lain, teks keagamaan (al-Qur`an dan hadits) tidak hanya mengandung apa yang tersurat (zahir) tetapi juga apa yang tersirat (batin). Aspek zahir teks adalah bacaannya (tilawah) sedang aspek batinnya adalah takwilnya.[24] Jika dianalogikan dengan bayani, konsep zahir-batin ini tidak berbeda dengan lafat-makna. Bedanya, dalam epistemologi bayani, seseorang berangkat dari lafat menuju makna; sedang dalam irfani, seseorang justru berangkat dari makna menuju lafat, dari batin menuju zahir, atau dalam bahasa al-Ghazali, makna sebagai ashl, sedang lafat mengikuti makna (sebagai furu`).
Pendapat zahir-batin diatas didasarkan, pertama, pada al-Qur`an, QS. Luqman: 20, al-An`am: 120 dan khususnya QS. al-Hadid: 3, yang sekaligus digunakan sebagai dasar pijakan metafisisnya. Kedua, hadis Rasul, ‘Tidak ada satu ayatpun dalam al-Qur`an kecuali disana mengandung aspek zahir dan batin, dan setiap huruf mempunyai had (batas) dan matla` (tempat terbit).[25] Ketiga, pernyataan Imam Ali ibn Abi Thalib (w. 660 M). Menurut Ali ra, al-Qur`an mengandung empat dimensi, zahir, batin, had dan matla`. Aspek zahir al-Qur`an adalah tilawah, aspek batinnya adalah pemahaman, aspek had-nya ketentuan halal dan haram, dan matla`nya adalah apa yang dikehendaki Tuhan atas hamba-Nya.[26]
Menurut Jabiri, makna batin ini, pertama, diungkapkan dengan cara apa yang disebut sebagai I`tibâr atau qiyas irfani. Yakni analogi makna batin yang ditangkap dalam kasyf kepada makna zahir yang ada dalam teks.[27]Sebagai contoh, qiyas yang dilakukan kaum Syiah yang menyakini keunggulan keluarga Imam Ali ra. atas QS. Al-Rahman, 19-22. “Dia membiarkan dua lautan mengalir dan bertemu; diantara keduanya ada batas yang tidak terlampaui dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan”. Dalam hal ini, Ali dan Fatimah dinisbatkan pada dua lautan, Muhammad saw dinisbatkan pada batas (barzah), sedang Hasan & Husein dinisbatkan pada mutiara dan marjan.[28] Barzah = Muhammad , Dua lautan = Ali/Fatimah Dua laut Ali/Fatimah Mutiara & Marjan Hasan/Husein Contoh lain adalah qiyas yang dilakukan al-Qusyairi atas ayat yang sama. Menurutnya,[29] dalam hati ini ada dua lautan, yakni khauf (takut) dan raja’ (harapan), dan dari sana keluar mutiara dan marjan, yakni ahwâl al-shufiyah dan lathâif al-mutawaliyah. Diantara keduanya ada batas yang tak terlampaui, yakni pengawan Tuhan atas ini dan itu. Artinya, konsep sufisme tentang khauf dan raja’ dinisbatkan pada kata ‘bahrain’ (dua lautan), sedang ahwâl dan lathâif dinisbatkan pada mutiara dan marjan. Khauf/ Raja’ via Dua lautan Ahwâl/ Lathaif Mutiara/ Marjan Dengan demikian, qiyas irfani ini tidak sama dengan qiyas bayani atau silogisme.
Qiyas irfani disini berusaha menyesuaikan konsep yang telah ada atau pengetahuan yang diperoleh lewat kasyf dengan teks. Ibn Arabi menyatakan bahwa zahir al-Qur`an adalah tafsir, aspek batinnya adalah takwil, had-nya adalah batas kemampuan pemahaman dan matla`nya adalah puncak pendakian hamba dimana ia menyaksikan Tuhan. Namun, Jabiri menyangsikan otensitas hadis dan tafsir ini, karena dibagian lain, Ibn Arabi menyatakan bahwa ia memperoleh hadis tersebut lewat kasyf. Tidak mengikuti rantai perawian sebagaimana dalam ilmu hadis.
Dengan kata lain, seperti dikatakan al-Ghazali diatas, zahir teks dijadikan furû’ (cabang) sedang konsep atau pengetahuan kasyf sebagai ashl (pokok). Karena itu, qiyas irfani atau I`tibâr tidak memerlukan persyaratan illat atau pertalian antara lafat dan makna (qarînah lafdziyah `an ma`nawiyah) sebagaimana yang ada dalam qiyas bayani, tetapi hanya berpedoman pada isyarat (petunjuk batin).[30]Metode analogi seperti diatas, menurut al-Jabiri,[31]juga dikenal dalam pemikiran di Barat, yakni dalam aliran filsafat esoterik, yang disebut analogi intuitif. Namun, dalam analogi filsafat esoterik, perbandingan bukan dialakukan atas dasar kesamaan tetapi karena adanya keterpengaruhan. Bagi al-Jabiri, dengan tidak adanya kesetaraan atau kesamaan diantara dua hal yang dianalogikan berarti analogi (qiyas) tersebut telah jatuh.[32] Karena itu, dan ini merupakan kesalahan alJabiri, ia menggunakan metode analogi Barat tersebut untuk menganalisa irfani Islam, sehingga menganggap bahwa pengetahuan irfani yang dibangun diantas dasar qiyas bukan sesuatu yang luar biasa tetapi hanya kreatifitas akal yang didasarkan atas imajinasi. Lebih lanjut, irfan akhirnya hanya merupakan filsafatisasi mitos-mitos, yang tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pembangunan masyarakat.[33] Padahal, irfani Islam sama sekali berbeda dengan mistik di Barat, meski dibeberapa bagian ada kesamaan.
Irfani lebih berkaitan dengan kebersihan jiwa, rasa dan kayakinan hati, sementara mistik Barat kurang berkaitan dengan semua itu dan lebih positifistik. Karena itu, menggunakan alat ukur mistik Barat untuk menganalisa irfan Islam, sesungguhnya, tidak berbeda dengan mengukur rasa kepedasan cabe dengan melihat warna kulitnya. Tidak akan mencapai hakekat yang sebenarnya. Kedua, pengetahuan kasyf diungkapkan lewat apa yang disebut dengan syathahât. Namun, berbeda dengan qiyas irfani yang dijelaskan secara sadar dan dikaitkan dengan teks, syathahât ini sama sekali tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Syathahât lebih merupakan ungkapan lisan tentang perasaan (al-wijdan) karena limpahan pengetahuan langsung dari sumbernya dan dibarengi dengan pengakuan, seperti ungkapan ‘Maha Besar Aku’ dari Abu Yazid Bustami (w. 877 M), atau ‘Ana al-Haqq’ (Aku adalah Tuhan) dari al-Hallaj (w. 913 M).[34] Ungkapan-ungkapan seperti itu, keluar saat seseorang mengalami suatu pengalaman intuitif yang sangat mendalam, sehingga sering tidak sesuai dengan kaidah teologis maupun epistemologis tertentu; sehingga, karena itu pula, ia sering dihujat dan dinilai menyimpang dari ajaran Islam yang baku. Meski demikian, secara umum, syathahât sebenarnya diterima dikalangan sufisme, meskipun dikalangan sufisme sunni yang membatasi diri pada aturan syareat, dengan syarat bahwa syathahât tersebut harus di takwilkan, yakni ungkapannya harus terlebih dahulu dikembalikan pada makna zahir teks.[35] Artinya, syathahat tidak boleh diungkapkan secara ‘liar’ dan berseberangan dengan ketentuan syareat yang ada. Persoalannya, di mana hakekat qiyas irfani, takwil atau syathah sufisme diatas, sebab apa yang diungkapkan para tokoh sufis tersebut ternyata tidak sama, meski mereka sama-sama mengklaim telah mengalami atau mendapat pengetahuan langsung dari realitas mutlak. Mengikuti al-Jabiri, hakekat takwil dan syathah tidak terletak pada makna umumnya atau universalitasnya melainkan justru pada makna temporal atau subjektifitasnya. Sebab, takwil atau syathah tidak lain adalah pemaknaan atau pemahaman atas realitas yang ditangkap saat kasyf, dan itu pasti berbeda diantara masing-masing orang, sesuai dengan kualitas jiwa dan pengalaman sosial budaya yang menyertainya.[36]
E. Nubuwah & Walayah.
Sejalan dengan konsep zahir dan batin, muncul konsep nubuwah dan walayah. Nubuwah adalah padanan dari konsep zahir sedang walayah pasangan dari batin. Keduanya berkaitan dengan otoritas religius yang diberikan Tuhan atas diri seseorang. Bedanya, kenabian ditandai dengan wahyu dan mukjizat serta diperoleh dengan tanpa usaha, sedang kewalian ditandai dengan karamah serta irfan, dan diperoleh lewat usaha (iktisab). Ibn Arabi menyebut kedua konsep tersebut dengan konsep ‘kenabian umum’ dan ‘kenabian khusus’. Kenabian umum adalah kewalian yang berhubungan dengan ilham, makrifat atau irfan, sedang kenabian khusus adalah nabi yang dibekali syareat dan ketentuan hukum-hukum formal.[37] Kedua posisi tersebut mempunyai derajat yang berbeda. Kenabian lebih tinggi dibanding kewalian, dimana puncak kewalian adalah awal dari kenabian. Pengalaman mukâsyafat (kasyf) yang bisa dialami pada permulaan kenabian adalah puncak perjalanan spiritual kewalian. Sementara itu, dalam pemikiran madzhab Syiah, walayah dikaitkan dengan konsep imamah yang punya otoritas religius dan politik. Bagi kaum Syiah, karena risalah yang diberikan kepada para Rasul telah selesai dengan wafatnya Muhammad saw, maka para imam-lah yang bertugas menjaga dan meneruskan misi syareat dengan menerima ilham yang tidak lain adalah hakekat rilasah kenabian. Karena itu, keberadaan imamah adalah sesuatu yang mutlak karena mereka adalah nubuwah al-bathiniyah, nubuwah al-haqiqah yang menjadi salah satu rukun agama. Karena itu pula, menurut Imam Ja`far Shadiq (702-757 M), kedudukan para imam Syiah adalah sama dengan kedudukan para nabi ghair al-mursalîn (nabi yang tidak dibekali syareat tersendiri), bahkan dengan para rasul. Bedanya, Rasul boleh menikah dengan lebih dari empat wanita sementara para imam tidak boleh.[38]
BAB III
PENUTUP
Berbeda dengan pengetahuan pada umumnya yang digali dari objek eksternal (korespondesi), pengetahuan irfani digali dari diri sendiri, tepatnya dari realitas kesadaran diri yang dalam bahasa tasawuf disebut kasyf. Objeknya tidak lain hanya bersifat immaterial dan essensial, bersifat (self-objectknowledge), sehingga apa yang disebut sebagai objektivitas objek tidak lain bersifat analitis dan terwujudkan dalam tindakan mengetahuai itu sendiri. Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan :
- Adapun sumber asal mula irfani adalah Pertama, menganggap bahwa irfan Islam berasal dari sumber Persia dan Majusi, seperti yang disampaikan Dozy dan Thoulk. Kedua, irfan berasal dari sumber-sumber Kristen, seperti dikatakan Von Kramer, Ignaz Goldziher, Nicholson, Asin Palacios dan O’lery. Ketiga, irfan ditimba dari India, seperti pendapat Horten dan Hartman. Keempat, irfan berasal dari sumber-sumber Yunani, khususnya neoplatonisme dan Hermes, seperti disampaikan O’leary dan Nicholson.
- Perkembangan Irfani adalah, Pertama, fase pembibitan, terjadi pada abad pertama hijriyah. Pada masa ini, apa yang disebut irfan baru ada dalam bentuk laku zuhûd (askestisme). Kedua, fase kelahiran, terjadi pada abad kedua hijrah. Pada masa ini, beberapa tokoh sufisme mulai berbicara terbuka tentang irfan. Ketiga, fase pertumbuhan, terjadi abad 3-4 hijrah. Sejak awal abad ke-3 H, para tokoh sufisme mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku, sehingga sufisme menjadi ilmu moral keagamaan (akhlâq). Keempat, fase puncak, terjadi pada abad ke-5 H. Pada periode ini irfan mencapai masa gemilang. Kelima, fase spesikasi, terjadi abad ke- 6 & 7 H. Berkat pengaruh pribadi al-Ghazli yang besar, irfan menjadi semakin dikenal dan berkembang dalam masyarakat Islam. Keenam, fase kemunduran, terjadi sejak abad ke-8 H. Sejak abad itu, irfan tidak mengalami perkembangan berarti, bahkan justru mengalami kemunduran
- Sedangkan metode irfan dibagi menjadi tiga yaitu :
(1) persiapan,
(2) penerimaan,
(3) pengungkapan, baik dengan lisan atau tulisan.
- Aspek zahir teks adalah bacaannya (tilawah) sedang aspek batinnya adalah takwilnya.
- Nubuwah adalah padanan dari konsep zahir sedang walayah pasangan dari batin. Keduanya berkaitan dengan otoritas religius yang diberikan Tuhan atas diri seseorang.
DAFTAR RUJUKAN
1.Husein Nashr, Tasawuf Dulu & Sekarang, terj. Abd Hadi, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.
2.Horald Titus, Persoalan-Persoalan Filsafat, terj. HM Rasjidi, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.
3.Martin Lings, Membedah Tasawuf, terj. Djohan Effendi, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
4.Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Hudhuri, terj. Ahsin M, Bandung, Mizan, 1994.
5.Nicholson, al- Shufiyah fî al-Islâm, terj. Nurudin Syaribah, Kairo, tp. 1951
6.Nicholson, Mistik dalam Islam, terj. Tim Bumi Aksara, akarta, Bumi Aksara, 1998.
7.Parvis Morewedge, Islamic Philosophy and Mysticism, New York, Caravan Books, 1981.
8.Simuh, Tasawuf & Perkembangannya dalam Islam, Jakarta, Rajawali Press, 1997.
9.Thabathabai, ‘Pengantar’, dalam Muthahhari, Menapak Jalan Spiritual, terj. Nasrullah, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995.
10.Wittgenstein, Philosophical Investigations, terj. Anscombe, New York, 1968.
[1] Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 251.
[2] Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Hudhuri, terj. Ahsin M, (Bandung, Mizan, 1994), h. 47
[3] Yazid Busthami, Farid al-Din al-Attar, Warisan Para Aulia, terj. Anas Muhyidin, (Bandung, Pustaka, 1994). h.48
[4]Nicholson, al- Shufiyah fî al-Islâm, terj. Nurudin Syaribah, (Kairo, tp. 1951), h. 12
[5]Al-Attar, Warisan Para Aulia, terj. Anas Muhyidin, (Bandung, Pustaka, 1994). H. 56
[6]Abu al-Wafa Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani, (Bandung, Pustaka, 1985), 29-30.
[7] Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 372
[8] Abu al-Wafa Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani, (Bandung, Pustaka, 1985), h. 29-30.
[9] Abu al-Wafa Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani, (Bandung, Pustaka, 1985), h. 112.
[10]; Simuh, Tasawuf & Perkembangannya dalam Islam, (Jakarta, Rajawali Press, 1997), h. 103-158.
[11] Abu al-Wafa Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani, (Bandung, Pustaka, 1985), 29-30.
[12] Nicholson, al- Shufiyah fî al-Islâm, terj. Nurudin Syaribah, (Kairo, tp. 1951), xvi
[13] Muthahhari, Menapak Jalan Spiritual, terj. Nasrullah, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1995), h.46-48.
[14] Nicholson, al- Shufiyah fî al-Islâm, terj. Nurudin Syaribah, (Kairo, tp. 1951), h. 84
[15] Abu al-Wafa Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani, (Bandung, Pustaka, 1985), h. 29-30.
[16] Thabathabai, Pengantar dalam Muthahhari, Menapak Jalan Spiritual, terj. Nasrullah, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1995), h.47
[17] Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 269.
[18]Abu al-Wafa Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani, (Bandung, Pustaka, 1985), 29-30.
[19] Dalam pandangan Suhrawardi, pengetahuan ini melalui empat tahapan, yakni persiapan, penerimaan, pembentukan konsep dalam pikiran, dan penuangan dalam bentuk tulisan. Lihat Parvis Morewedge, Islamic Philosophy and Mysticism, (New York, Caravan Books, 1981), h. 177.
[20] Husein Nashr, Tasawuf Dulu & Sekarang, terj. Abd Hadi, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994), h. 89-96
[21]Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Hudhuri, terj. Ahsin M, (Bandung, Mizan, 1994), h. 51-53.
[22] Wittgenstein, Philosophical Investigations, terj. Anscombe, (New York, 1968), h. 247.
[23]Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Hudhuri, terj. Ahsin M, (Bandung, Mizan, 1994), h. 245-268.
[24] Ibn Arabi, Tafsîr Ibn Arabi II, (Kairo, Bulaq, 1867), h. 2.
[25] Ibn Arabi, Tafsîr Ibn Arabi II, (Kairo, Bulaq, 1867), h. 2.
[26] Abu Abdullah al-Sulami, ‘Haqiq al-Tafsir’ dalam Ali Zighur (edit), al-Tafsir al-Shufi
li al-Qur`an, (Beirut, Dar al-Andalus, 1979), h. 3.
[27]Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 295
[28]Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 306.
[29] Ibid, 107. Al-Qusyairi, Lathâif al-Isyârât, III, edit oleh Ibrahim Basyuni, (Kairo, al- Haiah al-Misriah, 1981), h. 507.
[30]Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 274.
[31]Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993)h. 376.
[32] I Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 377.
[33]Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993) h. 378.
[34]Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993) h. 288.
[35]Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 290.
[36] Al-Jabiri, Bunyah al-Aql al-Arabi, (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 281.
[37] Ibn Arabi, Futuhât al-Makiyah, III, (Beirut, Dar Shadir, tt), h. 101.
[38] Muthahhari, Falsafah Kenabian, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1991).